Perempuan penghayat tersingkir pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Ruang hidup mereka makin tergerus bahkan menghilang.
Oleh: Shinta Maharani | Republikasi dari Tempo
BERBICARA di hadapan ratusan peserta konferensi internasional penghayat kepercayaan, Atik Manggala mengisahkan kerusakan lahan pertanian miliknya. Sejak tiga tahun lalu, sawah Atik tercemar limbah semen proyek strategis nasional (PSN) jalan tol akses Yogyakarta-Bawean. Lahan itu berjarak 100 meter dari lokasi pengolahan semen jalan tol Yogya-Bawean yang dibangun sepanjang 75,12 kilometer.
Endapan semen proyek jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta, Temanggung, Magelang, Borobudur, Banyurejo, dan Ambarawa itu bercampur dengan air, masuk ke parit-parit yang mengaliri sawah Atik di Kecamatan Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Limbah semen itu, kata Atik, mengganggu kesuburan tanah dan tanaman di lahan seluas 2.000 meter yang dia kelola dengan sistem pertanian organik.
“Keserakahan manusia merusak alam dan menyebabkan bencana,” kata Atik di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.Kerusakan itu juga mengganggu ritual mereka. Bagi Atik yang menjadi penghayat kepercayaan, tanah berkaitan erat dengan laku spiritualisme. Mereka menjalankan berbagai ritual Jawa, misalnya labuh sawah, ritual masyarakat Jawa yang menandai awal musim tanam padi. “Ritual ini merupakan wujud syukur, keselamatan, dan melestarikan kearifan lokal,” ujar perempuan penganut Ngesti Kasampurnan ini.
Ngesti Kasampurnan merupakan penghayat kepercayaan yang mempraktikkan hidup selaras dengan alam semesta. Atik merupakan pendiri Sri Tumuwuh, gabungan komunitas penghayat kepercayaan yang diundang sebagai pembicara dalam INTERSECTORAL Collaboration for Indigenous Religions Rumah Bersama atau kolaborasi lintas sektor konferensi internasional ketujuh bertajuk “Ecocracy: Power to the People, Justice for All Planetary Community”. Istilah ekokrasi dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh, dan untuk alam seisinya.
Dalam kepercayaan leluhur Jawa, kerusakan itu mengganggu ekosistem seluruh kehidupan. Dia mencontohkan, lumpur semen telah memusnahkan berbagai mikroorganisme, ulat, dan semua hewan penyokong ekosistem. Dampaknya, hasil panen menjadi tak maksimal, bahkan gagal. Atik terpaksa bersiasat dengan cara berganti-ganti pola tanam pertanian, misalnya dari padi ke singkong. “Menanam singkong tak butuh banyak air seperti padi,” ujarnya.
Selain di Yogyakarta, PSN pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, berdampak terhadap perempuan komunitas penghayat kepercayaan. Salah satu warga Dataran Tinggi Dieng, Rizal Setiawan, mengatakan proyek geotermal mencemari mata air di Dusun Pawuhan dan Ngandan-andan.
Padahal, di Dataran Tinggi Dieng, kata dia, terdapat penganut penghayat kepercayaan yang menjalankan serangkaian ritual di mata air. Ritual itu disebut “merti kali” sebagai wujud rasa syukur atas limpahan air. “Semenjak pembangunan PSN, debit air berkurang dan kualitasnya jadi buruk. Rasa air jadi asin,” tuturnya.
Dampak proyek strategis nasional geotermal terhadap penghayat kepercayaan terekam dalam riset Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM. Riset itu melibatkan 14 komunitas penghayat kepercayaan yang tinggal di sekitar pegunungan.
Beberapa di antaranya di Dieng, Jawa Tengah; Gunung Wai Sano, Nusa Tenggara Timur; Gunung Poco Leok, NTT; Gunung Talang, Sumatera Barat; Gunung Mandailing, Sumatera Utara; Sinjai, Sulawesi Selatan; dan Toraja, Sulawesi Selatan. Riset itu tertuang dalam buku berjudul Energi Hijau Vs Pelestarian Ruang Hidup Cerita Warga Melawan Geotermal.
Peneliti CRCS, Martha Hesty Susilowati, menyebutkan proyek geotermal menggusur ruang hidup masyarakat adat. Dia mencontohkan sejumlah tempat sakral untuk ritual penghayat kepercayaan hilang karena proyek tersebut. Bagi komunitas penghayat kepercayaan, kata Martha, tanah menjadi ruang hidup yang menghubungkan ritual, budaya, dan berbagai aktivitas mereka. “Tanah lekat dengan identitas dan spiritualitas,” ucap penulis buku Energi Hijau Vs Pelestarian Ruang Hidup Cerita Warga Melawan Geotermal itu.
Ketua Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya UGM Samsul Maarif mengatakan PSN geotermal meminggirkan kelompok rentan, salah satunya perempuan penghayat. Proyek itu membuat komunitas penghayat kepercayaan kehilangan lahan dan terusir. Situasi itu, kata Samsul, menggambarkan pemerintah anti-demokrasi karena tidak mau mendengarkan suara kelompok rentan. “Demokrasi hanya jadi tipuan dan legitimasi untuk meminggirkan kelompok rentan,” katanya.
Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Dahlia Madani menjelaskan, sejak 2020-2025, terdapat 80 kasus menyangkut konflik sumber daya alam, agraria, dan tata ruang yang dilaporkan masyarakat. Sebanyak 42 di antaranya merupakan konflik sumber daya alam. Dahlia menyebutkan sejumlah wilayah dengan konflik sumber daya alam paling parah, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Komnas Perempuan menerima delapan aduan konflik akibat pembangunan PSN energi panas bumi di NTT. Temuan Komnas menunjukkan adanya intimidasi oleh aparat pemerintah, aparat keamanan, serta tentara bersenjata yang menimbulkan rasa takut, ancaman kriminalisasi, dan pengucilan sosial bagi mereka yang menolak ataupun menyetujui untuk menjual tanah di sana.
Komisioner Komnas Perempuan telah bertemu dengan Keuskupan Agung Ende yang menyatakan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling menderita akibat proyek tersebut. Sejak awal Januari 2025, Uskup Ende telah mengeluarkan pernyataan menolak proyek geotermal di wilayah kegembalaannya karena dianggap merusak hubungan sosial, budaya, dan lingkungan.
Komisioner Komnas Perempuan Deden Sukendar mengatakan, di NTT, perempuan adat tercerabut dari kehidupan spiritualnya karena PSN geotermal. Dia mencontohkan, proyek itu menghancurkan rumah adat di Desa Wae Sano, Manggarai Barat. Proyek yang sama juga berdampak bagi perempuan masyarakat adat di Gunung Poco Leok.
Menurut dia, proyek itu menutup harapan hidup masyarakat adat karena sumber mata air mereka tercemar, altar persembahan untuk ritual hilang, serta terjadi polarisasi warga yang menolak dan setuju.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Harison Mocodampis belum memberikan tanggapan ihwal dampak proyek strategis nasional terhadap perempuan penghayat dengan alasan sedang cuti. Dia hanya memberikan nomor kontak kepala kantor wilayah di sejumlah daerah yang terdapat proyek tersebut, antara lain NTT.
Manajer Humas PT Jogjasolo Marga Makmur Rahmat Jesiman Putra, pengelola jalan tol Solo-Yogyakarta, belum memberikan tanggapan ketika dimintai konfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp. “Saya sedang di perjalanan,” ucapnya.







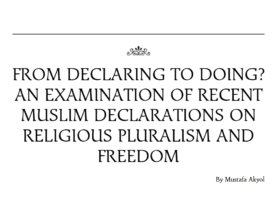



Leave a Reply