
Vikry Reinaldo Paais
Semua orang menginginkan kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi bagaimana jika kebebasan itu saling menafikan dan tidak bisa didamaikan?
Pertanyaan ini menjadi pemantik bagi Sharma untuk mengeksplorasi, atau lebih tepatnya memproblematisasi, fenomena kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Hasil telisikannya itu ia tuangkan dalam buku berjudul Problematizing Religious Freedom (2011) yang ia jabarkan menjadi dua bagian. Pada Bagian I, Sharma memulai upaya problematisasi ini dengan menjelaskan pengertian agama secara komprehensif dalam konteks historis dan legal. Dalam konteks historis, ia meminjam ide dua tokoh yang cukup terkenal: Wilfred Cantwell Smith, seorang teolog dan sejarawan yang lahir pada 1916 di Toronto; dan Williard Oxtoby, seorang profesor perbandingan agama asal Amerika Serikat yang lahir pada 1933. Smith menekankan bahwa agama adalah fenomena manusia yang dapat dijelaskan secara historis maupun geografis. Dengan kata lain, agama merupakan kreasi manusia yang senantiasa berkaitan dengan kebudayaan manusia. Sementara itu, Oxtoby menyoroti kecenderungan kekristenan sebagai pemasok model agama bagi agama atau kepercayaan di luarnya. Penekanan pada kredo dan institusionalisasi agama ala Kristen memperuncing pembedaan antara sakral dan profan—yang tidak mesti ada di agama atau kepercayaan lain. Meminjam pemikiran kedua akademisi agama tersebut, Sharma ingin menunjukkan secara historis bagaimana agama dikonstruksi.
Dalam konteks legal, memahami agama berarti memahaminya dalam kerangka negara. Bagi Sharma, pertanyaan krusialnya adalah, “Apa itu agama menurut perspektif negara?” Dalam asas Perjanjian Westphalia dikenal istilah cuius regio, eius religio, yang artinya ‘dia yang menguasai wilayah, memilih agama’. Asas ini seolah menunjukkan dominasi negara terhadap agama—bagaimanapun juga agama selalu dipraktikkan dalam wilayah suatu negara. Karenanya, untuk kepentingan praktikal maupun legal, agama selalu mengalami pendefinisian oleh negara. Pendefinisian ini tak terelakkan, karena—salah satunya—berkaitan dengan cara kerja hukum itu sendiri. Hakim, pengacara, dan petugas hukum memerlukan secara konkrit penjelasan definisi agama sebagai pijakan untuk menimbang atau memutuskan perkara. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja jika tidak ada kepastian mengenai definisinya?
Dengan kata lain, definisi agama tidaklah final. Agama tidak memiliki definisi yang disepakati oleh para akademisi, bahkan oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, konsep KBB yang dirumuskan senantiasa terikat dengan konsep agama yang dianut perumusnya (hlm.17). Beranjak dari titik tolak tersebut, pada Bagian II Sharma mengeksplorasi lebih lanjut tarik ulur KBB melalui beberapa studi kasus, salah satunya konversi agama.
Memahami “Kompleksitas” Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Ekspresi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan sering diasumsikan secara sederhana sebagai kebebasan untuk memilih agama apa pun yang diinginkan atau bahkan tidak memilih sama sekali. Akan tetapi, bagi Sharma, ekspresi ini juga mencakup kebebasan untuk meyakini ajaran agama atau kepercayaan lain meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran dan konsep agama yang dianut. Misalnya, seseorang berhak dan bebas mengakui Tuhan lain meski agama yang ia peluk adalah monoteistik. Individu yang mengekspresikan kebebasan beragama semacam ini juga harus dilindungi haknya. Dengan kata lain, yang menjadi subjek hukum adalah individu, bukan agamanya.
Beranjak dari pemahaman tersebut, Sharma memaparkan tiga pendekatan dalam memahami kompleksitas kebebasan beragama: derajat, jenis, dan pembatasan kebebasan beragama. Derajat kebebasan beragama mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang setara. Kita bisa menyebutnya sebagai kebebasan kolektif, sebuah kebebasan yang didasarkan pada nilai-nilai kolektif yang diakui. Akan tetapi dalam praktiknya, derajat kebebasan beragama tiap individu ini berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia misalnya, umat Kristen akan kesulitan memiliki lahan dan membangun tempat ibadah di daerah tertentu meskipun tidak ada larangan baginya untuk menjalankan ibadah. Dengan kata lain, meskipun sama-sama memiliki kebebasan beragama, ada umat tertentu yang dibatasi ekspresi haknya dikarenakan agama yang ia anut.
Derajat kebebasan beragama ini bertaut erat dengan jenis kebebasan beragama itu sendiri. Seperti yang disinggung sebelumnya, kebebasan beragama juga bisa berarti kebebasan untuk tidak memilih salah satu agama. Namun, setidaknya dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama “jenis itu” belum diakui bahkan mendapat stigma keras—jangankan tidak beragama, pengakuan dan pemenuhan kebebasan beragama di luar enam agama yang difasilitasi pemerintah saja masih jauh panggang dari api. Pada muaranya, diskursus jenis dan derajat kebebasan beragama ini akan mengarahkan kita pada soal pembatasan kebebasan beragama. Sejauh mana kebebasan agama dapat (atau perlu) dibatasi? Sharma menggarisbawahi bahwa pembatasan ini sangat dipengaruhi oleh otoritas keagamaan. Ia mencontohkan setidaknya ada tiga otoritas yang memiliki pengaruh kuat yaitu otoritas politik, lembaga keagamaan, dan orang tua. Ketiganya berpengaruh pada pembatasan kebebasan beragama dalam skala dan tingkatan yang berbeda.
Menurut Sharma, makna “kebebasan” dalam kebebasan beragama menyiratkan, “tidak adanya keharusan, paksaan, atau kendala dalam pilihan atau tindakan (hlm. 75).” Dengan kata lain, jika seorang individu dibatasi hanya dapat menjalankan satu agama, maka dia tentu tidak bebas. Dari diskursus tersebut, Sharma menggarisbawahi bahwa ada dua bentuk atau pengertian kebebasan beragama. Pertama, kebebasan untuk berpindah agama dan kedua, kebebasan untuk mempraktikkan suatu agama tanpa harus berpindah agama (akses tak berbatas).
Konversi Agama: Kebebasan Beragama dari Perspektif Agama-Agama
Kebebasan beragama seringkali dipertentangkan dengan klaim kebenaran agama. Doktrin agama kerap bersifat mengikat: meninggalkan agama berarti penyimpangan atau pembangkangan terhadap Tuhan. Namun, paradigma ini sebenarnya tidak eksis pada semua agama. Sharma mendedikasikan enam dari delapan bab pada Bagian II buku ini untuk menelusuri dan menganalisis corak serta ragam kemungkinan kebebasan beragama dari berbagai agama—dari agama Abrahamik yang cenderung bercorak misionaris, agama “Timur” nonmisionaris, hingga agama leluhur di Amerika Utara. Sharma menyimpulkan bahwa sikap terhadap konversi agama ini sangat ditentukan oleh esensi, ajaran, serta latar belakang agama tersebut.
Sharma, meminjam kategorisasi Max Mueller, mengelompokkan beberapa agama tersebut dalam dua kelompok besar: agama misionaris dan nonmisionaris. Keduanya dibedakan berdasarkan sejarah proses dan cara penyebaran, serta ideologi yang tersirat. Islam, Kristen, dan Buddha dikelompokkan sebagai agama misionaris—yang bercorak universal ataupun penyiaran agama secara masif; sedangkan sisanya sebagai agama nonmisionaris. Sebagian besar agama nonmisionaris merupakan agama yang eksistensinya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku, etnik, ataupun agama nasional—misalnya agama Yahudi (Yudaisme) dan Hindu. Karenanya, perpindahan agama bukan merupakan tujuan atau karakter utamanya. Akan tetapi, menurut Sharma, ini bukan berarti agama-agama nonmisionaris tersebut menolak konversi secara mentah-mentah.
Pada akhirnya, sikap netral, pro, ataupun antikonversi tidak terlepas dari ajaran dan interpretasi terhadap nilai-nilai agama. Dengan demikian, muncul pertanyaan: jika hak untuk konversi adalah elemen dalam kebebasan beragama, apakah penyiaran agama (proselytizing) malah mempersulit kebebasan beragama?
Pada Bab 10, Sharma menjawab keraguan ini dengan beberapa pernyataan lugas, di antaranya: ajakan atau bujukan untuk masuk ke suatu agama (proselytizing) adalah bentuk dari religious violence (kekerasan agama). Tindakan itu berkontribusi pada pelecehan kebebasan beragama karena mendemonstrasikan inferioritas terhadap pihak lain dan mempromosikan misrepresentasi agama. Sharma menambahkan, penyebaran agama yang terjadi pada masa pramodern cenderung mengorbankan agama suku (tribal religions). Ironisnya, praktik tersebut masih dipertahankan hingga saat ini, meski tidak seekspansif dahulu.
Sebagai hasil konstruksi, setiap agama mengandung ideologi tertentu yang terbentuk sepanjang sejarah eksistensi dan penyebarannya. Konsep kepercayaan dalam agama-agama sangat bervariasi. Oleh karenanya, ketika membahas konversi, agama-agama tidak berdiri pada posisi yang sama. Dengan kata lain, kebebasan beragama yang tidak sama pula. Gagasan-gagasan Sharma tentang kebebasan beragama memang sangat menantang—bahkan tampaknya terlalu idealis, misal argumentasinya tentang “kebebasan untuk mempraktikkan agama lain tanpa konversi”. Meski argumen itu secara esensial adalah bagian dari kebebasan beragama, ide tersebut masih sulit diterima secara komunal—meski tidak semua agama antikonversi. Pada akhirnya, karya Sharma ini tidak hanya membuka ruang-ruang baru dalam diskursus KBB, tetapi juga memberikan rambu di tengah kompleksitas isu tersebut.
Problematizing Religious Freedom | Arvind Sharma | Springer, 2011. 264 + vii hlm. | ISBN 978-90-481-8992-2
Tulisan ini diambil dari website CRCS UGM









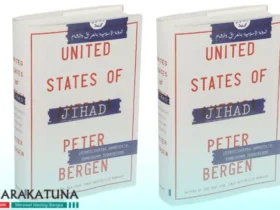
Leave a Reply