Oleh: Tedi Kholiludin | Republikasi dari elsaonline
Pendekatan dalam memahami dimensi kebebasan beragama sejauh ini didominasi aspek filosofis, politik dan hukum. Kajian yang bersifat sosiologis, bisa dikatakan relatif baru sebagai sebuah analisis ilmiah terhadap kebebasan beragama. Upaya untuk menelaah struktur sosial, perubahan masyarakat, tradisi serta sejarah kelompok tertentu akan sangat bermakna dalam studi mengenai kebebasan beragama. Dalam buku pengantar buku “Religious Freedom: Thinking Sociologically,” Olga Breskaya et.al. (2023) menjelaskan bahwa penelitian sosiologis atas kebebasan beragama berupaya “menjelaskan bagaimana klaim kebebasan beragama dan proses pembentukan maknanya terkait dengan kondisi keagamaan dan politik individu, agama dominan, dan masyarakat yang lebih luas.”
Kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal serta masuk pada kategori hak yang tidak dapat dicabut atau non-derogable rights. Ini adalah hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Dalam kondisi internal (forum internum), kebebasan beragama masuk kategori sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Meski demikian, dalam aspek implementasinya, ada hak yang bisa dibatasi (derogable rights), atau biasa dikenali dengan forum eksternum. Kovenan internasional hak sipil dan politik mengatur tentang alasan-alasan dilakukannya pembatasan.
Pada praktiknya, tafsir atas alasan-alasan pembatasan tersebut sering kali berada dalam kekuasaan negara. Salah satu klausul yang kerap digunakan adalah alasan social order yang kemudian diterjemahkan dengan “ketertiban umum.” Ketertiban umum kerapkali dibentuk oleh sensitivitas sosial kelompok dominan atas masyarakat yang lebih kecil secara jumlah.
Kelompok ibadah keluarga tiba-tiba dibubarkan aparat karena dianggap meresahkan warga. Padahal mereka hanya berdoa bersama dan tidak menimbulkan ancaman, hanya karena berbeda dengan yang dominan. Ketertiban umum, menjadi batas antara apa yang dianggap “normal” dengan yang “menyimpang,” tergantung bagaimana masyarakat dominan membentuk persepsi terhadap kelompok lain.
Kelompok minoritas agama mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah mereka, bukan karena hukum melarangnya secara eksplisit, tetapi karena tekanan sosial dari kelompok yang lebih besar. Pemerintah kerapkali menganggap penolakan tersebut sebagai salah satu bentuk ketiadaan “ketertiban umum” yang menjadi salah satu syarat pendirian rumah ibadah.
Ketertiban umum kemudian menjadi istilah yang lentur, bukan sekadar norma legal, tetapi cermin dari struktur kekuasaan sosial dan identitas dominan dalam masyarakat. Tafsir negara atas ketertiban umum pada akhirnya merefleksikan siapa yang dianggap diberikan izin untuk tampil di panggung publik, dan siapa yang harus disembunyikan.
Dalam situasi seperti ini, kebebasan beragama khususnya yang berkaitan dengan pembatasan atas implementasknya, terjadi bukan semata karena keputusan hukum, tetapi karena dinamika sosial atau dan relasi kekuasaan yang tak kasatmata. Di sinilah pendekatan sosiologis menjadi penting: cara baca ini membantu kita memahami kebebasan beragama sebagai ruang sosial yang penuh dengan negosiasi, resistensi, dan kontestasi makna.
Breskaya dan kawan-kawan (2023), menilai pentingnya intervensi sosiologis mendesak ketika realitas sosial baru menantang prinsip-prinsip hukum dan pengaturan kelembagaan kebebasan beragama yang telah mapan dengan klaim-klaim individu dan kolektif yang baru. Penerapan analisis sosiologis tersebut pada gilirannya mengharuskan pendefinisian kembali mengenai kondisi sosial kebebasan beragama, proses klaim akan haknya, dampak sosial yang timbul, serta interseksionalitas kebebasan beragama dengan hak-hak lainnya.
Dalam “A Sociology of Religious Freedom,” yang ditulis Breskaya bersama Giuseppe Giordan, dan James?T.?Richardson (2024), dielaborasi empat pendekatan dalam memahami kebebasan beragama dari sudut pandang sosiologis. Pendekatan pertama berakar pada pikiran Peter L. Berger yang meletakkan kebebasan beragama dalam konteks pluralisme dan otonomi individu, terutama dalam konteks masyarakat modern yang sekuler. Kebebasan muncul dalam dunia yang terdesakralisasi sehingga tidak ada monopoli atas kebenaran di sana. Berikutnya adalah pendekatan yang berakar pada gagasan Roger Finke (dan Stark) mengenai pasar agama. Kebebasan beragama diletakkan dalam kerangka pasar yang kompetitif, sehingga komunitas agama berkembang bebas tanpa intervensi negara.
Pendekatan ketiga berasal dari apa yang oleh James Richardson (2021) sebut sebagai yudisialisasi kebebasan beragama (Judicialization of Religious Freedom). Makna kebebasan beragama dikonstruksi oleh putusan hukum, bukan legislator atau komunitasnya. Di sini, hukum tidak hanya memproteksi atau menjamin kebebasan, tetapi sekaligus membatasi dan juga mengarahkan maknanya. Pendekatan terakhir berasal dari gagasan sekularisme politik John Fox. Dalam pendekatan ini, Fox memfokuskan pada kebebasan menjalankan praktik keagamaan dan kebijakan negara yang berpotensi melahirkan diskriminasi melalui apa yang disebutnya sebagai “unreasonable interference” campur tangan negara yang tidak proporsional terhadap kelompok agama yang pada gilirannya melahirkan ketimpangan.
Oleh Breskaya dan kawan-kawan, empat pendekatan itu tidak digunakan secara tunggal Keempat pendekatan ini tidak digunakan secara tunggal, melainkan untuk membangun konsepsi bahwa kebebasan beragama adalah lanskap sosiologis yang multidimensi, bukan sekadar prinsip hukum abstrak. Keempat pendekatan ini digabungkan untuk memberikan penjelasan kalau kebebasan beragama dipahami, dibatasi, dan dijalankan dalam berbagai konteks masyarakat dan negara.
Breskaya dan rekan-rekannya memformulasikan kebebasan beragama sebagai konsep multidimensi dimana di sana ditemukan interseksi pada lima ranah makna; autonomi individu dan kelompok; nilai sosial kebebasan beragama dan bebas dari agama; prinsip normatif hubungan agam-negara; standar internasional hak asasi manusia; dan dampak sosio-legal dari yudisialisasi agama. Pendekatan ini memungkinkan kita memahami kebebasan beragama tidak semata sebagai prinsip normatif yang abstrak, tetapi sebagai hasil dari negosiasi sosial yang melibatkan aktor-aktor keagamaan, negara, dan masyarakat luas, di mana makna kebebasan itu dibentuk, dipertentangkan, dan dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari.

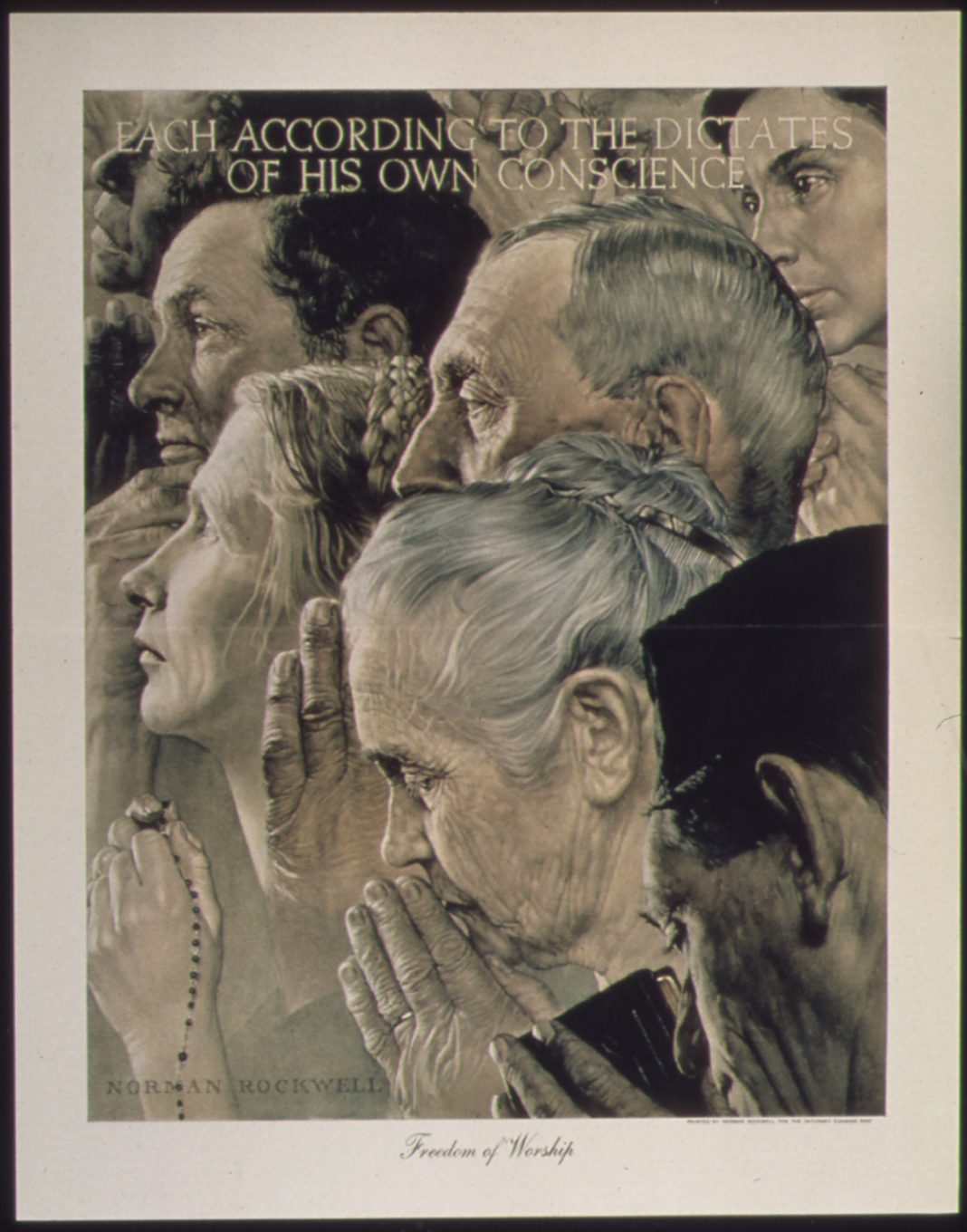





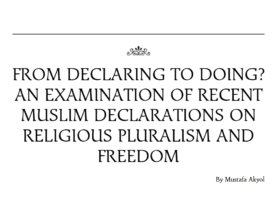

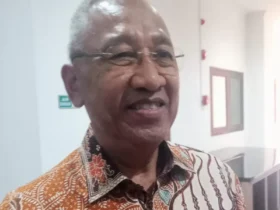
Leave a Reply