Oleh: Anna Soetomo (Indonesian Consortium of Religious Studies/ICRS)
Apakah hak orang tua atas agama anak dapat dibatasi?
Artikel ini disarikan dari diskusi dalam empat presentasi dalam dua panel pada The 8th Human Rights Conference yang diselenggarakan oleh Sydney Southeast Asia Center di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 11-13 Agustus 2025. Panel pertama yaitu panel 2.6. Alternative Perspectives on Religion and Rights, dan Panel kedua yaitu panel 3.3: Children’s Rights and Protection.
Pada panel 2.6 Anna Amalia dari ICRS membuat presentasi dengan judul: “Kidness as Perspective to FoRB”. Kemudian pada panel 3.3, Sheila Devi dari Malaysia membuat presentasi dengan judul “Analysing the Confluence of Child Marriages and Trafficking in Malaysia”, Muhrisun Afandi dari UIN Sunan Kalijaga membuat presentasi dengan judul “Shattered Innocence: Children of Parents Subjected to Public Caning under Sharia Law in Aceh”, lalu Fairuz Zahirah, dkk, membuat presentasi dengan judul “Marriage Dispensation: Fulfillment of Children’s Right Analysis Through the Building Equity Taxonomy”
Sekalipun mengambil kasus yang berbeda, empat presentasi tersebut menunjukkan bagaimana anak yang terikat dengan agama orang tuanya, harus berhadapan dengan situasi yang menyebabkan haknya diingkari, dihambat, bahkan dihilangkan.
Anak Dalam Belenggu Agama
Agama anak mengikuti agama orang tua. Kalimat tersebut tampaknya netral dan dapat diterima secara umum. Tanpa diberikan kesepatan memilih agama, anak-anak melekat pada agama orang tuanya dan harus berhadapan dengan sejumlah situasi sebagaimana disampaikan empat pemapar.
Pada panel pertama, Anna dari ICRS mempersoalkan apakah orang tua boleh memaksakan agama tertentu pada anaknya. Ia mengambil sejumlah kasus di mana orang tua menolak intervensi medis terhadap anaknya karena alasan agama, baik karena tindakan medis bertentangan dengan ajaran agamanya, maupun karena keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan atas kehendak-Nya. Salah satu argumen ekstrem yang diberikan adalah “If evolution believes in survival of the fittest, well then why are we vaccinating everybody? Shouldn’t we just let the weak die off and let the strong survive?” (Jika teori evolusi meyakini bahwa yang kuat dapat bertahan, mengapa harus ada vaksin? Mengapa tidak membiarkan mereka yang lemah untuk mati dan mereka yang kuat terus bertahan?). Beberapa kasus yang diangkat menunjukkan penolakan intervensi ini menyebabkan cacat seumur hidup bahkan kematian pada anak.
Dalam paparan berikutnya, Sheila Devi dari Malaysia mengajukan argumen bahwa perkawinan-anak adalah bentuk perdagangan orang. Bagi Sheila, “Setiap perkawinan anak, pada faktanya adalah kawin paksa”. Ia menjelaskan pada umumnya di Malaysia agama anak mengikuti agama orang tuanya, akan tetapi pola asuh anak pada keluarga Islam, Hindu, dan Kristen dapat berbeda satu sama lain. Studi kasus Sheila menunjukkan anak-anak dari keluarga migran yang beragama Islam lebih rentan menjadi korban perdagangan orang karena kemiskinan ekstrim, praktek budaya, akses yang terbatas pada pendidikan, marjinaliasi secara sosial, serta minimnya perlindungan dari keluarga. Situasi tersebut diperparah karena hukum syariah menetapkan batas usia legal yang sangat rendah untuk anak perempuan boleh menikah, sehingga memberi celah bagi terjadinya kawin paksa.
Muhrisun Afandi dari UIN Sunan Kalijaga membuat paparan tentang anak-anak yang orang tuanya menjadi penerima hukuman cambuk. Ia berpendapat bahwa, dari banyak studi tentang qanun cambuk, jarang sekali pembahasan dari sudut pandang keluarga, terutama anak-anak. Dalam prakteknya, sekalipun hukuman cambuk tidak boleh disaksikan oleh anak-anak, tetapi karena dilakukan di muka umum maka semua orang bisa melihat, termasuk anak-anak. Ia menyoroti bagaimana anak-anak memahami hukuman tersebut serta bagaimana pengalaman anak secara emosi, psikis, dan hambatan sosial lain yang dialami. Bagi Muhrisun, dampaknya adalah pelanggaran hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak, terutama hak atas tumbuh kembang dalam lingkungan yang baik.
Dalam paparannya, Fairuz dkk mengkritisi dispensasi perkawinan, yang dianggap bertentangan dengan semangat Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua kepada KUA untuk dapat menikahkan anaknya yang usianya di bawah ketentuan undang-undang. Alasan yang sering digunakan adalah karena adanya kehamilan, akan tetapi peserta diskusi juga menemukan bahwa dispensasi juga dimintakan dengan alasan karena anak terlalu lama pacaran, sehingga dinikahkan untuk menghindari kehamilan tidak diinginkan. Alih-alih melakukan edukasi yang menjadi tanggungjawabnya, orang tua memilih mengawinkan anak karena dianggap sebagai beban, dengan menggunakan alasan agama. Fairuz dkk mengatakan, “Jika mau jujur, permintaan dispensasi perkawinan adalah demi nama baik keluarga, bukan kepentingan terbaik bagi anak”.
Anak (Bukan) Milik Orang Tua
Dalam penelitiannya yang lain, Muhrisun menyampaikan bahwa 90% orang tua setuju bahwa anak punya hak dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian, 90% juga menyatakan tidak setuju bahwa anak memiliki hak atas kebebasan beragama.
Interseksi yang kompleks antara hak atas kebebasan beragama, keputusan partisipatif anak, serta otoritas orang tua bukan isu yang unik dan baru. Ia telah lama diperbincangkan baik dalam ruang akademik maupun publik. Bagi mereka yang menolak gagasan otoritas orang tua, argumen mendasar yang digunakan adalah: tidak ada satu orang pun boleh memaksakan agamanya pada orang lain. Argumen tersebut berupaya mengatasi persoalan jika ada benturan antara apa yang diyakini oleh anak (termasuk hak anak untuk menyatakan agamanya atau menolak pilihan agama orangtuanya) dengan hak orang tua untuk menentukan agama bagi anak-anak mereka. Permasalahannya, Konvensi Hak Anak yang menjadi kekuatan moral dan legal untuk kepentingan terbaik bagi anak, secara tekstual, memberi ruang bagi orang tua untuk mengatur agama anak.
Pasal 14 Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa negara pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama, menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua atau wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak, dan kemudian membunyikan kembali pembatasan dalam Deklarasi DUHAM, bahwa kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan tunduk pada ketetapan undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Jika ini bicara hak anak, lalu dari mana gagasan tentang hak hak dan kewajiban orangtua tersebut? Bagi Hall (1999), secara sederhana, hak tersebut berakar dari pandangan bahwa anak adalah (kepe)milik(an) orang tua.
Meninjau Ulang Otoritas Orangtua
Jika anak juga termasuk setiap orang dalam gagasan pasal 18 DUHAM, maka penting untuk meninjau ulang gagasan tentang hak atau otoritas orang tua terkait agama anak. Konvensi Hak Anak menetapkan usia 18 tahun sebagai batas atas, akan tetapi pasal 18 DUHAM menjamin kemerdekaan setiap orang sejak usia nol. Jika presentasi satu-arah terkait agama yang dilakukan orang tua pada anak disepakati sebagai standar kepatutan yang umum, maka juga perlu ada ruang untuk kepentingan terbaik bagi anak. Konvensi Hak Anak bertujuan melindungi anak dari ragam bentuk kekerasan, dan prinsip partisipasi anak dalam konvensi hanya dapat dipenuhi dengan cara memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai pilihan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.
Jauh sebelum adanya KHA, Dwyer (1994) mengatakan bahwa hak orangtua atas anak tidak punya legitimasi. Ia menyarankan agar rezim hukum yang lebih baik di masa mendatang dapat memberikan keistimewaan secara legal pada orang tua untuk mengasuh dan mengambil keputusan terkait anak dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Pendeknya, bukan hak, tetapi keistimewaan untuk mengasuh. Ia menegaskan penting melihat kembali legitimasi dalam doktrin hak orangtua, bahkan perlu menolak legitimasi tersebut di masa mendatang. Dalam konteks Indonesia, tawaran yang demikian tentu sulit dilakukan mengingat konteks sosial budaya serta politik agama yang ada. Yang paling mungkin dilakukan adalah membuat batasan pada hak orang tua sehingga hak anak dan otoritas orangtua dapat dipertemukan.
Pasal 1 Konvensi Hak Anak menetapkan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika regulasi mengatur batasan kematangan seseorang dengan usia lebih rendah. Tapi kematangan usia yang ditetapkan secara sosial, seringkali menafikkan hak-hak anak yang lain. Islam misalnya, pada mulanya tidak dikenal istilah perkawinan anak. Dalam beberapa tradisi, menstruasi adalah batas anak perempuan boleh menikah. Dan secara sosial, segera setelah mereka menikah, statusnya berubah menjadi dewasa, dan kehilangan seluruh haknya sebagai anak. Kehilangan hak inilah yang menyebabkan kerentanan di masa mendatang.
Indonesia telah meratifikasi KHA, dengan demikian harus berkomitmen untuk memenuhi. KHA merupakan instrumen pemenuhan hak anak, namun pada saat bersamaan, KHA juga cara pandang. Dengan demikian, hak orang tua yang melekat pada anak, terutama dalam urusan agama, harus dijaga dalam terang prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang tidak menyebabkan hilangnya hak anak yang lain, penderitaan fisik dan psikis, cacat permanen, bahkan kematian.
Bacaan lebih lanjut
The Origin of Parental Rights, Barbara Hall, 1999
Parents’ Religion and Children ‘s Welfare: Debunking the Doctrine of Parents’ Rights, James G. Dwyer, 1994
Tulisan yang sama dalam Bahasa Inggris dimuat dalam website ICRS, dengan penyesuaian non-substantif







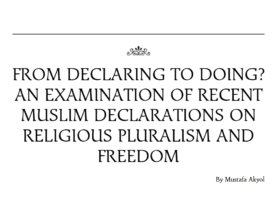

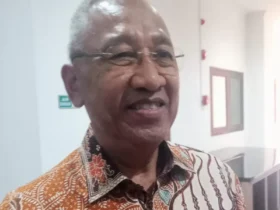
Leave a Reply