Oleh: Ahsan Jamet Hamidi – Anggota Dewan Pengarah SEKBER KBB
“Konferensi internasional agama-agama jadul? Apakah itu berarti lawannya agama-agama pendatang? Berarti kembali ke suasana masa jahiliah lagi, dong.”
Komentar itu disampaikan oleh seorang teman terhadap perhelatan yang akan saya hadiri. Tidak heran dengan sikap sebagian teman yang agak sinis, seperti yang tercermin dalam pertanyaan bernada penuh curiga di atas.
Saya baru saja selesai mengikuti Konferensi Internasional ke-7 dan Konsolidasi Agama-Agama Adat yang digagas oleh Rumah Bersama ICIR (Intersectoral Collaboration on Indigenous Religion) pada 23–24 Oktober 2025 di Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Tema pertemuan ini menarik, yaitu “Ekokrasi: Kekuasaan untuk Rakyat, Keadilan bagi Seluruh Komunitas Planet”—sebuah seruan untuk memperkuat cara berpikir, bertindak, dan strategi demi tercapainya keadilan bagi seluruh makhluk hidup di planet ini.
Hadir para perwakilan akademisi, peneliti dari berbagai bidang ilmu, praktisi dari berbagai profesi, aktivis organisasi masyarakat sipil, anggota komunitas, serta individu independen yang berminat. Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman kritis maupun kreatif melalui makalah, poster, film, atau pertunjukan yang berkaitan dengan tema-tema seperti hak asasi manusia; demokratisasi dan masa depan planet; isu interseksionalitas hak yang meliputi agama atau keyakinan, perempuan, anak-anak, disabilitas, dan lingkungan; isu demokrasi, gerakan sosial, dan kekuasaan rakyat; isu pembangunan, polarisasi, dan kreativitas budaya; dialog, konflik, dan pembangunan perdamaian; serta dunia digital, kreativitas religius/artistik, dan kesejahteraan.
Dari sekian banyak tema di atas, saya memilih satu tema saja, yakni terkait hak untuk beragama atau berkeyakinan dan lingkungan. Kebetulan, saya tinggal di satu pondokan dengan kawan-kawan PAMU (Purwo Ayu Mardi Utomo) Malang, sebuah ajaran kebatinan atau penghayat kepercayaan yang berasal dari Jawa. Saya dapat berdiskusi secara rileks dengan mereka untuk menyempurnakan pemahaman tentang komunitas masyarakat adat.
Kesan saya, memang tetap ada ruang perdebatan di antara kelompok penganut agama leluhur (maaf jika penyebutan ini dirasa kurang tepat) dengan penganut enam agama lainnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam berbagai isu. Saya hanya membatasi pembahasan pada masalah pengelolaan alam beserta seluruh kandungannya oleh para penganut agama-agama penghuni planet bumi.
Para penganut agama leluhur mengaku telah memiliki sistem untuk melindungi ekosistem lingkungan agar dapat beradaptasi dengan alam, sehingga mampu mewujudkan keadilan lingkungan yang menjamin keseimbangan alam dan makhluk hidup di dalamnya. Selama berabad-abad, masyarakat adat menggunakan tradisi hidup untuk melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem yang rapuh, namun tetap mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan mereka menjadi dasar dalam membangun ketahanan komunitas untuk menghadapi agenda pembangunan yang merusak bumi, seperti disampaikan oleh Atika Manggala (Sri Tumuwuh, Yogyakarta).
Eko Cahyono dari Sajogyo Institute telah meneliti tentang respons para penganut agama terhadap krisis sosial-ekologi global. Ia menemukan adanya praktik “dua wajah” oleh para penganut agama di Indonesia. Satu wajah menunjukkan agama sebagai penganjur pelestarian lingkungan, sementara wajah lainnya menjadi legitimator praktik tertentu. Secara rinci, Eko menemukan adanya praktik instrumentalisasi, politisasi, dan komodifikasi agama untuk tujuan politik pragmatis. Terdapat pula monopoli dan reduksi tafsir atas kitab suci untuk kepentingan pribadi dan kelompok, serta absolutisme dan monopoli tafsir “kebenaran” agama oleh golongan tertentu. Yang memprihatinkan, muncul fenomena holy grabbing, yaitu perampasan ruang hidup rakyat dengan legitimasi kesucian (agama).
Selain temuan di atas, ada hambatan yang dialami oleh para penganut agama untuk bisa memberikan kontribusi dalam agenda pencegahan ancaman kerusakan iklim. Pendeta Jimmy M. I. Sormin memandang bahwa selama ini peran kelompok agama hanya ditempatkan sebagai bagian dari komponen “proyek”, bukan sebagai leading sector. Di komunitas akademis, mereka juga hanya dianggap sebagai objek penelitian yang menarik sesuai selera “pasar”. Tidak heran jika mereka sering terjebak pada aktivitas seremonial saja. Tragisnya, ketika dukungan dana untuk kegiatan agama dan lingkungan selesai, berhenti pula program seremonial bersama umat itu.
Perbedaan klaim dan pandangan tersebut lumrah selama terjadi di ruang diskusi seperti dalam perhelatan itu. Semua akan selesai di situ. Perbedaan pendapat yang berpangkal pada keragaman sudut pandang para penganut agama adalah hal yang wajar. Namun, ketika perbedaan itu berlanjut pada sikap dan pilihan perilaku diskriminatif serta intoleran terhadap penganut agama lain, hal itu harus dicegah.
Mencegah Ancaman Diskriminasi dan Intoleransi
Dalam pandangan Samsul Maarif, Kepala Program Magister di Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, praktik diskriminasi dan intoleransi terhadap agama leluhur masih terjadi di ranah sosial dan ruang publik. Faktor penyebabnya beragam, salah satunya adalah pendidikan dan pengelolaan agama yang membatasi keragaman hanya pada enam agama resmi. Atas dasar itulah konferensi seperti ini rutin dilakukan, salah satunya bertujuan untuk membuka ruang perjumpaan antar mereka yang selama ini berbeda pandangan dan keyakinan, sehingga dapat saling mengungkapkan pandangan yang berbeda-beda secara sehat.
Secara normatif, seharusnya bangsa Indonesia sudah tidak memiliki masalah dengan harmoni antarpemeluk agama apa pun. Konstitusi negara telah memberikan jaminan terhadap kesetaraan semua agama, termasuk agama leluhur (indigenous religions). Para penganut agama apa pun di Indonesia harus dilayani secara adil oleh negara. Semua pemeluk agama mesti dijamin kemerdekaannya dalam meyakini dan menjalankan agamanya masing-masing. Masalah-masalah sosial masih terus terjadi karena adanya regulasi dan implementasi pengelolaan agama, seperti pendidikan agama/kepercayaan, pernikahan, dan layanan publik lainnya kepada penganut agama leluhur, yang dijalankan oleh aparatur negara secara diskriminatif. Mereka menggunakan sebagian regulasi sebagai sandaran sikap diskriminatifnya.
Perjalanan menuju ekokrasi dapat dilakukan dengan semangat keselarasan dalam merawat alam secara lestari sekaligus menghormati keberagaman keyakinan, seperti yang diajarkan oleh alam itu sendiri. Planet Bumi, meskipun isinya sangat beragam, semestinya tetap bisa hidup dalam harmoni. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan iklim dan keadilan spiritual harus berjalan beriringan, karena saat kita sedang berusaha menjaga planet, upaya itu harus senapas dengan menjaga kemanusiaan.

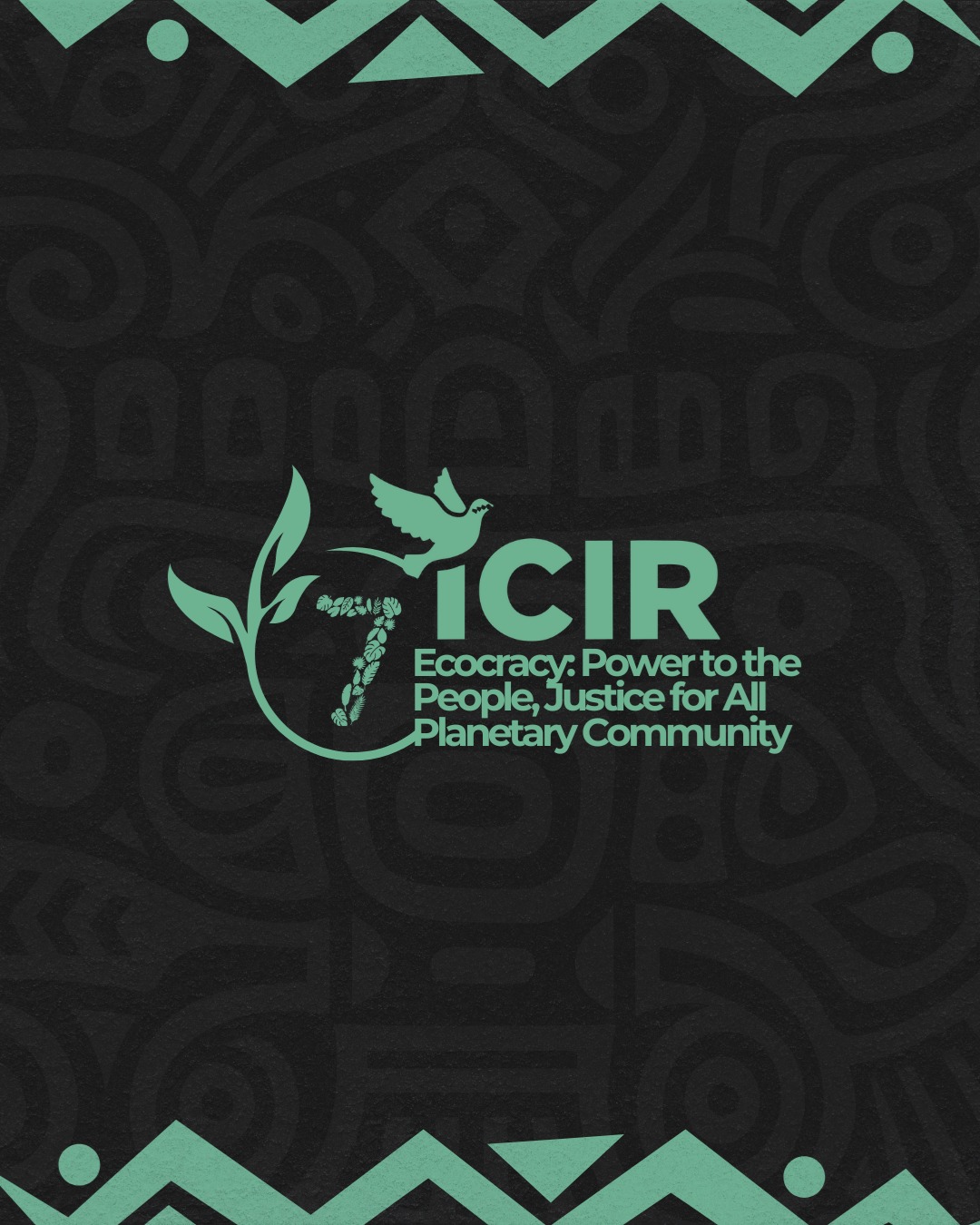





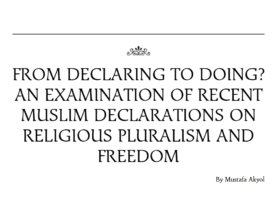




Leave a Reply