Oleh: Nuzula Nailul Faiz | Republikasi dari CRCS UGM
Ringkasan:
● Studi agama memperkuat sinergi akademik–aktivisme untuk mendorong keadilan sosial dan lingkungan.
● Alumni CRCS menerapkan wawasan lintas disiplin dalam pemberdayaan komunitas, mitigasi konflik, dan isu ekologi.
● Kolaborasi akademis dan praksis terbukti efektif membangun transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Segregasi antara kerja akademik dan aktivisme sering kali digambarkan terpisah oleh garis batas yang saling mengelakkan. Kerja akademik dianggap harus objektif dan netral, sementara aktivisme bersifat subjektif dan politis. Karakteristik yang berlawanan itu melahirkan anggapan bahwa keduanya mesti dipisahkan dalam ruang lingkupnya masing-masing. Anggapan ini dikritisi oleh para alumni CRCS UGM berdasarkan kiprah mereka dalam dunia aktivisme dari berbagai latar belakang.
Acara Alumni Berbagi bertajuk “Studi Agama untuk Keadilan: Sinergi Kerja Akademik dan Aktivisme” (22/10), sebagai rangkaian perayaan 25 tahun CRCS UGM, menghadirkan para alumni dari berbagai angkatan dan latar belakang profesi. Pada acara yang dimoderatori oleh Kristi (CRCS 2016/Gereja Kristen Jawa) ini, mereka berbagi pengalaman tentang bagaimana studi agama mewujud di ruang akademik maupun dalam aksi nyata di masyarakat.
Wilis Rengganiasih Endah Ekowati (CRCS 2004/Sanggar Omah Sewu Sirah), sebagai seorang penari, menemukan benang merah antara seni, agama, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui sanggarnya, ia mengangkat isu lingkungan dan pemberdayaan dengan pendekatan kesenian kampung, seperti Gejog Lesung dan parikan Jawa yang hampir punah. Konsep gender yang dipelajarinya di CRCS UGM menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di komunitasnya. Baginya, agama dan seni berkelindan untuk mengurai konflik dan mengisi spiritualitas.
Khoirul Anam (CRCS 2011/Densus 88 AT Polri Bidang Media dan Literasi) menjelaskan bahwa CRCS UGM mengajarkannya mempelajari agama sebagai fenomena sosial, bukan sekadar sistem keyakinan. Pendekatan ini membantunya memahami akar penyebab toleransi dan intoleransi. Dalam tugasnya sekarang, ia mereviu dan meredefinisi konsep terorisme dan radikalisme. Ia bersyukur telah diajari menulis response paper yang analitis ketika kuliah. Kunci yang ia pegang ialah membuka “ruang perjumpaan”, karena ketidaksukaan sering kali muncul dari ketidaktahuan dan ketiadaan pertemanan. Ia membagikan pengalaman membawa mantan anggota kelompok teroris berjumpa dengan komunitas lain, seperti mengajak mereka ke UIN dan memperkenalkan tradisi tari, sehingga memutus mata rantai prasangka.
Titik temu antara agama dan keadilan mendorong semangat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Pengalaman studi di kampus dan keterlibatannya di berbagai komunitas lintas iman membawa Asman Azis (CRCS UGM 2011/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Kalimantan Timur) pada keyakinan bahwa semua agama berbicara tentang kemanusiaan, keadilan, dan warisan bagi generasi mendatang. Hal ini menjadi pintu masuk baginya untuk bergerak dalam isu lingkungan, seperti batu bara, sawit, dan mangrove di Kalimantan Timur. Ia bercerita tentang gugatan warga terhadap institusi negara terkait izin tambang batu bara. Saat ini, ia menangani rehabilitasi 16.500 hektare mangrove. Asman menegaskan bahwa aktivisme dan akademik adalah satu kesatuan. Dalam pekerjaannya mendampingi warga yang lahannya dialihfungsikan, ia menggabungkan pengetahuan administratif adat, perizinan perusahaan, dan pertimbangan otoritas akademik dari kampus. Ia tidak sepakat dengan pemisahan (segregasi) antara keduanya.
Bagi Karen Erina Puimera (CRCS 2021/Gereja Protestan Indonesia Barat), CRCS UGM memberikan bekal akademik dan spiritual untuk pelayanannya sebagai pendeta di GPIB. Momentum itu terjadi saat ia mengikuti sidang gereja dunia (WCC) yang membahas feminisme lintas iman. Ia menyadari bahwa studi agama menjadi sangat relevan untuk memahami realitas kemajemukan. Dahulu, lintas iman terasa simbolis, tetapi setelah terjun langsung, ia memahami pentingnya kolaborasi. Gerejanya kini berfokus pada isu kerusakan lingkungan, geopolitik, dan ekonomi, serta bekerja sama dengan lembaga seperti ICRS untuk mengampanyekan kebinekaan. CRCS UGM membantunya melihat hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam secara lebih holistik, sekaligus mengalami transformasi spiritual yang merangkul.
Studi agama di CRCS tidak hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi juga menumbuhkan empati dalam melihat persoalan masyarakat, serta menghadirkan agama untuk mengarahkan hidup yang lebih baik. Asep Saepudin Sudjatna (CRCS 2015/Eksotika Desa Lestari), yang berlatar belakang sastra dan pencinta alam (Mapala), mempertanyakan mengapa agama sering absen dalam isu ekologi. Saat riset konservasi air di Gunung Kidul, ia menemukan bahwa ritus-ritus lokal justru menjadi kunci pelestarian mata air. Namun, perilaku ini sering dianggap “menyimpang” oleh narasi agama arus utama. Pembelajaran selama kuliah S-2 memberinya perspektif metodologis etnografi yang cair dan empatik. Ia menekankan bahwa kuliah di CRCS UGM tidak hanya membangun logika berpikir, tetapi juga lingkungan yang menumbuhkan empati—sesuatu yang sering luput dari diskusi di jurusan lain. Kini, ia menggabungkan sisi akademis dan aktivisme dengan meneliti desa-desa rawan longsor menggunakan berbagai pendekatan, karena penelitian harus berdampak, tidak berhenti pada laporan.
Sebagai rektor, I Gede Suwindia (CRCS 2003/Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan) menekankan bahwa CRCS UGM mempertemukannya dengan orang-orang hebat dari lintas disiplin. CRCS UGM memberinya ruang yang selaras dengan filosofi Bali bahwa agama mengarahkan hidup. Ia bangga dengan kiprah alumni CRCS UGM yang berdampak luas. Untuk menjawab tantangan kekinian, institusinya melahirkan kurikulum baru, termasuk mengintegrasikan studi film untuk mengangkat nilai-nilai moderasi beragama, menanggapi era digital dan kebiasaan masyarakat mengonsumsi media. Ia menegaskan bahwa kurikulum harus terus diperbarui dan dimulai dengan pertanyaan, “Mau ke mana?”.
Diskusi ini menegaskan bahwa studi agama yang empatik tidak hanya memiliki kapasitas akademik yang kuat, tetapi juga komitmen aktivisme yang mendalam. Keduanya memang memiliki ruang lingkupnya masing-masing, tetapi dapat dipertemukan dan saling mendukung untuk mewujudkan keadilan. Sinergi di antara keduanya terbukti efektif dalam menjawab tantangan keadilan sosial, lingkungan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Jejaring alumni CRCS UGM terus menjadi kekuatan untuk mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Andrianor







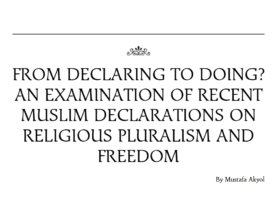





Leave a Reply