Oleh: Arina Rahmatika | Republikasi dari GUSDURian
Beberapa tahun lalu saya berkesempatan mengunjungi Pulau Bali, sebuah tempat yang kerap disebut sebagai surga dunia. Namun di balik keindahan pantainya, tersimpan kisah yang jarang diceritakan. Bagaimana hubungan antarumat beragama di sana perlahan berubah. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga lokal, saya mendengar ungkapan yang sederhana tetapi menyimpan luka sejarah.
“Dulu kita saudara, sekarang kita teman saja.”
Kalimat itu bukan sekadar ucapan lepas. Ia lahir dari perjalanan panjang interaksi antara masyarakat Hindu dan Muslim di Bali. Dahulu, hubungan mereka begitu erat. Masyarakat Hindu dan Muslim saling mengunjungi, merayakan hari besar bersama, dan bekerja bahu membahu dalam kehidupan sehari-hari. Persaudaraan terasa alami, tanpa syarat. Namun, ikatan itu mulai kabur setelah peristiwa Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005).
Ledakan itu bukan hanya menghancurkan gedung dan nyawa, tetapi juga mengguncang kepercayaan yang telah lama terjalin. Masyarakat Hindu mulai merasa takut terhadap Muslim. “Agama teroris,” begitu stigma yang melekat, meski tak adil untuk menyamaratakan. Banyak warung pecel lele milik Muslim dijarah, bahkan ada yang dirobohkan. Bagi warga Hindu, itu adalah luapan amarah terhadap luka yang tak terbayar. Bagi Muslim di Bali, itu adalah bentuk diskriminasi yang menyakitkan.
Sejak saat itu, hubungan antarumat beragama di Bali berubah. “Sekarang kita teman saja,” kata seorang bapak yang saya wawancarai. Ia tidak lagi menyebut “saudara”. Ada jarak yang tidak bisa dipungkiri, ada luka yang belum sembuh.
Bayangan Kasus Ahok
Perubahan suasana itu semakin nyata ketika kasus Ahok mencuat di Jakarta pada 2016. Kasus penodaan agama yang menjeratnya memicu demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi 212. Meski peristiwa itu terjadi di ibu kota, gaungnya sampai ke Bali.
Masyarakat Hindu yang masih menyimpan trauma bom Bali merasa semakin waspada. Pemerintah lokal bahkan mengeluarkan aturan bahwa khutbah Jumat tidak boleh lagi disiarkan melalui pengeras suara ke luar masjid. Alasannya jelas, ada ketakutan jika suatu saat khutbah dijadikan ajang provokasi atau menjelek-jelekkan agama lain. Padahal, bagi umat Muslim, pengeras suara khutbah adalah hal biasa.
Di titik ini kita melihat betapa rentannya relasi antaragama jika dibiarkan ditentukan oleh kasus-kasus yang dimanfaatkan secara politis. Kasus Ahok memperlihatkan bagaimana pasal penodaan agama dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan. Ahok bukan hanya didakwa di pengadilan, tetapi juga diadili oleh sentimen massa.
Pasal Penodaan Agama
Pasal penodaan agama di Indonesia, baik yang tercantum dalam Pasal 156a KUHP maupun UU PNPS No. 1/1965, sudah lama menjadi perdebatan. Di satu sisi, ia diklaim sebagai “pelindung kerukunan”. Namun di sisi lain, pasal ini sering kali digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam suara yang berbeda.
Pertanyaan mendasarnya, siapa yang sebenarnya dilindungi oleh pasal ini? Apakah individu pemeluk agama, ataukah “agama” itu sendiri sebagai sebuah institusi? Bila negara menganggap agama sebagai objek hukum, maka ia melenceng dari prinsip dasar, hukum semestinya melindungi manusia, bukan entitas abstrak.
Agama adalah keyakinan yang hidup dalam diri pemeluknya. Melindungi pemeluk agama dari diskriminasi, intimidasi, atau kekerasan jelas penting. Tetapi menjadikan “agama” sebagai sesuatu yang bisa “dilecehkan” lalu menghukum seseorang atas dasar interpretasi, itu berbahaya. Apalagi, siapa yang berhak menentukan apakah suatu ucapan termasuk penodaan agama? Negara? Mayoritas? Ulama? Jawabannya selalu sarat kepentingan politik.
Luka yang Tak Sembuh-Sembuh
Pengalaman di Bali memperlihatkan bagaimana peristiwa bom dan kasus Ahok meninggalkan residu ketidakpercayaan. Warga Hindu yang dulu menyebut Muslim sebagai saudara, kini memilih menyebut “teman”. Ada jarak emosional yang terbentuk.
Ketakutan akan terorisme bercampur dengan bayang-bayang pasal penodaan agama membuat masyarakat semakin defensif. Alih-alih memperkuat toleransi, aturan-aturan baru justru lahir dari rasa curiga. Misalnya, larangan pengeras suara khutbah. Secara sekilas itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya ia menandakan trauma sosial yang belum sembuh.
Di sini terlihat bahwa pasal penodaan agama tidak benar-benar menyembuhkan luka. Ia justru memperdalam kecurigaan. Alih-alih menciptakan keadilan, pasal ini memberi ruang bagi pihak yang ingin menggunakan isu agama sebagai bahan bakar konflik.
Kalimat “dulu kita saudara, sekarang kita teman saja” bagi saya adalah refleksi getir tentang perjalanan kebangsaan kita. Persaudaraan adalah sesuatu yang alami, lahir dari kedekatan dan rasa percaya. Sementara “teman” sering kali hanya soal formalitas, ramah di permukaan, tetapi menjaga jarak di dalam hati.
Apakah ini yang kita mau? Masyarakat hidup berdampingan, tetapi tidak lagi saling percaya? Bila iya, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kerukunan formal, kita kehilangan rasa memiliki satu sama lain.
Pasal penodaan agama, dalam banyak kasus, tidak membantu memperbaiki keadaan. Justru ia menjadi alasan untuk mempertebal jarak. Negara seharusnya hadir untuk melindungi setiap individu tanpa membeda-bedakan agama, bukan malah menjadikan agama sebagai instrumen hukum yang rawan disalahgunakan.
Saatnya Menghapus Pasal Penodaan Agama
Refleksi dari Bali ini membawa saya pada satu kesimpulan bahwa pasal penodaan agama lebih banyak melukai daripada menyembuhkan. Ia tidak punya dasar ilmiah yang kuat, tidak jelas dalam definisi, dan kerap dipakai untuk kepentingan politik.
Sudah saatnya kita berani bertanya, apakah pasal ini benar-benar dibutuhkan? Ataukah justru ia menjadi tembok yang memisahkan kita?
Saya percaya, persaudaraan sejati tidak bisa lahir dari hukum yang memaksa. Ia lahir dari rasa percaya, saling menghargai, dan keberanian untuk melihat perbedaan sebagai bagian dari kemanusiaan. Bila kita ingin kembali menjadi saudara, maka negara harus menghapus pasal yang membatasi kebebasan beragama dan berpendapat.
Karena hanya dengan begitu, kita bisa berkata lagi: “Kita saudara, bukan sekadar teman.”







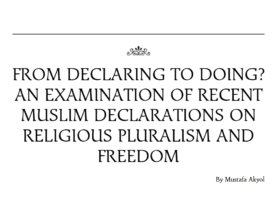


Leave a Reply