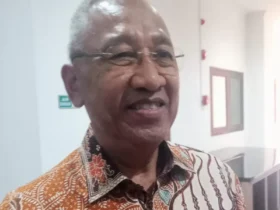Bagi umat Kristiani, perayaan Natal adalah momen untuk mengenang kelahiran Yesus, Juru Selamat. Kelahiran Yesus adalah kasih Tuhan untuk menebus dosa manusia yang diwarisi dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Momen Natal adalah untuk mengingat segala salah dan dosa yang telah diperbuat, bertobat karenanya, dan kembali menguatkan komitmen mendekatkan diri pada Tuhan, memenuhi panggilan-Nya melalui doa. Introspeksi diri, saling memaafkan dan berbagi kasih dengan sesama, keluarga dan tetangga, teman, sahabat dan sejawat adalah bentuk-bentuk pemaknaan perayaan Natal, hari kelahiran Yesus.
Sebagaimana hari raya agama lainnya, Natal dirayakan secara semarak di Indonesia. Berbagai atribut penanda perayaan Natal digunakan. Di antara atribut yang sering digunakan adalah pohon natal, bintang natal, Sinterklas dengan topinya, kaus kaki, lonceng, dan lain-lainnya. Atribut-atribut tersebut dipajang di gereja, di rumah, hingga di hotel-hotel dan di tempat-tempat perbelanjaan. Penggunaan atribut-atribut tersebut adalah sarana menyampaikan ragam makna dan pesan keagamaan (Kristiani) berkaitan dengan Natal. Semua atribut adalah “simbol” yang melaluinya pesan universal terkait Natal disampaikan. Pohon natal misalnya dimaknai sebagai simbol kekekalan kehidupan rohani, bintang natal dimaknai sebagai semangat ketaatan dan kerendahan hati di hadapat Tuhan dan sesama, Sinterklas disimbolkan sebagai pembawa kebaikan dan kegembiraan bagi semua, dan seterusnya. Sebagaimana simbol-simbol agama-agama lainnya, atribut-atribut natal adalah kreatifitas keagamaan yang di antara tujuannya adalah untuk menyemarakkan kehidupan keagamaan, menyampaikan pesan keselamatan dan kebahagiaan manusia.
Berbeda dengan perayaan hari raya agama lainnya, perayaan Natal di Indonesia masih terus diperhadapkan dengan diskursus kontroversial. Terlepas dari perayaannya di Indonesia yang sudah menyejarah, ia senantiasa menjadi isu hangat bagi kehidupan beragama di Indonesia. Setiap tahun, larangan ucapan “selamat natal”, utamanya oleh individu-individu dan bahkan organisasi Islam, seperti MUI, terus mewarnai diksusi publik.
Lebih jauh, perayaan Natal seringkali diperhadapkan dengan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Kasus-kasus pelarangan perayaan Natal oleh pemerintah sering terjadi di beberapa daerah. Pengurasakan atribut natal dilakukan oleh kelompok warga, dan dibiarkan oleh aparat. Diskriminasi negara terhadap umat Kristian seringkali terjadi di setiap perayaan natal, misalnya ketika aparat negara menghalangi perayaan natal, tetapi pada saat yang berbeda menfasilitasi penganut agama lain marayakan hari raya agamanya.
2. Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Perayaan Natal.
Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih terus menjadi sorotan. Berbagai kasus pembatasan KBB terus terjadi menimpa khususnya kelompok agama minoritas. Seperti telah disinggung sebelumnya, larangan ibadah Natal, larangan penggunaan atribut Natal, dan seterusnya adalah fenomena tahunan di Indonesia.
Dalam perspektif HAM, hak KBB terbagi dalam dua kategori. Pertama, forum internum, yang berlaku absolut. Pada wilayah ini, kebebasan beragama tidak bisa dibatasi atau dikurangi (non-derogable) dalam kondisi apapun. Pembatasannya adalah pelanggaran HAM. Sebaliknya, wilayah ini harus dilindungi secara setara, tanpa syarat. Wilayah forum internum menyangkut hak untuk memeluk agama atau keyakinan yang definisinya harus ditafsirkan seluas mungkin mencakup kebebasan berpikir dalam segala hal, keyakinan pribadi, dan kebebasan hati nurani—termasuk juga kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateistik, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.
Kedua, forum externum, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan atau memanifestasikan agama atau keyakinan yang dapat dibatasi melalui syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Perayaan Natal adalah salah satu bentuk manifestasi dan ekspresi agama atau keyakinan yang status aktivitasnya dapat dibatasi atau dikurangi (derogable) dalam kondisi-kondisi dan tujuan-tujuan tertentu. Wilayah ini juga mencangkup aktivitas-aktivitas seperti beribadah atau berkumpul yang berkaitan dengan ritual suatu agama atau kepercayaan. Perbedaan mendasar mengapa forum externum dapat dibatasi karena manifestasi agama memiliki implikasi sosial, khususnya bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Oleh karenanya pembatasan dimungkinkan. Ia berbeda dengan forum internum tidak memiliki implikasi sosial, sehingga yang terakhir tidak boleh dibatasi.
KBB dengan kategori forum externumnya sekali lagi dapat dibatasi. Namun, pembatasannya harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan prinsip HAM. Secara singkat, dalam perspektif HAM internasional, setidaknya ada beberapa aspek normatif mengenai pembatasan KBB. Aspek-aspek itu mengacu pada apa yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12/2005. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa “Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.” Arti dan definisi poin-poin tersebut mengacu pada penjelasan tentang apa yang ada dalam Prinsip Sirakusa (Syracuse Principles). Dasar ini menjadi instrumen awal dalam pendekatan HAM untuk melihat pembatasan hak KBB (Lebih detail tentang ini, baca: Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan).
Di sisi lain, sesuai amanatnya, negara berkewajiban dalam menjamin KBB. Dalam konteks ini, pada prinsipnya, kehadiran negara menjadi penting dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan kepada umat beragama dalam memanifestasikan ajaran agama dan keyakinannya. Kaitannya dengan poin tersebut adalah bahwa seringkali kasus-kasus pelanggaran KBB terjadi karena pembatasan dilakukan oleh individua atau kelompok masyarakat akibat tidak adanya perlindungan, ketidakhadiran negara, bahkan pembiaran oleh negara.
Berdasarkan prinsip-prinsip KBB di atas, perayaan Natal dan penggunaan atribut-atributnya sebagai manifestasi ke-Kristen-an seharusnya mendapatkan jaminan KBB dari negara, dan tidak dapat dibatasi jika syarat-syarat pembatasannya tidak terpenuhi. Ketika ibadah Natal dibatasi di masa pandemi, pembatasan tersebut tidak melanggar karena dengan alasan kesehatan umum dan telaah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Terkait itu, pembatasan terhadap ibadah Natal harus diberlakukan terhadap ibadah-ibadah agama lain secara setara. Poin non-diskriminasi ini penting ditegaskan mengingat di beberapa daerah umat Kristiani, dengan situasinya sebagai minoritas—secara sosiologis maupun politis, sering menjadi kelompok rentan untuk dibatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya. Penerapan pembatasan KBB yang diskriminatif dan karena itu melanggar KBB faktanya sering terjadi. Misal, penyegelan masjid Al-Aqsa milik jemaat Ahmadiyah pada awal April 2020, yang sekalipun wacananya karena alasan pandemi, dianggap melanggar KBB karena tidak berlaku untuk semua tempat ibadah (baca: Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah COVID-19).
3. Pola Kasus KBB dalam Konteks Perayaan Natal
A. Pembatasan Perayaan Natal oleh Negara
Dalam perayaan Natal, negara masih melakukan pembatasan KBB pada umat Kristiani. Misal, pada tahun 2010, dalam laporan Hasani & Naipospos (2012), Politik Diskriminasi Rezim SBY: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2011, jemaat GKI Yasmin mendapatkan larangan untuk melakukan ibadah dari pihak kepolisian akibat adanya tekanan aksi dan intimidasi dari Forkami dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembatasan ini akibat konflik sengketa lahan yang sudah sejak lama dialami para jemaat, hingga tuduhan melakukan kristenisasi dari kelompok-kelompok tersebut. Tetapi, polisi bukannya melindungi para jemaat untuk beribadah, malah mengimbau para jemaat untuk membubarkan ibadah Natal tersebut.
Contoh kasus lainnya adalah di Desa Purwodadi, Kab Aceh Tamiang, pada tahun 2020. Pemerintah setempat tidak memberikan izin menggelar kebaktian Natal di rumah umat Kristiani melalui surat edaran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam surat itu, pemerintah melakukan pembatasan ibadah dengan dasar, agar tidak terjadi konflik horizontal di kampung Purwodadi (lebih jauh, baca: Duduk Perkara Larangan Ibadah Natal di Rumah Warga).
Hal serupa juga terjadi di Aceh Singkil. Seperti dicatat dalam Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia (2015) oleh The Wahid Institute, pemerintah Provinsi Aceh menghimbau umat Kristiani Aceh Singkil untuk merayakan Natal di gereja-gereja yang memiliki izin dan melarang umat Kristiani menggunakan rumah atau gereja yang sudah dibongkar. Pembatasan dilakukan oleh pemerintah karena umat Kristiani tidak memiliki izin tempat yang legal untuk melakukan peribadatan.
Contoh kasus yang agak pelik, tetapi dapat dianggap melanggar KBB adalah yang terjadi pada tahun 2015. Pemerintah kota Padang mengimbau karyawan Muslim, yang bekerja di beberapa hotel, mal, perkantoran, restoran, dan lainnya, untuk tidak menggunakan atribut Natal atau Sinterklas. Imbauan itu tertulis melalui Surat Imbauan No. 451.338/Kesra-2015 tentang larangan pemakaian atribut Natal. Dalam surat itu, Walikota meminta semua pihak menjaga ketenteraman, kenyamanan dan keamanan serta menjauhi perbuatan yang melanggar hukum.
Walikota sebagai wakil negara seharusnya tidak membatasi warga, termasuk warga Muslim, untuk merayakan Natal dan atribut-atributnya. Terkait kasus di atas, beberapa memberi komentar bahwa surat imbauan tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemerintah melindungi warganya (yang Muslim) dari paksaan menggunakan atribut Natal oleh pimpinan tempat warga Muslim bekerja, seperti hotel, mal, dan lain-lainnya. Jika demikian alasannya, walikota dapat memainkan peran negara dalam melindungi warganya dari paksaan oleh warga lain dengan surat imbauan larangan paksaan kepada perusahaan atau lembaga, bukan kepada warga yang diasumsikan dipaksa. Selama penggunaan atribut Natal oleh karyawan didasari dengan kesadaran dan keinginan diri sendiri, penggunaan atribut tersebut adalah ekspresi kebebasan yang juga tidak boleh dibatasi oleh negara.Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
4. Bentuk Pelanggaran KBB dalam Konteks Perayaan Natal
A. Pembatasan
Meskipun KBB bisa dibatasi, tetapi pembatasannya tidak bisa sembarangan. Yang bisa diuji dari pembatasan KBB pertama-tama adalah justifikasinya. Pada kasus pembatasan ibadah di Kab Aceh Tamiang, justifikasi yang digunakan adalah menghindari konflik horizontal. Tentunya argumen pembatasan ini tidak dijustifikasi dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip KBB. Sama halnya dengan kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin dan umat Kristiani di Singkil sangat berkaitan dengan perizinan tempat ibadah sehingga berimplikasi pada pembatasan KBB. Kedua argumen dari kasus ini juga tidak bisa memiliki legitimasi HAM.
Dengan kata lain, pembatasan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak KBB. Alih-alih menjamin hak warga negara untuk menjalankan beribadah, negara justru membatasi hak warga negaranya tanpa dasar yang diperbolehkan.
Justifikasi lainnya yang tidak tepat bisa dilihat dari kasus yang cukup mengecoh, yaitu larangan menggunakan atribut Natal di beberapa usaha hotel, mal, perkantoran, restoran, yang dilakukan Pemkot Padang dalam rangka menjaga ketenteraman, kenyamanan dan keamanan serta menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Argumentasi pembatasan ini harus dilihat sedikit lebih jeli. Di beberapa kasus pembatasan KBB lainnya yang tidak tepat, negara sering menjustifikasi argumennya dengan term atau frasa untuk menjaga “ketenteraman, kenyamanan dan keamanan”. Term dan frasa ini memang cenderung dan mungkin bisa dilekatkan dengan frasa “ketertiban umum”. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua aktivitas cocok dan tepat dengan kategori itu—contoh-contoh aktivitas yang mengganggu ketertiban umum salah satunya bisa mengacu pada UU KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Pasal 154-181. Acuan tersebut yang perlu digunakan untuk menilai apakah menggunakan atribut termasuk salah satu aktivitas kejahatan terhadap ketertiban umum itu. Dan tentu saja, menggunakan atribut Natal bukanlah aktifitas yang dimaksud.
Artinya, pembatasan tersebut tidak bisa dijustifikasi dan tidak tepat sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan pembatasan tersebut. Dalam konteks ini, negara hanya perlu memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara dalam mengekspresikan keberagamaan dan keyakinannya dengan damai dan tidak ada paksaan, sehingga yang bisa dilakukan negara adalah menjamin tidak adanya paksaan dari pemilik perusahaan swasta kepada umat non-Kristiani untuk memakai atribut Natal dan Sinterklas.
Kasus-kasus itu bisa dikontraskan dengan pembatasan Natal yang dilakukan pemerintah kota Makassar melalui Surat Edaran No. 003.02/419/S. EDAR/DISPAR/XII/2020 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dasar dari pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga kesehatan publik (baca: Cegah Cluster Baru Jelang Tahun Baru, Dispar Makassar Sampaikan Pesan ini untuk Warga Makassar). Tidak hanya untuk umat Kristiani, Pemkot Makassar juga mengeluarkan larangan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan takbir keliling bagi umat muslim untuk mencegah kerumunan orang. Pembatasan itu disampaikan melalui surat edaran Wali Kota Makassar Nomor 400 Tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah (baca: Pemkot Makassar Larang Shalat Idul Fitri di Lapangan Karebosi).
Mengacu pada prinsip KBB setidaknya pembatasan mendapatkan justifikasinya. Tetapi perlu dilihat lagi syarat-syarat lainnya yang lebih jauh seperti apakah pembatasannya ditetapkan oleh hukum (prescribed by law), diperlukan (necessary), proporsional—bahkan kalau bisa less-restrictive dan sesuai konteks, dan penerapannya non-diskriminatif (tidak untuk kelompok tertentu). Dengan begitu, baru kita baru bisa benar-benar menilai bahwa pembatasan dibolehkan dan legitimate. Sebaliknya, apabila prinsip dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembatasan KBB tidak bisa dilakukan dan telah melanggar HAM.
B. Pembiaran
Sebaliknya, ketidakhadiran negara dalam mengelola KBB bisa dilihat sebagai bentuk pengabaian serta tidak adanya komitmen negara dalam menjamin umat beragama dalam beribadah, yang pada gilirannya turut berkontribusi pada menguatnya intoleransi dalam masyarakat. Dalam kasus yang menimpa umat Kristiani di Nagari Sikabau dan Sungai Tambang telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana negara tidak menunjukan komitmennya pada prinsip-prinsip HAM.
Dalam kondisi ini, negara justru diharapkan kehadirannya untuk menjamin umat beragama dalam memanifestasikan ajaran agama dan keyakinannya, sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya. Munculnya pembatasan yang dilakukan masyarakat di Nagari Sikabau dan Sungai Tambang menunjukan bahwa negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan untuk umat Kristiani. Padahal, idealnya, negara harus bisa memberikan diskresinya untuk menegakan nilai-nilai HAM, dan KBB khususnya. Sebaliknya, negara justru menormalisasi kesepakatan bersama tersebut yang dianggap sebagai aspirasi dari kepentingan warga di Sumatera Barat. Umat Kristiani di dua wilayah tersebut tidak dijamin hak-haknya untuk menjalankan aktivitas Natal. Ketidakhadiran negara ini justru turut memperkuat intoleransi dalam kehidupan beragama.
Di samping itu, negara dan penegak hukumnya lebih sering diam pada kasus yang menyangkut umat minoritas (bukan hanya dari segi kuantitas), yang sama artinya dengan membiarkan praktik intoleran. Lebih jauh dari itu, di beberapa kasus lain yang bisa ditemukan, negara—yang seharusnya berorientasi pada nilai-nilai HAM—justru berpihak kepada praktik-praktik intoleran, dengan membubarkan aktivitas-aktivitas ibadah umat beragama karena adanya tekanan dari massa seperti yang dialami jemaat GKI Yasmin pada tahun 2010.
Kabar baiknya di beberapa kasus komitmen negara terhadap nilai-nilai HAM sudah mulai ditunjukan, misal, pasca kasus larangan penggunaan atribut Natal yang dilakukan ormas islam (FPI) pada 2015 silam di mal-mal besar di Surabaya, setelah kejadian itu, di tahun-tahun berikutnya, berbagai pejabat publik, mulai dari Menteri Agama, Kapolri, bahkan Presiden, turut memberikan pernyataan untuk melarang aksi “sweeping” atribut Natal—meskipun hal itu belum cukup. Komitmen negara menjadi penting karena turut mempersempit ruang intoleransi dalam masyarakat sekaligus turut menciptakan ruang publik yang aman bagi umat beragama dalam memanifestasikan nilai dan ajaran agama dan keyakinannya.
A. Komitmen Negara terhadap HAM dan Politik Identitas
Perlu diketahui bahwa tidak semua kasus yang menyangkut KBB bisa langsung dijawab. Bahkan seringkali ada kasus-kasus di luar agama yang berkaitan dengan KBB atau sebaliknya. Justru karena belum ada jawaban tersebut, perlu ada diskusi sekaligus menjadi tantangan kita.
Sebagai contoh, kasus yang lebih rumit lagi adalah larangan mengucapkan Selamat Natal oleh anggota Ansharusyariah di Mojokerto, 2014 silam. Dalam laporan tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi, The Wahid Institute tahun 2014, beberapa anggota tersebut mensosialisasikan kepada masyarakat haramnya mengucapkan selamat Natal, mengenakan atribut Natal serta merayakan Natal. Aktivitas ini dilakukan di ruang publik, tepatnya di pusat pertokoan dengan spanduk sekaligus menyebarkan selebaran yang berisikan dalil-dalil Islam tentang pelarangan tersebut.
Sering dijumpai argumen bahwa mengucapkan selamat Natal mengganggu akidah umat Muslim, bahkan hingga tahap “murtad”. Misal, pada tahun yang sama, di 2014, Ketua Dewan Syura Front Pembela Islam (FPI—organisasi yang sudah dibubarkan), Misbachul Anam, menganggap Presiden Jokowi murtad kalau mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani (lebih lanjut, baca: Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad).
Meskipun tidak ada larangan untuk mengekspresikan pendapat seperti itu, tetapi ada beberapa implikasi praktis mengingat adanya penggunaan term “murtad”. Menurut Asfinawati (2014) dalam Advokasi untuk Kebebasan Keagamaan dan Keyakinan: Peluang, Keterbatasan dan Strategi Masa Depan (baca: Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi), term murtad memiliki implikasi serius karena tersedianya berbagai situs dan referensi online mengenai term murtad, seperti “Hukuman Mati bagi Orang Murtad”. Karena penafsiran terhadap term murtad ini tidak boleh dibatasi, termasuk penafsiran yang ekstrim—bahwa orang murtad sah dibunuh, sehingga dapat menimbulkan implikasi eksternum, maka penggunaannya penting untuk dipertimbangkan, bahkan untuk kemungkinan dibatasi (kecuali dengan catatan bahwa pengguna term tersebut memberikan definisi yang jelas).
Namun, pada dasarnya pendapat jenis itu tidak diatur dalam prinsip KBB, melainkan masuk ke dalam ujaran kebencian (hate speech). Tetapi, itu menunjukan bahwa ada keterkaitan antara KBB dengan hak-hak lainnya. Artinya KBB tidak berdiri sendiri, ia saling berkaitan dengan hak-hak lainnya. Begitupun hak-hak lainnya bisa berimplikasi pada KBB.
Terlepas dari itu semua, bentuk-bentuk intoleransi yang menciderai KBB tidak hadir begitu saja. Ia juga memiliki kaitan dengan struktur sosial-politik di Indonesia. Setidaknya ada dua tesis yang berupaya menjelaskan hubungan antara kondisi struktural dengan KBB di Indonesia: (1) adanya transformasi karakter negara pasca reformasi 1998 sehingga memungkinkan muncul dan menguatnya kelompok kekerasan berbasis agama (vigilante groups); (2) proses demokratisasi dan desentralisasi yang memperkuat elit lokal dan politik identitas yang berdampak pada intoleransi. Meskipun dua tesis ini bukan penjelasan satu-satunya, tetapi setidaknya ini membantu kita melihat bagaimana pelanggaran hak KBB dimungkinkan dan semakin masif pasca reformasi.
Yang pertama, karya Ian Wilson (2014) Reconfiguring Rackets: Racket Regimes, Protection and the State in Post-New Order Jakarta menunjukan bahwa adanya perubahan relasi negara dengan umat beragama pasca reformasi yang sebelumnya lebih bersifat patron-klien, berubah menjadi lebih otonom. Negara sebelum reformasi cenderung memonopoli kekerasan, sementara penguasaan dan penggunaan kekerasan pasca reformasi tersebar seturut dengan perubahan negara yang tidak lagi terpusat karena adanya proses demokratisasi dan desentralisasi. Akibatnya, kekerasan yang tersebar tersebut membentuk kelompok-kelompok vigilantis. Hampir sejalan dengan tesis itu, Sidney Jones (2015) Sisi Gelap Demokrasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran menunjukan bahwa “struktur kesempatan politik” yang lebih terbuka memungkinkan tumbuhnya aksi-aksi dan kelompok intoleran. Struktur kesempatan politik tidak hanya dimaknai bahwa negara memungkinkan kelompok vigilantis, tetapi sebaliknya, kelompok vigilantis bisa memanfaatkan negara.
Yang kedua, berkaitan dengan struktur kesempatan politik, proses demokratisasi dan desentralisasi turut menumbuhkan elit lokal. Elit lokal ini berperan penting dalam tumbuhnya politik identitas, yang secara tidak langsung berkontribusi pada bertahannya kelompok-kelompok vigilantis. Michael Buehler (2013) dalam Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing “Shari’a” Politics in Two Indonesian Provinces menunjukan beberapa kasus pilkada dimana kelompok-kelompok vigilantis ini dirawat dan dimobilisasi oleh elit lokal untuk mendulang suara. Di satu sisi elit lokal membawa kepentingan memenangkan pemilu, sementara di sisi lain kelompok vigilantis membawa kepentingannya—seperti menutup kegiatan Ahmadiyah, mencegah pembangunan gereja atau meloloskan perda berbasis agama. Perpaduan kepentingan ini diakomodasi melalui kontrak politik.
Sidney Jones pun melihat adanya hubungan antara fenomena politik tersebut dengan pelanggaran KBB. Misal, kontrak politik elit lokal dengan kelompok-kelompok vigilantis dalam pemenangan pilgub Jawa Barat turut menumbuhkan kelompok-kelompok vigilantis tersebut. Pertumbuhan kelompok itu pun sejalan dengan tingkat pelanggaran hak KBB dimana wilayah Jawa Barat menjadi tempat dengan kekerasan atas nama agama tertinggi. Hal itu dibuktikan dari beberapa kasus—salah satunya persekusi kelompok Ahmadiyah—yang kelompok vigilantis itu sendiri mengklaim bahwa mereka yang melakukannya. Bahkan beberapa aksi didukung oleh beberapa purnawirawan yang memiliki kepentingan politis.
Problem struktural ini juga sama pentingnya. Kasus pelanggaran KBB bukan hanya problem hukum dan penegakannya, melainkan juga menyangkut sosiologis dan historis. Tetapi, poinnya bahwa sejauh mana negara memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip KBB. Banyaknya kasus diskriminasi dan intoleransi setidaknya menjadi tantangan negara untuk mengelola KBB berdasarkan prinsip-prinsip HAM.
B. Intoleransi: Atas nama Ketertiban Umum, Moralitas, Kerukunan
Seperti yang sudah diulas sedikit di atas, bahwa frasa ketertiban umum, moralitas, dan kerukunan seringkali dijadikan dalih untuk melakukan pembatasan KBB. Lebih jauh lagi, dalih itu digunakan masyarakat untuk melakukan pembatasan KBB terhadap kelompok minoritas agama. Sebagaimana yang terjadi di Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, melarang masyarakat merayakan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam rangka menjaga kondusifitas, menghargai syariat Islam, menghindari benturan antar komponen masyarakat, menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Frasa ini dalam interpretasinya sering diterjemahkan pada kondisi yang berbeda-beda. Frasa ini juga sering digunakan untuk menjerat kasus-kasus penodaan agama—dimana seseorang dipidana karena pernyataan atau perbuatannya yang menimbulkan dampak sosial seperti kerusuhan, mobilisasi massa atau yang lebih parah persekusi.
Pertama, harus dilihat apakah perayaan Natal dan tahun baru merupakan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Hal itu tentunya harus merujuk pada definisi aktivitas ketertiban umum itu sendiri. Kedua, ketertiban umum yang terganggu seringkali diasosiasikan dengan munculnya aksi massa, kerusuhan atau persekusi sehingga pendefinisiannya sangat bergantung pada pihak yang merasa terganggu, yang seringkali atas nama mayoritas. Padahal, ketertiban masyarakat terganggu bukan sebagai akibat langsung dari aktivitas perayaan Natal dan tahun baru. Lagi-lagi fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ada berbagai macam faktor seperti demografi masyarakat, relasi kekuasaan, politik identitas dll.
Sama halnya dengan frasa mengganggu kerukunan umat dan moralitas yang dijadikan basis argumen masyarakat untuk membatasi kelompok lain yang lebih rentan. Pendefinisian frasa itu pun sangat bergantung dengan kondisi demografi dan relasi kuasa dalam masyarakat. Kontestasi ini yang masih terus berkembang sekaligus menjadi tantangan KBB di Indonesia, apalagi saat-saat mendekati perayaan Natal.
- 4. Bentuk Pelanggaran KBB dalam Konteks Perayaan Natal
- 5. Tantangan KBB
A. Pembatasan
Meskipun KBB bisa dibatasi, tetapi pembatasannya tidak bisa sembarangan. Yang bisa diuji dari pembatasan KBB pertama-tama adalah justifikasinya. Pada kasus pembatasan ibadah di Kab Aceh Tamiang, justifikasi yang digunakan adalah menghindari konflik horizontal. Tentunya argumen pembatasan ini tidak dijustifikasi dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip KBB. Sama halnya dengan kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin dan umat Kristiani di Singkil sangat berkaitan dengan perizinan tempat ibadah sehingga berimplikasi pada pembatasan KBB. Kedua argumen dari kasus ini juga tidak bisa memiliki legitimasi HAM.
Dengan kata lain, pembatasan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak KBB. Alih-alih menjamin hak warga negara untuk menjalankan beribadah, negara justru membatasi hak warga negaranya tanpa dasar yang diperbolehkan.
Justifikasi lainnya yang tidak tepat bisa dilihat dari kasus yang cukup mengecoh, yaitu larangan menggunakan atribut Natal di beberapa usaha hotel, mal, perkantoran, restoran, yang dilakukan Pemkot Padang dalam rangka menjaga ketenteraman, kenyamanan dan keamanan serta menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Argumentasi pembatasan ini harus dilihat sedikit lebih jeli. Di beberapa kasus pembatasan KBB lainnya yang tidak tepat, negara sering menjustifikasi argumennya dengan term atau frasa untuk menjaga “ketenteraman, kenyamanan dan keamanan”. Term dan frasa ini memang cenderung dan mungkin bisa dilekatkan dengan frasa “ketertiban umum”. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua aktivitas cocok dan tepat dengan kategori itu—contoh-contoh aktivitas yang mengganggu ketertiban umum salah satunya bisa mengacu pada UU KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Pasal 154-181. Acuan tersebut yang perlu digunakan untuk menilai apakah menggunakan atribut termasuk salah satu aktivitas kejahatan terhadap ketertiban umum itu. Dan tentu saja, menggunakan atribut Natal bukanlah aktifitas yang dimaksud.
Artinya, pembatasan tersebut tidak bisa dijustifikasi dan tidak tepat sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan pembatasan tersebut. Dalam konteks ini, negara hanya perlu memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara dalam mengekspresikan keberagamaan dan keyakinannya dengan damai dan tidak ada paksaan, sehingga yang bisa dilakukan negara adalah menjamin tidak adanya paksaan dari pemilik perusahaan swasta kepada umat non-Kristiani untuk memakai atribut Natal dan Sinterklas.
Kasus-kasus itu bisa dikontraskan dengan pembatasan Natal yang dilakukan pemerintah kota Makassar melalui Surat Edaran No. 003.02/419/S. EDAR/DISPAR/XII/2020 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dasar dari pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga kesehatan publik (baca: Cegah Cluster Baru Jelang Tahun Baru, Dispar Makassar Sampaikan Pesan ini untuk Warga Makassar). Tidak hanya untuk umat Kristiani, Pemkot Makassar juga mengeluarkan larangan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan takbir keliling bagi umat muslim untuk mencegah kerumunan orang. Pembatasan itu disampaikan melalui surat edaran Wali Kota Makassar Nomor 400 Tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah (baca: Pemkot Makassar Larang Shalat Idul Fitri di Lapangan Karebosi).
Mengacu pada prinsip KBB setidaknya pembatasan mendapatkan justifikasinya. Tetapi perlu dilihat lagi syarat-syarat lainnya yang lebih jauh seperti apakah pembatasannya ditetapkan oleh hukum (prescribed by law), diperlukan (necessary), proporsional—bahkan kalau bisa less-restrictive dan sesuai konteks, dan penerapannya non-diskriminatif (tidak untuk kelompok tertentu). Dengan begitu, baru kita baru bisa benar-benar menilai bahwa pembatasan dibolehkan dan legitimate. Sebaliknya, apabila prinsip dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembatasan KBB tidak bisa dilakukan dan telah melanggar HAM.
B. Pembiaran
Sebaliknya, ketidakhadiran negara dalam mengelola KBB bisa dilihat sebagai bentuk pengabaian serta tidak adanya komitmen negara dalam menjamin umat beragama dalam beribadah, yang pada gilirannya turut berkontribusi pada menguatnya intoleransi dalam masyarakat. Dalam kasus yang menimpa umat Kristiani di Nagari Sikabau dan Sungai Tambang telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana negara tidak menunjukan komitmennya pada prinsip-prinsip HAM.
Dalam kondisi ini, negara justru diharapkan kehadirannya untuk menjamin umat beragama dalam memanifestasikan ajaran agama dan keyakinannya, sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya. Munculnya pembatasan yang dilakukan masyarakat di Nagari Sikabau dan Sungai Tambang menunjukan bahwa negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan untuk umat Kristiani. Padahal, idealnya, negara harus bisa memberikan diskresinya untuk menegakan nilai-nilai HAM, dan KBB khususnya. Sebaliknya, negara justru menormalisasi kesepakatan bersama tersebut yang dianggap sebagai aspirasi dari kepentingan warga di Sumatera Barat. Umat Kristiani di dua wilayah tersebut tidak dijamin hak-haknya untuk menjalankan aktivitas Natal. Ketidakhadiran negara ini justru turut memperkuat intoleransi dalam kehidupan beragama.
Di samping itu, negara dan penegak hukumnya lebih sering diam pada kasus yang menyangkut umat minoritas (bukan hanya dari segi kuantitas), yang sama artinya dengan membiarkan praktik intoleran. Lebih jauh dari itu, di beberapa kasus lain yang bisa ditemukan, negara—yang seharusnya berorientasi pada nilai-nilai HAM—justru berpihak kepada praktik-praktik intoleran, dengan membubarkan aktivitas-aktivitas ibadah umat beragama karena adanya tekanan dari massa seperti yang dialami jemaat GKI Yasmin pada tahun 2010.
Kabar baiknya di beberapa kasus komitmen negara terhadap nilai-nilai HAM sudah mulai ditunjukan, misal, pasca kasus larangan penggunaan atribut Natal yang dilakukan ormas islam (FPI) pada 2015 silam di mal-mal besar di Surabaya, setelah kejadian itu, di tahun-tahun berikutnya, berbagai pejabat publik, mulai dari Menteri Agama, Kapolri, bahkan Presiden, turut memberikan pernyataan untuk melarang aksi “sweeping” atribut Natal—meskipun hal itu belum cukup. Komitmen negara menjadi penting karena turut mempersempit ruang intoleransi dalam masyarakat sekaligus turut menciptakan ruang publik yang aman bagi umat beragama dalam memanifestasikan nilai dan ajaran agama dan keyakinannya.
A. Komitmen Negara terhadap HAM dan Politik Identitas
Perlu diketahui bahwa tidak semua kasus yang menyangkut KBB bisa langsung dijawab. Bahkan seringkali ada kasus-kasus di luar agama yang berkaitan dengan KBB atau sebaliknya. Justru karena belum ada jawaban tersebut, perlu ada diskusi sekaligus menjadi tantangan kita.
Sebagai contoh, kasus yang lebih rumit lagi adalah larangan mengucapkan Selamat Natal oleh anggota Ansharusyariah di Mojokerto, 2014 silam. Dalam laporan tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi, The Wahid Institute tahun 2014, beberapa anggota tersebut mensosialisasikan kepada masyarakat haramnya mengucapkan selamat Natal, mengenakan atribut Natal serta merayakan Natal. Aktivitas ini dilakukan di ruang publik, tepatnya di pusat pertokoan dengan spanduk sekaligus menyebarkan selebaran yang berisikan dalil-dalil Islam tentang pelarangan tersebut.
Sering dijumpai argumen bahwa mengucapkan selamat Natal mengganggu akidah umat Muslim, bahkan hingga tahap “murtad”. Misal, pada tahun yang sama, di 2014, Ketua Dewan Syura Front Pembela Islam (FPI—organisasi yang sudah dibubarkan), Misbachul Anam, menganggap Presiden Jokowi murtad kalau mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani (lebih lanjut, baca: Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad).
Meskipun tidak ada larangan untuk mengekspresikan pendapat seperti itu, tetapi ada beberapa implikasi praktis mengingat adanya penggunaan term “murtad”. Menurut Asfinawati (2014) dalam Advokasi untuk Kebebasan Keagamaan dan Keyakinan: Peluang, Keterbatasan dan Strategi Masa Depan (baca: Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi), term murtad memiliki implikasi serius karena tersedianya berbagai situs dan referensi online mengenai term murtad, seperti “Hukuman Mati bagi Orang Murtad”. Karena penafsiran terhadap term murtad ini tidak boleh dibatasi, termasuk penafsiran yang ekstrim—bahwa orang murtad sah dibunuh, sehingga dapat menimbulkan implikasi eksternum, maka penggunaannya penting untuk dipertimbangkan, bahkan untuk kemungkinan dibatasi (kecuali dengan catatan bahwa pengguna term tersebut memberikan definisi yang jelas).
Namun, pada dasarnya pendapat jenis itu tidak diatur dalam prinsip KBB, melainkan masuk ke dalam ujaran kebencian (hate speech). Tetapi, itu menunjukan bahwa ada keterkaitan antara KBB dengan hak-hak lainnya. Artinya KBB tidak berdiri sendiri, ia saling berkaitan dengan hak-hak lainnya. Begitupun hak-hak lainnya bisa berimplikasi pada KBB.
Terlepas dari itu semua, bentuk-bentuk intoleransi yang menciderai KBB tidak hadir begitu saja. Ia juga memiliki kaitan dengan struktur sosial-politik di Indonesia. Setidaknya ada dua tesis yang berupaya menjelaskan hubungan antara kondisi struktural dengan KBB di Indonesia: (1) adanya transformasi karakter negara pasca reformasi 1998 sehingga memungkinkan muncul dan menguatnya kelompok kekerasan berbasis agama (vigilante groups); (2) proses demokratisasi dan desentralisasi yang memperkuat elit lokal dan politik identitas yang berdampak pada intoleransi. Meskipun dua tesis ini bukan penjelasan satu-satunya, tetapi setidaknya ini membantu kita melihat bagaimana pelanggaran hak KBB dimungkinkan dan semakin masif pasca reformasi.
Yang pertama, karya Ian Wilson (2014) Reconfiguring Rackets: Racket Regimes, Protection and the State in Post-New Order Jakarta menunjukan bahwa adanya perubahan relasi negara dengan umat beragama pasca reformasi yang sebelumnya lebih bersifat patron-klien, berubah menjadi lebih otonom. Negara sebelum reformasi cenderung memonopoli kekerasan, sementara penguasaan dan penggunaan kekerasan pasca reformasi tersebar seturut dengan perubahan negara yang tidak lagi terpusat karena adanya proses demokratisasi dan desentralisasi. Akibatnya, kekerasan yang tersebar tersebut membentuk kelompok-kelompok vigilantis. Hampir sejalan dengan tesis itu, Sidney Jones (2015) Sisi Gelap Demokrasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran menunjukan bahwa “struktur kesempatan politik” yang lebih terbuka memungkinkan tumbuhnya aksi-aksi dan kelompok intoleran. Struktur kesempatan politik tidak hanya dimaknai bahwa negara memungkinkan kelompok vigilantis, tetapi sebaliknya, kelompok vigilantis bisa memanfaatkan negara.
Yang kedua, berkaitan dengan struktur kesempatan politik, proses demokratisasi dan desentralisasi turut menumbuhkan elit lokal. Elit lokal ini berperan penting dalam tumbuhnya politik identitas, yang secara tidak langsung berkontribusi pada bertahannya kelompok-kelompok vigilantis. Michael Buehler (2013) dalam Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing “Shari’a” Politics in Two Indonesian Provinces menunjukan beberapa kasus pilkada dimana kelompok-kelompok vigilantis ini dirawat dan dimobilisasi oleh elit lokal untuk mendulang suara. Di satu sisi elit lokal membawa kepentingan memenangkan pemilu, sementara di sisi lain kelompok vigilantis membawa kepentingannya—seperti menutup kegiatan Ahmadiyah, mencegah pembangunan gereja atau meloloskan perda berbasis agama. Perpaduan kepentingan ini diakomodasi melalui kontrak politik.
Sidney Jones pun melihat adanya hubungan antara fenomena politik tersebut dengan pelanggaran KBB. Misal, kontrak politik elit lokal dengan kelompok-kelompok vigilantis dalam pemenangan pilgub Jawa Barat turut menumbuhkan kelompok-kelompok vigilantis tersebut. Pertumbuhan kelompok itu pun sejalan dengan tingkat pelanggaran hak KBB dimana wilayah Jawa Barat menjadi tempat dengan kekerasan atas nama agama tertinggi. Hal itu dibuktikan dari beberapa kasus—salah satunya persekusi kelompok Ahmadiyah—yang kelompok vigilantis itu sendiri mengklaim bahwa mereka yang melakukannya. Bahkan beberapa aksi didukung oleh beberapa purnawirawan yang memiliki kepentingan politis.
Problem struktural ini juga sama pentingnya. Kasus pelanggaran KBB bukan hanya problem hukum dan penegakannya, melainkan juga menyangkut sosiologis dan historis. Tetapi, poinnya bahwa sejauh mana negara memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip KBB. Banyaknya kasus diskriminasi dan intoleransi setidaknya menjadi tantangan negara untuk mengelola KBB berdasarkan prinsip-prinsip HAM.
B. Intoleransi: Atas nama Ketertiban Umum, Moralitas, Kerukunan.
Seperti yang sudah diulas sedikit di atas, bahwa frasa ketertiban umum, moralitas, dan kerukunan seringkali dijadikan dalih untuk melakukan pembatasan KBB. Lebih jauh lagi, dalih itu digunakan masyarakat untuk melakukan pembatasan KBB terhadap kelompok minoritas agama. Sebagaimana yang terjadi di Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, melarang masyarakat merayakan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam rangka menjaga kondusifitas, menghargai syariat Islam, menghindari benturan antar komponen masyarakat, menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Frasa ini dalam interpretasinya sering diterjemahkan pada kondisi yang berbeda-beda. Frasa ini juga sering digunakan untuk menjerat kasus-kasus penodaan agama—dimana seseorang dipidana karena pernyataan atau perbuatannya yang menimbulkan dampak sosial seperti kerusuhan, mobilisasi massa atau yang lebih parah persekusi.
Pertama, harus dilihat apakah perayaan Natal dan tahun baru merupakan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Hal itu tentunya harus merujuk pada definisi aktivitas ketertiban umum itu sendiri. Kedua, ketertiban umum yang terganggu seringkali diasosiasikan dengan munculnya aksi massa, kerusuhan atau persekusi sehingga pendefinisiannya sangat bergantung pada pihak yang merasa terganggu, yang seringkali atas nama mayoritas. Padahal, ketertiban masyarakat terganggu bukan sebagai akibat langsung dari aktivitas perayaan Natal dan tahun baru. Lagi-lagi fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ada berbagai macam faktor seperti demografi masyarakat, relasi kekuasaan, politik identitas dll.
Sama halnya dengan frasa mengganggu kerukunan umat dan moralitas yang dijadikan basis argumen masyarakat untuk membatasi kelompok lain yang lebih rentan. Pendefinisian frasa itu pun sangat bergantung dengan kondisi demografi dan relasi kuasa dalam masyarakat. Kontestasi ini yang masih terus berkembang sekaligus menjadi tantangan KBB di Indonesia, apalagi saat-saat mendekati perayaan Natal.