Ringkasan:
● Pemaksaan jilbab sejak dini dapat menimbulkan luka psikologis karena mengabaikan tubuh dan pengalaman anak.
● Religious trauma lahir dari praktik agama yang menekan melalui kontrol tubuh, relasi kuasa, dan simbol kepatuhan.
● Pendidikan agama yang sehat menuntut empati, pilihan sadar, dan penghormatan terhadap pengalaman manusiawi.
Oleh: Arina Rahmatika | Republikasi dari GUSDURian
Agama sering kali diposisikan sebagai sumber nilai, moral, dan ketenangan batin. Ia diajarkan sebagai jalan menuju kebaikan, kasih sayang, dan kedekatan dengan Tuhan. Namun, dalam praktik sosial, agama tidak selalu hadir dengan wajah yang lembut. Dalam banyak pengalaman hidup, terutama pada masa kanak-kanak, agama justru dapat tampil sebagai ruang yang penuh tekanan, paksaan, dan pengabaian terhadap pengalaman manusiawi. Dari sinilah muncul religious trauma (trauma religius).
Istilah religious trauma merujuk pada luka psikologis yang muncul akibat pengalaman beragama yang menindas, menghakimi, atau memaksa. Trauma ini bukan disebabkan oleh keyakinan spiritual semata, melainkan oleh cara agama disampaikan—sering kali melalui relasi kuasa, disiplin tubuh, dan kontrol sosial. Pengalaman semacam ini kerap dialami sejak usia dini, ketika individu belum memiliki kapasitas kognitif maupun emosional untuk memahami ajaran agama secara utuh.
Aku masih mengingat dengan jelas pengalaman masa kecilku saat bersekolah di sebuah Sekolah Islam Terpadu. Sejak taman kanak-kanak, jilbab diposisikan sebagai kewajiban mutlak bagi murid perempuan. Tidak ada ruang dialog, tidak ada penjelasan yang membumi tentang makna atau tujuannya. Yang ada hanyalah aturan yang harus dipatuhi. Setiap hari, dari pagi hingga siang, jilbab harus dikenakan, terlepas dari kondisi tubuh, cuaca, atau kenyamanan.
Sebagai anak kecil yang tinggal di kota Semarang dengan iklim panas dan lembap, tubuhku bereaksi. Kulit kepalaku menjadi gatal, muncul biang keringat, bahkan beruntusan yang menimbulkan rasa perih. Rasa sakit itu bukan sekadar ketidaknyamanan fisik, melainkan juga tekanan emosional. Setiap hari aku harus menahan rasa gatal dan panas demi memenuhi kewajiban yang tidak kupahami. Tubuhku memberi sinyal, tetapi sinyal itu tidak pernah dianggap penting.
Hingga suatu hari, tubuh ini mencapai batasnya. Aku melepas jilbabku. Keputusan itu bukan lahir dari kesadaran ideologis atau penolakan terhadap agama, melainkan dari kebutuhan paling dasar seorang anak, yaitu menghindari rasa sakit. Namun, respons lingkungan sangat jauh dari empati. Aku diejek oleh teman-temanku, bahkan oleh anak-anak laki-laki yang juga masih duduk di bangku TK. Ejekan tersebut menempelkan stigma pada tubuhku; bahwa tubuh perempuan yang tidak sesuai dengan aturan agama pantas dipermalukan.
Yang lebih menyakitkan adalah sikap guru. Sebagai figur otoritas dan pengasuh, guru seharusnya menjadi pelindung. Namun, yang kuterima justru pembiaran. Tidak ada pembelaan, tidak ada upaya untuk memahami kondisi fisikku, dan tidak ada afirmasi bahwa rasa sakit itu nyata. Dalam diamnya guru tersebut, tersirat pesan kuat bahwa kepatuhan terhadap simbol agama lebih penting daripada kesehatan dan perasaan seorang anak.
Pengalaman ini menunjukkan bagaimana agama, melalui institusi pendidikan, dapat beroperasi sebagai mekanisme kontrol tubuh, khususnya tubuh perempuan. Jilbab, yang dalam wacana dewasa sering dibicarakan sebagai simbol kesalehan atau identitas religius, dalam pengalaman anak justru menjadi alat disiplin. Tubuh anak perempuan diajarkan untuk patuh, menahan sakit, dan menerima ketidaknyamanan sebagai konsekuensi menjadi “anak baik” atau “anak salehah”.
Inilah titik krusial munculnya religious trauma. Trauma tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik yang ekstrem. Ia sering lahir dari pengalaman berulang tentang pengabaian, rasa malu, dan pemaksaan. Dalam konteks ini, agama menjadi sesuatu yang diasosiasikan dengan rasa takut, rasa bersalah, dan luka, bukan dengan cinta atau ketenangan. Ingatan tentang jilbab tidak lagi netral, tetapi sarat emosi negatif yang bertahan hingga bertahun-tahun kemudian.
Religious trauma juga berkaitan erat dengan pengalaman diskriminasi. Dalam kasus ini, diskriminasi terjadi pada beberapa level sekaligus: diskriminasi usia (karena anak tidak dianggap mampu menentukan kebutuhan tubuhnya), diskriminasi gender (karena tubuh perempuan yang dikontrol), dan diskriminasi pengalaman (karena rasa sakit dianggap tidak relevan). Pemaksaan jilbab sejak dini sering kali dibingkai sebagai “pendidikan moral”, padahal di baliknya terdapat praktik ketidakadilan yang jarang disadari.
Lebih jauh, pengalaman ini memperlihatkan bagaimana institusi keagamaan kerap gagal membedakan antara nilai dan simbol. Nilai agama seperti kasih sayang, rahmah, dan keadilan justru terpinggirkan demi simbol kepatuhan visual. Padahal, ketika simbol dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi manusia, yang lahir bukanlah kesalehan, melainkan keterasingan.
Dampak religious trauma tidak berhenti di masa kanak-kanak. Ia dapat muncul kembali dalam bentuk kegamangan beragama, jarak emosional dengan simbol-simbol keagamaan, atau rasa bersalah yang berlebihan ketika menjalankan atau meninggalkan praktik tertentu. Bagi sebagian orang, trauma ini membuat agama terasa seperti ruang yang penuh tuntutan dan penghakiman. Bagi yang lain, hal ini memicu konflik batin antara iman dan pengalaman luka.
Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap pemaksaan jilbab bukanlah penolakan terhadap jilbab itu sendiri. Banyak perempuan dewasa memilih berjilbab dengan kesadaran, cinta, dan keyakinan yang mendalam. Dalam konteks pilihan bebas, jilbab dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas. Namun, makna itu runtuh ketika jilbab dikenakan dalam situasi tanpa pilihan, terutama pada anak-anak.
Agama yang sehat adalah agama yang tumbuh bersama kesadaran, bukan melalui rasa takut. Pendidikan agama seharusnya dimulai dari nilai-nilai kemanusiaan: empati, penghormatan terhadap tubuh, dan pengakuan atas pengalaman personal. Anak-anak perlu diajak memahami, bukan sekadar disuruh patuh. Mereka perlu merasa aman, bukan merasa diawasi dan dihakimi.
Membicarakan religious trauma adalah langkah penting untuk merefleksikan ulang cara kita mengomunikasikan agama. Ini bukan upaya untuk melemahkan iman, melainkan justru menyelamatkannya dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri. Mengakui bahwa agama bisa melukai bukan berarti agamanya yang salah, tetapi cara kita mengajarkannya yang perlu diperbaiki.
Pengalaman kecil seperti yang kualami mungkin sering dianggap sepele. Namun, bagi seorang anak, pengalaman itulah yang membentuk relasi awal dengan agama. Jika relasi itu dibangun di atas rasa sakit dan malu, luka tersebut akan dibawa hingga dewasa. Oleh karena itu, refleksi ini menjadi pengingat bahwa masa depan keberagamaan seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana agama pertama kali hadir dalam hidupnya: sebagai pelukan, atau sebagai luka.
Editor: Andrianor









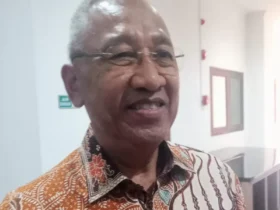
Leave a Reply