Oleh: Yogi Febriandi (Indonesian Scholars Network on Freedom of Religion or Belief [ISFoRB])
Perdebatan tentang posisi negara dalam melihat ateisme telah ada bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Dalam perumusan Pancasila, sila pertama yang menggunakan kata “ketuhanan” menghadirkan perdebatan sengit dalam melihat posisi agama dalam konstitusi negara (Fachrudin, 2016). Ujung dari perdebatan ini ialah adanya pengakuan tegas kewajiban negara dalam melayani warga negara tentang urusan agama.
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28E UUD 1945, di mana negara memberikan kebebasan untuk menganut, meninggalkan, dan kembali menganut agama. Namun, tidak adanya penjelasan terkait posisi orang-orang yang tidak menganut agama melahirkan persoalan terhadap hak untuk tidak menganut agama bagi kelompok ateisme di Indonesia. Kini, setelah terbitnya KUHP baru pada 2023, persoalan hak untuk tidak menganut agama di Indonesia kian mendesak untuk dibahas. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dengan putusan nomor 146/PUU-XXII/2024 yang mempertegas kewajiban warga negara untuk memilih afiliasi agama akan mempermudah upaya kriminalisasi pada kelompok ateisme.
Esai ini akan membahas kerentanan Pasal 302 ayat 1 KUHP yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok ateisme. Menggunakan perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Esai ini mendorong penafsiran yang proporsional terhadap kata “menghasut” dalam Pasal 302 ayat 1 KUHP untuk memberikan keadilan yang setara, baik bagi kelompok beragama atau pun kelompok ateisme.
Dua Wajah Negara pada Pasal 302
Baik dalam KUHP lama atau pun KUHP baru, ateisme atau tidak beragama tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan yang melarangnya. Dalam KUHP 2023, yang diatur ialah larangan tindakan “menghasut” pandangan ateisme. Pasal 302 ayat 1: “Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
Meski begitu, kerentanan terhadap pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan bukan berarti tidak ada. Pada ayat 1 Pasal 302 KUHP secara langsung melarang perbuatan penghasutan tanpa adanya unsur lain, seperti pemaksaan dan kekerasan. Bila kita melihat ayat 2 Pasal 302, terdapat frasa “pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang muncul bersamaan dengan “berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia”. Perbedaan ini bukan hanya memberi tekanan berbeda terhadap kategori pidana dan denda, tetapi memperlihatkan perbedaan sikap negara dalam melihat penyebaran ide agama dan ateisme.
Sebagai contoh, diskusi atau tayangan yang memuat ide ateisme, akan rentan dianggap sebagai penghasutan untuk meninggalkan agama. Sedangkan diskusi atau tayangan yang memuat ide agama tertentu yang mengajak seseorang untuk berpindah agama tidak dapat dipidanakan sebelum ada unsur pemaksaan atau ancaman. Jadi, meskipun menurut Bagir (2023) bahwa Pasal 302 telah cukup baik karena tidak mengatur soal apostasy (murtad), tetapi secara proporsional pasal ini menunjukkan pembatasan penyebaran ateisme. Pada ayat 2 harus memenuhi unsur ajakan yang memaksa dan berpotensi melahirkan kekerasan baru akan masuk pada kategori pidana.
Mengapa Perlu Tafsir yang Adil?
Dalam buku Penafsiran Pasal 300-305 KUHP yang diterbitkan ISFORB, kata “menghasut” tidak hanya berimplikasi pada KBB, tetapi juga beririsan dengan kebebasan berekspresi. Hal ini karena pada Pasal 300 KUHP, kata menghasut dimaknai sebagai tindakan yang “harus dilakukan di muka umum” dan di “khalayak ramai dapat mengetahui”.
Bila melihat pada berbagai literatur tentang ateisme di Indonesia, ruang publik bukanlah arena yang setara bagi kelompok ateisme.
Schafer (2016) melihat sering kali kelompok ateisme mengalami kriminalisasi dari negara karena visibilitas mereka di ruang publik. Hal ini dapat terlihat pada kasus Alexander Aan pada 2012, di mana ia dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama hanya karena ia membagikan postingan terkait ateisme di halaman facebook yang ia buat. Jagok (2018) yang melakukan penelitian terhadap kasus Aan, memperlihatkan proses kriminalisasi tersebut dilakukan oleh cara Hakim menafsirkan Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama.
Meski visibilitas ateisme di ruang publik di Indonesia rentan terhadap upaya krimininalisasi, tetapi pertumbuhan konten kreator yang mengaku secara terang-terangan sebagai ateis tetap bermunculan. Duile (2024) melihat para konten kreator ini aktif mempromosikan ateisme sebagai gaya hidup baru di Indonesia. Meski kasus kriminalisasi kelompok ateisme sangat sedikit jumlahnya, tetapi meningkatnya jumlah konten yang berhubungan dengan ateisme di media sosial akan menjadi bom waktu apabila kata “menghasut” tidak ditafsirkan secara adil.
Sangat mungkin bagi kelompok ateisme visibilitas mereka di ruang publik adalah bagian dari kebebasan ekspresi, tetapi akan ditafsirkan sebagai tindakan menghasut oleh kelompok mainstream. Hal ini semakin dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2025 yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus memiliki agama atau kepercayaan dalam kolom KTP. Putusan ini berpotensi mempersempit ruang bagi ateisme di Indonesia.
Negara harus memastikan bahwa pasal ini tidak digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi cakupan tafsir “menghasut” pada tindakan penghasutan yang jelas-jelas mengarah pada kekerasan atau konflik sosial. Untuk itu diperlukan panduan bagi aparat penegakan hukum dalam menafsirkan pasal 302 KUHP.
Pentingnya Perspektif KBB
Tafsiran soal “menghasut” perlu penjelasan yang lebih detail dan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak untuk tidak beragama. Ketidakjelasan definisi “menghasut” dalam pasal ini membuka ruang bagi interpretasi subjektif yang dapat merugikan individu yang memilih untuk tidak beragama.
Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang tidak kabur dan dapat menjembatani keadilan pembatasan penyiaran ide agama atau keyakinan pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 302. Untuk membuat frasa “menghasut” tidak kabur dapat digunakan model tafsir yang ditawarkan ISFORB di buku Penafsiran Pasal 300-305 KUHP yang merujuk pada Prinsip Camden. Dalam prinsip ini, hasutan dilihat dari tingkat timbulnya risiko langsung berupa diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut.
Berarti perbuatan menghasut yang dapat dipidanakan pada Pasal 302 ayat 1 apabila terbukti secara langsung mengakibatkan tindakan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dari kajian tentang ateisme di Indonesia, terlihat stigma buruk masyarakat terhadap orang-orang tidak beragama masih sangat kuat. Bukan tidak mungkin kriminalisasi ateisme akan menjadi masalah di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada penafsiran progresif terhadap Pasal 302 ayat 1 KUHP agar tidak menjadi alat mengekang hak tidak beragama sekaligus menjamin ekspresi kelompok ateisme di Indonesia.
Selain memikirkan model penafsiran yang berperspektif KBB pada Pasal 302 ayat 1, negara mungkin perlu juga melihat kembali substansi dari Pasal 302 secara keseluruhan. Pasal ini hanya mengatur soal hasutan dan ajakan dengan paksa seseorang untuk keluar dari agama. Bagaimana penghasutan dengan maksud memaksa seseorang agar tetap pada agamanya? Seperti yang kita ketahui bersama pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015, seseorang dihukum cambuk apabila keluar dari agama Islam.




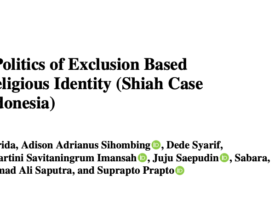

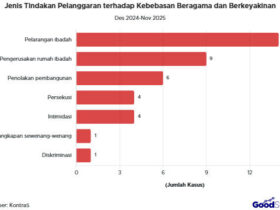
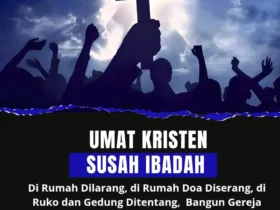

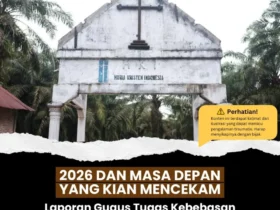

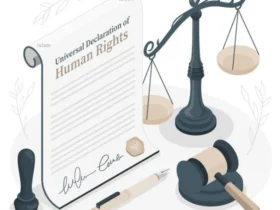
Leave a Reply