Oleh: Ahsan Jamet Hamidi (Anggota Dewan Pengarah Sekretariat Bersama KBB Indonesia)
“Jika masyarakat adat adalah perambah hutan, maka sejak ribuan tahun lalu, hutan yang ada di sekitar tempat tinggal kami pasti sudah habis terbabat dan berubah menjadi hamparan tanah tandus tak berpohon.”
Pernyataan seorang tokoh adat di pedalaman Kalimantan Timur itu begitu melekat dalam ingatan saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di hutan-hutan lebat Kalimantan Timur. Cara pandang masyarakat adat terhadap alam yang mereka tinggali sangat bertolak belakang dengan masyarakat yang pro terhadap aktivitas industri ekstraktif. Jika masyarakat adat memiliki keterikatan hubungan secara ruhani dengan tanah, air, tumbuhan, hewan, dan segala makhluk hidup yang terkandung di dalamnya, masyarakat industri bersikap sebaliknya.
Masyarakat adat akan sangat berhati-hati dan penuh cinta dalam memperlakukan alam. Mereka memang memanfaatkan hasilnya, namun dengan cara yang terbatas, cermat, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, masyarakat industri mengeruk dan membabat habis-habisan karena orientasi mereka adalah mengambil untung, menjual hasilnya dengan harga setinggi-tingginya untuk menumpuk kekayaan. Jika masyarakat adat mengambil hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar, masyarakat industri melakukannya demi memenuhi keserakahan. Praktik keduanya terhadap alam sangat bertolak belakang.
Dalam pertemuan bersama para pegiat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diselenggarakan oleh SEKBER KBB di Tomohon pada awal September lalu, keprihatinan terhadap peminggiran dan pengabaian hak-hak masyarakat adat serta praktik perusakan lingkungan kembali mencuat. Ketika lingkungan sudah hancur, masyarakat adat yang selama ini tinggal di sekitar wilayah industri ekstraktif harus menerima dampak kerugian ganda yang merusak tata kehidupan sosial mereka.
Industri ekstraktif yang saya maksud adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan cara menggali dan mengolah sumber daya alam yang diambil langsung dari bumi untuk dijadikan bahan baku. Misalnya, industri pertambangan (minyak, gas, batu bara, mineral), serta industri kehutanan.
Samsul Maarif dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS UGM) mengatakan bahwa masyarakat adat yang berani menolak atau bersikap kritis terhadap aktivitas industri ekstraktif di wilayah mereka akan mengalami beban ganda. Mereka tidak hanya dicap sebagai warga primitif, kuno, anti-kemajuan, dan penghambat pembangunan, tetapi juga terancam kehilangan akses terhadap alam dan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, hak asasi mereka atas pengelolaan sumber daya alam secara otomatis ikut terhambat.
Masuknya industri ekstraktif berskala besar dan bermodal sangat besar telah menyingkirkan eksistensi masyarakat adat. Mereka terkalahkan oleh industri besar, canggih, dan modern. Kehadiran industri tersebut telah mengubah status dan peran sosial warga adat: dari pengelola lahan secara mandiri menjadi buruh industri; dari warga yang bisa bekerja secara merdeka menjadi buruh yang harus mengikuti ritme kerja ala industri. Jika tidak mampu mengikuti irama itu, maka secara alamiah mereka akan tersingkir, menjauh, dan melepaskan diri dari jati dirinya sebagai manusia merdeka.
Peran Agama
Dalam kondisi seperti itu, beragam pandangan muncul dalam diskusi tersebut. Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya agama (maksudnya para pemangku agama) memiliki peran penting di dua sisi sekaligus.
Di satu sisi, para pemangku agama dapat berpihak pada masyarakat adat yang tersingkir, menemani mereka dalam proses mengkritisi praktik operasional industri yang cenderung tidak ramah terhadap alam sekitar. Namun, di sisi lain, tak jarang para pemuka agama justru larut dalam arus masyarakat industri yang menganggap keberadaan masyarakat adat sebagai penghalang. Selain itu, ada juga anggapan bahwa masyarakat adat telah memiliki tradisi dan ritual keimanan yang tidak selaras dengan agama yang mereka anut. Pilihannya: masyarakat adat harus ditarik masuk ke dalam lingkungan agama mereka, atau dianggap sebagai “orang lain” yang bukan bagian dari kelompoknya.
Dalam pertemuan lalu, saya tersentuh oleh cerita Jull Takaliung, seorang aktivis perempuan dari Sangihe, Sulawesi Utara. Wilayahnya mulai rusak dan lautnya tercemar akibat pertambangan ilegal. Sikapnya tegas dan pandangannya kritis: bahwa proses masuknya industri ekstraktif yang merambah kawasan hutan dan lahan milik adat tidak lepas dari strategi pendekatan industri yang lihai dalam menaklukkan sikap para tokoh adat, ketua lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat. Mereka menjadi lunak dan mengabaikan kerusakan lingkungan serta aksi penaklukan yang begitu sistematis. Iming-iming kekuasaan dan uang memang sangat menggiurkan, hingga mampu mengubah pandangan hidup seseorang.
Pendeta Johan Kristantara dari PGI juga memiliki pandangan kritis terhadap sikap dan cara sebagian tokoh agama dalam memanfaatkan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar argumentasi mereka. Ada yang menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai basis kebenaran dalam perjuangan merawat alam dan lingkungan dengan penuh cinta. Namun, ada juga yang menukil sebagian ayat lalu menafsirkannya demi kepentingan pragmatis. Tafsir mereka terhadap Alkitab digunakan untuk membenarkan aksi eksploitasi alam yang serakah dan habis-habisan oleh perusahaan. Hal ini sangat tergantung pada keteguhan sikap para pemangku agama yang bersangkutan. Praktik kedua pendekatan ini nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Hemat saya, perjalanan masyarakat adat dalam merawat alam bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan dari harmoni yang telah terjalin secara spiritual dan sosial selama berabad-abad. Hadirnya industri ekstraktif dengan segala dampak negatifnya telah menggeser posisi masyarakat adat: dari pengelola alam yang lestari dan mandiri menjadi pihak yang tersisih dan terkekang. Dalam konteks ini, peran para pemangku agama sangat strategis dan menentukan. Mereka memiliki peluang besar untuk menjadi pendamping sekaligus penyeimbang dalam perjuangan masyarakat adat—atau sebaliknya, berisiko menjadi bagian dari arus yang mengabaikan keberpihakan kepada yang lemah.




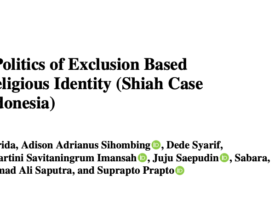

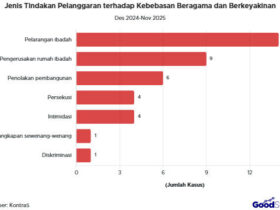
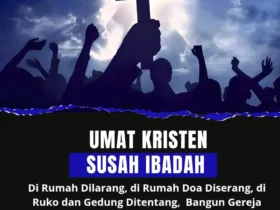

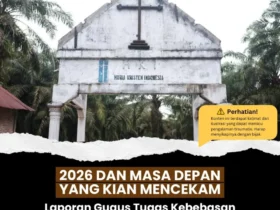

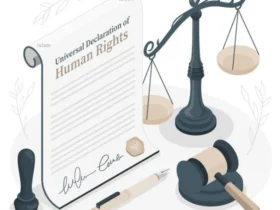
Leave a Reply