Oleh: Ahsan Jamet Hamidi | Anggota Dewan Pengarah Sekber KBB
Dalam sebuah acara diskusi bertema “Memperkuat Mediasi, Memperkokoh Kerukunan” yang diselenggarakan oleh PUSAD Paramadina dan Komnas HAM pada 3 Februari 2025 di Kampus Universitas Paramadina, seorang teman bertanya, “Kenapa harus ada mediasi bagi para pemeluk agama? Bukankah mereka adalah orang-orang baik yang selalu berjuang untuk mewujudkan kebaikan bagi sesama?” Pertanyaan itu diajukan di tengah acara diskusi.
Saya tidak mampu menjawab pertanyaan itu, namun saya memakluminya. Pertanyaan tersebut diajukan dengan tulus oleh seorang teman yang, sepengetahuan saya, belum memutuskan agama yang akan dianutnya. Ia masih terus melakukan observasi dengan cermat, belajar memahami berbagai ajaran agama, serta melihat langsung praktik keseharian para penganut agama-agama besar di Indonesia.
Beruntung, PUSAD Paramadina telah menyiapkan TOR acara yang menjelaskan dengan gamblang latar belakang diskusi tentang mediasi tersebut. Bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam memperkokoh kerukunan. Salah satunya adalah konflik antar-komunitas penganut agama yang sering memunculkan kekerasan.
Contoh terburuknya adalah konflik yang dipicu oleh penolakan terhadap aliran tertentu, seperti Ahmadiyah atau Syiah, yang memakan korban jiwa. Selain itu, ketegangan terkait pendirian rumah ibadah juga sering memicu konflik. Konflik-konflik semacam ini tentu mengganggu kerukunan antarwarga. Oleh karena itu, PUSAD Paramadina berinisiatif untuk membangun pendekatan mediasi yang dapat digunakan dalam menangani konflik-konflik berbasis agama.
Mengapa Harus Berkonflik?
Pertanyaan sederhana ini juga sering muncul di hati saya: Mengapa orang-orang beragama harus berkonflik? Padahal, semua agama yang saya kenal selalu mengajarkan kebaikan. Semua ajaran agama bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia di bumi ini.
Ajaran-ajaran yang paling banyak disyiarkan oleh semua agama berkisar pada kejujuran, menepati janji, berbaik sangka, menyantuni anak yatim, berpihak pada orang lemah, tidak mengambil barang atau uang yang bukan miliknya, bertanggung jawab atas amanah, tidak berzina, bertanggung jawab kepada keluarga, menjaga kelestarian lingkungan, serta mematuhi aturan hukum dan pranata sosial.
Itulah sisi kemuliaan ajaran agama yang biasa diajarkan di sekolah, tempat ibadah, forum pengajian, dan berbagai acara keagamaan. Namun, mengapa dalam praktiknya bisa terbalik? Seorang penganut agama bisa berubah menjadi pribadi yang mudah marah, penuh kebencian, dan bahkan di era media sosial ini, seseorang yang identik dengan atribut agama, tetapi bisa menyebarkan informasi bohong tanpa merasa bersalah. Padahal, ajaran agama sangat jelas aturannya bahwa menyebarkan informasi yang mengandung fitnah adalah kesalahan besar, bahkan lebih kejam daripada pembunuhan.
Perilaku yang saya sebutkan di atas mungkin terjadi pada skala kecil. Meskipun hal itu bisa memicu konflik, skala konfliknya tetap kecil dan mungkin hanya terjadi antar individu. Namun, konflik yang berskala besar bisa dipicu oleh persoalan yang lebih besar, seperti penyerobotan lahan oleh korporasi. Tanah adalah sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan bagi warga. Konflik antar suporter sepak bola pun bisa membesar karena fanatisme yang berlebihan.
Hal yang cukup mengherankan saya adalah konflik yang mengatasnamakan agama. Ia bisa berkembang menjadi konflik yang sangat besar dan berlarut-larut.
Sejarah Perluasan Penganut dan Pengajaran Agama
Terkait dengan penyebab yang bisa memicu konflik berbasis agama, hasil observasi saya menemukan beberapa kenyataan berikut:
Sejarah perluasan pengikut dan pengajaran agama di masa lalu yang masih dipraktikkan saat ini turut berperan dalam memprovokasi para penganut agama untuk berkonflik. Akhirnya muncul sikap fanatik dan gairah berkonflik yang bisa memicu perang, karena bias bacaan tentang sejarah masa lalu. Tidak hanya di situ, karakter dan kepribadiannya juga semakin sensitif terhadap perkembangan hal-hal baru yang terjadi di luar dirinya. Sensitivitas yang berlebihan itu telah menjadikan dirinya pribadi yang selalu merasa terancam—baik ancaman terhadap aqidah maupun agama yang dianutnya.
Jujur, saya kesulitan dalam membedakan, apakah ancaman itu terkait dengan kepentingan aqidah, agama, atau kepentingan pribadi seseorang yang terkait dengan uang, kekuasaan, bisnis, jabatan, atau peluang kerja.
Banyak cerita sejarah yang menggambarkan bagaimana perluasan ajaran agama dilakukan melalui perang. Namun, saya belum menemukan jawaban pasti, apakah pemicu perang yang mengatasnamakan agama itu karena ambisi perluasan wilayah kekuasaan oleh para pemimpin agama, penguasa kerajaan, atau negara, ataukah karena ambisi para pemuka agama yang ingin memperbanyak jumlah pengikutnya. Ada juga yang meyakini bahwa perang itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, dan melawan kemungkaran. Nalar sehat saya berusaha untuk bisa membedakannya.
Dalam pengalaman pribadi saya mengikuti kelas tentang agama di berbagai lembaga pendidikan, saya menemukan bahwa agama sering diajarkan dengan cara yang selalu menganggap agama lain sebagai kompetitor. Hal itu mungkin didasari atas bacaan sejarah panjang tentang peperangan yang mengatasnamakan agama di masa lalu. Para pelajar telah didoktrin sedemikian rupa bahwa keberadaan mereka di dunia ini menjadi terancam, bisa menjadi korban hanya karena agama yang dianutnya. Ada penganut agama lain yang siap menerkam dan memusnahkan agama lain yang tidak sama dengan dirinya. Betulkah seperti itu? Mari kita lihat bersama.
Akibatnya, para penganut agama—alih-alih bisa hidup semakin damai—tetapi selalu ada dalam suasana penuh ancaman. Bisa dibayangkan, bagaimana sikap para murid yang telah lulus belajar agama di sekolah yang mengajarkan materi agama dengan pola semacam itu. Tidak heran apabila muncul individu-individu yang semakin agamis, namun karakter dan perilakunya belum selaras dengan ajaran kebaikan agamanya. Jauh dari itu, mereka tumbuh menjadi pribadi yang fanatik, penuh kebencian, selalu merasa terancam, dan bersiap siaga untuk berperang melawan pengikut agama lain. Alasannya, mereka harus membela aqidah dan agama dengan raga dan nyawa mereka.
Agama Menjadi Korban
Memang ada catatan sejarah yang menggambarkan konflik dan perang antaragama. Namun demikian, catatan sejarah itu perlu dibaca dengan cermat dan penggalian sumber informasi yang lebih lengkap, sehingga kita bisa memahami konteks sejarah dari sudut pandang yang komplit. Catatan sejarah masa lalu sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai alat provokasi untuk menyuburkan fanatisme dan permusuhan antar pemeluk agama.
Saya menduga, penggunaan agama dalam konflik antarindividu atau kelompok, dilakukan oleh orang-orang yang sejatinya takut untuk terlibat dalam konflik sendirian. Memanfaatkan sikap fanatik buta yang menimpa sebagian orang dalam beragama akan sangat menguntungkan untuk mendapatkan dukungan secara mudah. Mereka lihai membungkus masalah dan kepentingan pribadi dengan bungkus berjargon agama hingga menyamarkan masalah sebenarnya. Orang lain tidak mampu membedakan antara kepentingan pribadi atau kepentingan untuk membela agama.
Hemat saya, agama harus ditempatkan pada posisi yang tepat sebagai sumber ajaran yang dapat menjadikan hidup manusia lebih damai, aman, dan penuh kemaslahatan. Jika beragama tetapi hanya menumbuhkan sikap penuh kebencian dan perang, saya yakin bahwa praktik keagamaan itu telah melenceng dari cita-cita sejati agama.









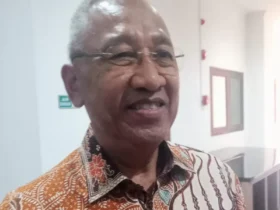
Leave a Reply