Oleh: Arina Rahmatika (Dosen; Penggerak Komunitas GUSDURian Jogja) | Republikasi dari GUSDURian
Sebagai seorang perempuan Muslim yang menggunakan jilbab, saya sering kali merasa berada di posisi mayoritas yang relatif aman. Sejak pertama kali memutuskan untuk mengenakan jilbab, saya jarang dipertanyakan, apalagi dipersoalkan. Bagi sebagian besar orang di sekitar saya, jilbab adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan pada agama. Namun, pengalaman itu membuat saya justru merenung, apakah kenyamanan yang saya rasakan lantas membuat saya dapat memaksakan orang lain agar menggunakan jilbab? Apakah karena saya merasa benar dengan pilihan berjilbab, maka semua orang harus mengikuti cara saya berpakaian, bahkan mereka yang berbeda keyakinan?
Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiran saya setiap kali muncul berita pemaksaan jilbab di sekolah negeri. Kasus terbaru yang ramai diperbincangkan adalah di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, pada 2022. Seorang siswi dipaksa mengenakan jilbab oleh pihak sekolah, padahal ia bukan beragama Islam. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas, membuka kembali luka lama tentang wajah intoleransi yang masih mengakar di dunia pendidikan kita. Dan yang lebih menyedihkan, peristiwa ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir.
Fenomena Gunung Es di Sekolah Negeri
Jika ditelusuri, kasus Bantul hanyalah puncak dari fenomena gunung es. Di Sumatera Barat, Januari 2021, siswi non-Muslim bernama JCH dipaksa mengenakan jilbab. Ketika menolak, ia sampai harus membuat pernyataan terbuka di media sosial agar suaranya didengar. Kasus serupa pernah terjadi di Rokan Hulu, Riau, pada 2018, dengan pola yang sama yaitu siswi non-Muslim ditekan oleh pihak sekolah untuk mengikuti aturan berjilbab.
Ironisnya, diskriminasi tidak hanya berupa pemaksaan jilbab, tapi juga pelarangan jilbab. Di Nias dan Manokwari, pada 2022, siswi Muslimah justru dilarang memakai jilbab di sekolah negeri. Dua peristiwa yang tampak bertolak belakang ini memperlihatkan hal yang sama yaitu ketika sekolah masih gagal memahami prinsip kebebasan beragama. Di satu tempat, jilbab dianggap wajib untuk semua orang. Di tempat lain, jilbab dianggap terlarang. Akibatnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang inklusif justru berubah menjadi arena diskriminasi yang menekan identitas siswa.
Jilbab dan Hak Asasi Manusia
Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hak untuk memiliki, memilih, berganti, atau meninggalkan agama atau keyakinan adalah hak mutlak. Hak ini tidak boleh diganggu gugat dalam keadaan apa pun. Negara boleh mengatur sebatas pada manifestasi keagamaan di ruang publik, tapi itu pun hanya dengan empat syarat yang sangat ketat yaitu adanya dasar hukum yang jelas, alasan yang sah, tidak bersifat diskriminatif, dan harus proporsional. Sayangnya, dalam kasus pemaksaan jilbab di sekolah negeri, keempat syarat itu gagal dipenuhi.
Pertama, soal dasar hukum. Pemaksaan jilbab tidak memiliki payung hukum formal. Instruksi lisan guru, rapat OSIS, atau surat edaran kepala sekolah tidak bisa menjadi landasan. Justru, Permendikbud No. 45/2014 sudah dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan jilbab adalah pilihan pribadi siswi muslimah, bukan kewajiban seragam sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang memaksakan jilbab sebenarnya melanggar aturan pemerintah sendiri.
Kedua, soal alasan yang sah. Pembatasan hanya bisa dilakukan untuk tujuan tertentu: menjaga ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau melindungi hak orang lain. Tetapi apakah ada bukti bahwa siswi non-muslim yang tidak berjilbab mengganggu ketertiban sekolah? Tidak ada. Apakah ada bukti ia merugikan hak siswa lain? Juga tidak. Justifikasi yang dipakai biasanya sangat subjektif: “agar sopan,” “agar seragam,” “agar sesuai budaya sekolah.” Padahal, moralitas dan kesopanan tidak bisa diukur dari selembar kain.
Ketiga, soal diskriminasi. Pemaksaan jilbab jelas diskriminatif. Pertama, ia menekan siswi non-Muslim untuk mengenakan simbol agama yang bukan keyakinannya. Kedua, ia juga mendiskriminasi siswi Muslimah yang memilih untuk tidak berjilbab, seakan-akan mereka kurang beriman atau kurang bermoral. Diskriminasi ini bukan hanya langsung, tapi juga tidak langsung. Misalnya, ketika sekolah hanya memberi ruang bagi perayaan agama mayoritas, sementara agama minoritas diabaikan. Lama-lama, praktik semacam ini menciptakan rasa tersisih, membuat siswa dari kelompok minoritas merasa bukan bagian dari sekolah.
Keempat, soal proporsionalitas. Bahkan jika sekolah ingin mengatur kesopanan berpakaian, mewajibkan jilbab untuk semua siswi jelas tidak proporsional. Jika tujuannya sekadar menjaga kerapian seragam, maka cukup buat aturan umum: pakaian rapi, menutup bagian tubuh sesuai standar. Tidak perlu memaksa penggunaan atribut agama tertentu. Apalagi, jika pemaksaan itu membuat siswi mengalami tekanan psikologis, merasa dipermalukan, atau bahkan trauma. Itu bukan sekadar tidak proporsional, tapi juga melanggar martabat manusia.
Ketika Jilbab Menjadi Alat Diskriminasi
Sebagai Muslimah yang mengenakan jilbab, saya sadar betul bahwa kain ini adalah simbol spiritual. Bagi saya, jilbab adalah bentuk penghambaan kepada Allah, sebuah pilihan personal yang lahir dari keyakinan. Tetapi makna itu runtuh ketika jilbab dipaksakan. Ia tidak lagi menjadi simbol kesalehan, melainkan alat kontrol sosial. Ia tidak lagi tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan tentang mayoritas yang merasa berhak mengatur tubuh minoritas.
Inilah yang membuat kasus pemaksaan jilbab terasa begitu menyakitkan. Bukan hanya karena ia melanggar aturan hukum, tetapi juga karena ia merusak makna spiritual jilbab itu sendiri. Jilbab yang seharusnya lahir dari keikhlasan berubah menjadi beban psikologis.
Yang lebih mengkhawatirkan, diskriminasi di sekolah berpotensi membentuk cara pandang generasi muda. Anak-anak yang seharusnya belajar menghargai perbedaan justru dipaksa untuk menyeragamkan diri. Padahal, salah satu tujuan utama pendidikan adalah membentuk warga negara yang siap hidup di tengah masyarakat majemuk.
Bayangkan, seorang siswi non-Muslim yang sejak kecil diajari oleh keluarganya untuk setia pada keyakinan agamanya, tiba-tiba dipaksa mengenakan simbol agama lain hanya demi masuk kelas. Apa yang akan ia rasakan? Rasa terasing. Rasa ditolak. Rasa bahwa dirinya tidak diakui. Trauma semacam ini tidak hanya membekas di masa sekolah, tetapi bisa memengaruhi cara pandangnya terhadap masyarakat luas. Ia bisa tumbuh dengan rasa curiga pada kelompok mayoritas, merasa tidak aman di negeri sendiri.
Di sisi lain, siswa mayoritas yang terbiasa melihat diskriminasi tanpa protes bisa tumbuh dengan rasa superioritas palsu. Mereka menganggap wajar jika orang lain harus mengikuti cara hidup mereka. Tanpa disadari, sekolah telah menanamkan benih intoleransi sejak dini.
Belajar Menghargai Keberagaman
Padahal, Indonesia berdiri di atas keberagaman. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa ini menghormati hubungan manusia dengan Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Tetapi ketika di sekolah negeri, ruang yang dibiayai oleh uang rakyat dari berbagai latar belakang, justru terjadi pemaksaan agama, maka itu adalah pengkhianatan terhadap janji kebangsaan.
Sebagai Muslimah, saya percaya bahwa jilbab adalah ibadah yang nilainya tinggi di mata Allah. Tetapi ibadah, apa pun bentuknya, kehilangan makna ketika dipaksakan. Bukankah agama sendiri mengajarkan bahwa “tidak ada paksaan dalam beragama”? Lalu mengapa kita begitu mudah menutup mata terhadap praktik-praktik pemaksaan ini?
Pemaksaan jilbab di sekolah bukan sekadar masalah aturan berpakaian. Ia adalah cermin dari kegagalan kita mengelola perbedaan. Ia menunjukkan betapa rapuhnya komitmen kita terhadap toleransi, bahkan di ruang pendidikan yang seharusnya menjadi laboratorium kebhinekaan.
Saya percaya, setiap kasus yang muncul harus menjadi alarm bagi kita semua. Alarm bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi semua siswa. Alarm bahwa mayoritas harus lebih rendah hati, tidak menjadikan keyakinannya sebagai standar tunggal bagi orang lain.
Bagi saya pribadi, jilbab adalah pilihan iman. Tetapi ketika ia dipaksakan, jilbab kehilangan rohnya. Ia berubah dari simbol ketulusan menjadi simbol pemaksaan. Dan saat itulah, kita tidak lagi bicara tentang kain di kepala, melainkan tentang martabat manusia yang dirampas.
Sekolah seharusnya tidak hanya mendidik anak-anak untuk pintar membaca, menulis, dan berhitung. Lebih dari itu, sekolah harus mendidik mereka untuk menjadi manusia yang menghargai manusia lain. Sebab, tanpa itu, seragam yang rapi pun hanya akan menutupi luka yang lebih dalam, luka intoleransi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.







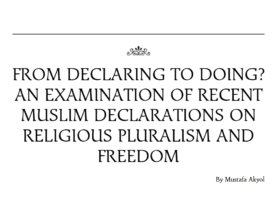

Leave a Reply