Ringkasan:
● Kekristenan di Asmat membawa pesan keselamatan sekaligus berisiko menghapus ingatan spiritual dan kosmologi lokal.
● Kosmologi Asmat memandang roh leluhur, ritus, dan artefak sebagai realitas hidup yang menjaga keseimbangan kosmos.
● Dialog setara antara Injil dan epistemologi Asmat membuka jalan dekolonisasi iman dan pemulihan ingatan spiritual.
Oleh: Yunus Demianus Djabumona | Republikasi dari CRCS UGM
Masuknya kekristenan di Asmat tidak hanya membawa pesan keselamatan rohani, tetapi juga membawa sistem makna baru yang berpotensi memutus ingatan spiritual.
Perjumpaan antara kosmologi Asmat dan kekristenan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan paling nyata ialah penghentian tradisi pengayauan atau berburu kepala manusia. Misionaris Kristen memandang praktik ini sebagai tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai moral Kristen, sehingga secara bertahap dilarang dan dihapuskan.
Penghentian praktik pengayauan memang mengurangi kekerasan fisik dalam kehidupan sosial masyarakat Asmat. Namun, proses ini juga menunjukkan bahwa nilai moral Kristen lebih sering diterapkan secara koersif sebagai pengganti, bukan sebagai hasil dialog dengan kosmologi lokal. Ketika kepercayaan terhadap roh leluhur, ukiran, dan ritus lokal terus-menerus dilabeli sebagai “masa lalu” atau “kesesatan”, kekristenan berisiko menjadi alat penghapusan memori spiritual komunitas (Smith, 2022). Masyarakat Asmat memahami pengayauan sebagai bagian dari upaya memulihkan kehormatan leluhur dan menyeimbangkan relasi antara dunia manusia dan dunia roh (Zulfikar, 2024). Persoalannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya praktik pengayauan dipertahankan atas nama adat, melainkan pada cara praktik tersebut dipahami ulang ketika kerangka moral pendukungnya telah berubah.
Kosmologi Asmat dan Dunia Roh
Bagi masyarakat Asmat, dunia roh bukanlah gagasan abstrak yang hanya hidup dalam mitos atau cerita masa lampau. Dunia roh merupakan realitas yang sungguh hadir dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas tidak ditempatkan dalam ruang yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan menyatu dalam cara orang Asmat memahami tubuh, alam, relasi sosial, seni, serta kematian. Hidup dipandang sebagai satu kesatuan kosmis yang melibatkan manusia, roh leluhur, dan dunia alam. Dalam kerangka ini, kepercayaan bukan sekadar sistem keyakinan, melainkan cara hidup yang memberi makna pada seluruh pengalaman manusia.
Pandangan tentang kehidupan, bagi orang Asmat, dibagi ke dalam tiga ranah utama: ow capinmi, dunia orang hidup; dampu ow capinmi, dunia perantara tempat roh-roh berada setelah kematian; dan safar, dunia terakhir bagi roh leluhur dan roh bayi. Kematian tidak dipahami sebagai pemutusan relasi, melainkan sebagai perubahan cara hadir. Roh orang mati belum sepenuhnya meninggalkan komunitas; roh tersebut masih berelasi aktif dengan mereka yang hidup. Bonifasius Jakfu (2017), seorang penulis sekaligus anggota masyarakat Asmat, menjelaskan bahwa roh-roh di dampu ow capinmi masih dapat membawa penyakit, menimbulkan konflik, atau sebaliknya menjaga keseimbangan hidup apabila relasi dengan mereka dirawat secara tepat melalui ritus dan penghormatan.
Kesadaran akan keberlanjutan relasi antara dunia manusia dan dunia roh mendorong masyarakat Asmat untuk terus menjaga keharmonisan kosmos melalui berbagai ritus. Salah satunya ialah ritus pembuatan ukiran ritual yang disertai dengan upacara penamaan roh. Melalui ritus penamaan tersebut, roh leluhur dibantu untuk melanjutkan perjalanannya menuju safar, sehingga tidak terjebak di dunia perantara (dampu ow capinmi) dan tidak mengganggu kehidupan komunitas yang masih hidup. Dalam kosmologi Asmat, ukiran mengalami transformasi makna: dari benda material menjadi medium kehadiran roh leluhur sekaligus ruang perjumpaan antara dunia orang hidup (ow capinmi) dan dunia roh (dampu ow capinmi dan safar). Dengan demikian, ukiran dalam tradisi Asmat tidak bersifat dekoratif, melainkan memiliki fungsi ontologis dan etis yang mendasar dalam menjaga relasi antardunia serta kesinambungan kehidupan sosial masyarakat (Anggraheni & Prasodjo, 2024).
Cara pandang ini terus bertahan hingga saat ini. Banyak orang Asmat memaknai artefak budaya bukan sekadar sebagai peninggalan sejarah, melainkan sebagai bagian dari kehidupan spiritual yang terus berlangsung. Artefak tidak kehilangan maknanya setelah ritual berakhir; ia tetap menyimpan dimensi relasional dan spiritual. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan modern yang cenderung memisahkan seni, sejarah, dan spiritualitas ke dalam kategori-kategori yang terpisah.
Pemahaman tersebut tampak jelas dalam cara masyarakat Asmat memaknai Museum Budaya dan Kemajuan Asmat. Bagi orang Asmat, ruang pamer artefak di dalam museum merupakan ruang mediasi spiritual. Keberadaan ukiran di museum memungkinkan masyarakat Asmat tetap “berjumpa” dengan roh leluhur mereka. Artefak tidak kehilangan dimensi spiritualnya hanya karena dipindahkan ke ruang institusional. Sebaliknya, museum menjadi ruang baru untuk menjaga kesinambungan ingatan dan spiritualitas leluhur di tengah perubahan zaman (Jakfu, 2017).
Mungkinkah Mendialogkan Pengayauan dan Kekristenan Secara Setara?
Dalam konteks geografis pesisir selatan Papua, praktik budaya dan artefak religius masyarakat Asmat berkembang melalui interaksi dinamis antara kondisi ekologis, struktur sosial, dan perubahan historis. Oleh karena itu, transformasi praktik budaya Asmat lebih tepat dipahami sebagai proses reartikulasi makna dan materialitas religius, bukan sebagai perubahan yang bergerak dalam kerangka penilaian normatif semata.
Pengayauan kini tidak lagi dijalankan secara literal, tetapi direartikulasi ke dalam bentuk simbolik yang mempertahankan fungsi kosmologisnya tanpa mereproduksi kekerasan. Proses ini menunjukkan upaya penyetaraan epistemologi lokal, ketika makna dan logika kosmologis masyarakat adat tidak dihapus, melainkan dinegosiasikan dalam kerangka religius yang baru.
Upaya menempatkan epistemologi lokal secara setara memiliki preseden historis dalam praktik teologi Kristen. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam teologi minjung yang dikembangkan oleh Ahn Byung-Mu (1981). Ahn menunjukkan bahwa pengalaman hidup rakyat tertindas (minjung)—termasuk kemiskinan, kekerasan politik, dan trauma kolonial—berfungsi sebagai sumber pengetahuan teologis yang sah dalam menafsirkan Injil. Kisah penderitaan Yesus dipahami melalui pengalaman penindasan rakyat Korea. Dalam kerangka ini, Injil tidak diterapkan secara sepihak dari luar, melainkan dibaca melalui pengalaman konkret masyarakat. Preseden ini menegaskan bahwa kekristenan dapat berkembang melalui dialog setara dengan epistemologi lokal, sekaligus membuka kemungkinan pendekatan serupa dalam konteks Asmat: kosmologi ow capinmi, dampu ow capinmi, dan safar dapat menjadi titik berangkat refleksi iman, bukan objek yang harus disingkirkan.
Di titik inilah dekolonisasi kekristenan menjadi penting. Dekolonisasi tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap iman Kristen, melainkan sebagai upaya membuka ruang dialog yang setara antara Injil dan kosmologi lokal. Dengan pendekatan ini, kekristenan tidak hadir sebagai kekuatan yang meniadakan spiritualitas Asmat, tetapi sebagai mitra dialog yang menghormati ruang-ruang kehidupan yang telah menopang eksistensi orang Asmat selama berabad-abad. Melalui cara inilah kekristenan dapat hadir sebagai kabar baik: bukan sebagai pengganti tunggal atas dunia makna lokal, melainkan sebagai kehadiran yang rendah hati, kontekstual, dan mampu memulihkan ingatan spiritual masyarakat Asmat.
Editor: Andrianor









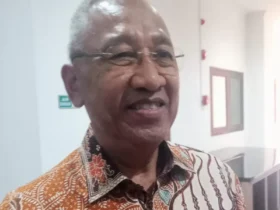
Leave a Reply