Ringkasan:
● Komedi dapat menyinggung perasaan keagamaan, tetapi tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana.
● Pasal 300–301 KUHP 2023 mensyaratkan niat permusuhan, kebencian, atau hasutan, bukan sekadar ketersinggungan.
● Pemidanaan atas dasar ketersinggungan mengancam kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi di Indonesia.
Rilis Media
Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB)
Pertunjukan special standup comedy “Mens Rea” oleh Pandji Pragiwaksono digelar pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, sebagai puncak dari tur sebelas kota yang berhasil menarik sekitar 10.000 penonton. Setelah versi rekamannya dirilis melalui layanan streaming berlangganan Netflix, jangkauan penontonnya meluas secara signifikan.
Memasuki akhir Desember 2025, “Mens Rea” menjadi sorotan publik setelah cuplikan-cuplikan materinya beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan, karena sebagian pihak menilai beberapa bagian dari pertunjukan tersebut “menodai agama”. Sebelum Pandji Pragiwaksono, komika Joshua Suherman dan Ge Pamungkas juga pernah dianggap menodai agama tertentu. Kasusnya mencuat pada Januari 2018. Namun, keduanya tidak diproses hukum secara berlanjut setelah kontroversi tersebut mereda.
Saat ini tercatat setidaknya ada lima laporan polisi dan dua aduan masyarakat terkait “Mens Rea” yang masuk ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya termasuk satu laporan aduan di Polda Banten. Di antara laporan dan aduan masyarakat tersebut, perbuatan Pandji Pragiwaksono dikaitkan dengan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP 2023 (UU No. 1/2023). Sebagai catatan, keberadaan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP mengganti dan mendekriminalisasi pasal 156a KUHP yang dikenal sebagai pasal penodaan agama.
Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP 2023, adalah pasal yang termasuk dalam Bab VII “Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan” (dan telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana). Pasal 300 KUHP 2023 terbaru terdiri dari dua ayat. Dalam pasal ini, tidak ada lagi istilah “penodaan terhadap suatu agama” yang sebelumnya ada dalam Pasal 156a. Tindak pidana pada pasal itu adalah perbuatan permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan, atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan.
Penegakan hukum terkait Pasal 300 dan 301 KUHP baru tentu perlu sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia yang ada pada UUD 1945, UU HAM, maupun UU No.12/2005 (ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, untuk panduan yang lebih operasional, aparat penegak hukum perlu merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, yang dikeluarkan oleh Komnas HAM Indonesia (2020). Di antara instrumen yang disarankan oleh dokumen tersebut adalah Rencana Aksi Rabat yang memberikan panduan terinci tentang bagaimana menafsirkan unsur “hasutan”, “permusuhan”, dan sebagainya.
Jika suatu laporan diproses menggunakan ketentuan KUHP baru, maka aparat penegak hukum wajib membuktikan unsur pokok yang lebih ketat, dengan merujuk pada instrumen-instrumen di atas. Pertama, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memusuhi, membenci, atau menghasut orang lain berdasarkan agama atau kepercayaan. Sebagaimana dalam doktrin hukum pidana, “sengaja dengan maksud” berarti pelaku memiliki pengetahuan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, bukan sekadar menimbulkan persepsi menyinggung.
Unsur “permusuhan dan kebencian” merujuk pada emosi yang intens dan irasional terhadap sasaran tertentu, baik individu maupun kelompok. Adapun “hasutan” dipahami sebagai pernyataan yang ditujukan kepada kelompok nasional, ras, atau agama yang menimbulkan risiko langsung berupa diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok tersebut.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pelapor juga menggunakan Pasal 301 KUHP baru, yang berbicara tentang pelaku tindak pidana Pasal 300 yang “menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi.” Pasal itu memperberat ketentuan Pasal 300, dan karenanya baru dapat diterapkan jika unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 300 telah terpenuhi.
Dengan memperhatikan pertimbangan pemaknaan di atas atas konsep-konsep yang ada dalam KUHP baru, sudah cukup jelas bahwa ujaran Pandji tidak termasuk pernyataan permusuhan, atau hasutan untuk melakukan kekerasan, atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok agama tertentu. Ujaran-ujaran Pandji amat mungkin menyinggung perasaan orang-orang tertentu (bukan hanya kelompok agama, tapi juga Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, anggota parlemen, militer, dan polisi yang menjadi sasaran komedinya). Namun perasaan ketersinggungan bukan merupakan unsur pidana. Orang atau kelompok tertentu tentu berhak tidak suka pada Pandji, namun tidak ada alasan untuk memidanakannya. Ungkapan ketidaksetujuan, ketidaksukaan atau ketersinggungan terhadap Pandji dapat diungkapkan melalui cara-cara berbeda, memanfaatkan ruang untuk kebebasan berekspresi.
Jika tidak, maka kritik terhadap pemerintah pun dapat dipidanakan atas alasan ketersinggungan, dan itu akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan warga untuk berpartisipasi, menyatakan pikirannya, termasuk untuk mengkritik pemerintah atau fenomena sosial yang (dianggap) buruk. Aparat penegak hukum sebaiknya tidak melanjutkan pemrosesan laporan tersebut, karena jelas penerapan pasal-pasal dalam KUHP baru tersebut tidak tepat dalam kasus komedi Pandji.
Masih munculnya laporan masyarakat yang mengaitkan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP sebagai tindak pidana “penistaan” atau “penodaan agama” menunjukkan bahwa informasi dan sosialisasi mengenai KUHP 2023 belum sepenuhnya dipahami, khususnya terkait pasal-pasal yang menyangkut agama dan kepercayaan. Pergeseran dari konsep “penodaan agama” menjadi permusuhan, kebencian, dan hasutan atas dasar agama atau kepercayaan merupakan kemajuan, karena sementara istilah dalam KUHP lama itu amat kabur, istilah-istilah yang digunakan KUHP baru jauh lebih jelas, dan memiliki sumber rujukan penafsiran yang jelas, termasuk dalam norma HAM di Indonesia.
ISFoRB, sebagai lembaga yang berfokus pada kajian akademik mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan berkomitmen mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai martabat manusia serta menjamin hak-hak KBB, memandang bahwa kasus yang melibatkan Pandji Pragiwaksono perlu ditempatkan dalam semangat pembaruan yang melatarbelakangi diundangkannya KUHP 2023. Argumen yang dipaparkan dalam rilis ini berdasarkan pada kajian lebih komprehensif yang telah diterbitkan dalam buku Pasal 300-305 KUHP 2023 terkait Agama Atau Kepercayaan: Prinsip-Prinsip Penafsiran untuk Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2025), yang di antaranya memiliki bab berjudul “Penafsiran Atas Bab VII KUHP 2023: Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan.”
KUHP baru membawa visi yang menekankan demokratisasi, adaptasi, dan harmonisasi, dengan tujuan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, setiap proses penegakan hukum seharusnya mengedepankan prinsip bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan harus dijaga bersama-sama, agar ruang publik tetap inklusif, adil, dan demokratis. Semangat KUHP baru, khususnya dalam bab-bab mengenai agama dan kepercayaan, bukanlah menghukum, tapi melindungi warga negara (dari permusuhan dan hasutan untuk permusuhan, kekerasan atau diskriminasi).
Editor: Andrianor










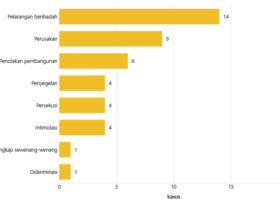
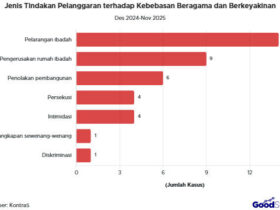
Leave a Reply