Ringkasan:
● Demokrasi Indonesia kian simbolik dan menjauh dari pemenuhan hak kelompok rentan.
● Ruang digital memperdalam polarisasi dan memperkuat disinformasi yang merugikan kelompok rentan.
● Teknologi politik dan regulasi baru mengancam kebebasan warga, sehingga literasi kritis menjadi mendesak.
Oleh: Ucu Cintarsih | Republikasi dari Jakatarub
Demokrasi yang Semakin Simbolik
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya menjadi fondasi yang menjamin martabat dan kesetaraan setiap individu. Namun, dalam kondisi Indonesia hari ini, kedua prinsip itu terasa semakin jauh.
Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana demokrasi berubah menjadi ritual yang serba simbolik—pencoblosan, kampanye, dan baliho—tanpa benar-benar menjawab kebutuhan serta pemenuhan hak warga negara, terutama kelompok rentan: penyandang disabilitas, perempuan, pemeluk agama atau keyakinan minoritas, ragam gender dan seksualitas, orang muda, serta masyarakat adat. Suara mereka terdengar diakomodasi dan difasilitasi saat kampanye, tetapi kembali terpinggirkan setelah pesta pemilu selesai.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan menjelang berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada Januari 2026. Sejumlah pasal berpotensi menimbulkan rasa takut untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi, menciptakan “tabu baru” dalam kehidupan sosial.
Dalam kultur Indonesia, sikap menahan diri sering dianggap bagian dari moralitas dan etika kesopanan. Namun, ketika kesungkanan muncul karena ketakutan akan ancaman hukum, ruang dialog yang seharusnya menjadi inti demokrasi patut dipertanyakan: sejauh mana negara tetap berkomitmen pada prinsip demokrasi?
Relasi antara negara dan warganya tampak semakin menyerupai pola lama yang sudah familiar dalam sejarah sosial Indonesia: hubungan patron–klien. Negara diposisikan sebagai pihak yang mengatur dan memutuskan, sementara warga ditempatkan sebagai penerima keputusan yang harus patuh.
Kebijakan cenderung dibuat untuk menertibkan ketimbang melindungi. Akibatnya, kebutuhan warga, terutama mereka yang rentan, tidak menjadi pusat perhatian. Jarak antara negara dan masyarakat makin senjang. Kebebasan kian menyempit.
Ruang Digital dan Polarisasi
Pergeseran ini semakin diperkuat oleh ruang digital. Alih-alih menjadi arena demokrasi baru, media sosial justru mempertebal batas antarkelompok. Identitas agama, etnis, dan gender yang seharusnya cair, dipersempit menjadi penanda “kami” dan “mereka”. Algoritma platform media sosial membentuk gelembung interaksi yang membuat orang hanya bertemu dengan mereka yang sepemikiran. Pandangan berbeda dianggap ancaman, bukan bagian alami dari keberagaman.
Situasi ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai krisis epistemik era post-truth. Fakta menjadi kurang penting, sementara emosi mengambil alih cara orang memahami realitas. Disinformasi dan ujaran kebencian semakin menyebar dengan cepat, memperkuat prasangka, dan menjadikan kelompok rentan sebagai sasaran empuk. Pada akhirnya, ruang digital menciptakan mitos-mitos modern tentang siapa yang dianggap berbahaya dan siapa yang boleh diterima. Hal ini berpengaruh besar pada kehidupan sosial, terutama di daerah yang memiliki sejarah panjang interaksi lintas budaya seperti Jawa Barat: ketidakpercayaan antarkelompok meningkat, sementara ruang dialog kian sempit.
Selain itu, manusia kini hadir dalam bentuk lain melalui data pribadi. Informasi seperti NIK, biometrik, hingga jejak interaksi digital merupakan bagian dari identitas. Karena itu, kebocoran data atau pencatutan identitas dalam kontestasi politik tidak bisa dianggap persoalan sepele. Ketika data diperlakukan sebagai komoditas politik, manusia direduksi menjadi angka dan aset yang dapat diperjualbelikan.
Tantangan Menuju Pemilu 2029
Melihat ke Pemilu 2029 nanti, tanda-tanda dehumanisasi kian kentara seiring teknologi analitika dan kecerdasan buatan yang memungkinkan micro-targeting untuk memanipulasi pilihan pemilih. Batas antara preferensi politik dan manipulasi semakin nisbi. Literasi kritis—kemampuan untuk mempertanyakan siapa pembuat narasi dan apa motifnya—menjadi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan dan memperjuangkan ruang publik yang menjunjung HAM.
Di tengah tekanan terhadap demokrasi, baik dari regulasi yang membatasi ruang sipil maupun teknologi yang membuka peluang manipulasi, ruang perjumpaan sosial perlu terus diupayakan dan dimasifkan. Komunitas lintas iman dan jaringan masyarakat sipil dapat mencegah masyarakat terbelah oleh ketakutan dan prasangka, menjadi tempat cerita dibagikan, pengalaman didengar, serta perbedaan dirayakan sebagai bagian dari kehidupan bersama yang inklusif.
Menempatkan Martabat Manusia di Pusat Demokrasi
Jika demokrasi ingin tetap memanusiakan, negara perlu melihat warga negara bukan sebagai kawula. Suara publik bukan ancaman, dan keberagaman bukan sesuatu yang harus ditertibkan. Demokrasi hanya dapat bertahan jika martabat manusia ditempatkan di pusatnya, melampaui sekadar prosedur.
Saat itu terwujud, demokrasi tidak lagi sekadar pesta lima tahunan yang sarat simbolik. Ia menjadi ruang bersama yang menjamin setiap orang memiliki tempat yang setara dan bermartabat.
Bahan Bacaan:
Timcke, Scott. AI, Inequality, and Democratic Backsliding. TechPolicy.Press, 14 April 2025.
Editor: Andrianor









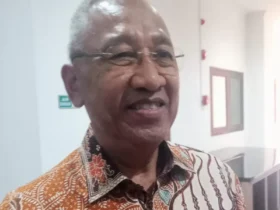
Leave a Reply