Ringkasan:
● Demokrasi dan kebebasan beragama terancam oleh polarisasi, represi negara, dan bias media.
● Krisis iklim dan isu minoritas membutuhkan pemberitaan yang adil, empatik, dan tidak maskulin-sentris.
● Jurnalisme etis menuntut verifikasi, independensi, dan keberpihakan pada kelompok rentan demi ruang publik inklusif.
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi
Sabtu lalu, saya menghadiri sebuah diskusi kecil yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Jurnalis Independen Banten. Mereka tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Biro Banten, bekerja sama dengan EcoBhinneka Muhammadiyah dan GreenFaith Indonesia. Tema yang diangkat sangat menarik, yaitu “Peran Media dalam Membangun Kehidupan yang Inklusif di Indonesia.”
Beberapa pemantik diskusi diundang, antara lain Andreas Harsono (pegiat HAM dan media), Sukowati Utami (GreenFaith Indonesia), Tantowi Anwari (SEJUK), dan Salsabila Putri Pertiwi (Konde). Diskusi dimoderatori oleh Hairul Alwan (Suara.com). Acara yang diselenggarakan di Omah Andreas Harsono ini dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis dari berbagai media, jurnalis kampus, pegiat EcoBhinneka Muhammadiyah, serta perwakilan Polsek dan KUA Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
Towik dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) membuka diskusi dengan memaparkan kondisi demokrasi Indonesia yang, menurutnya, berada dalam ancaman serius. Pendekatan keamanan kerap digunakan untuk merespons kritik terhadap kebijakan negara, terutama terkait kelompok minoritas agama serta isu lingkungan dan demokrasi. Para pengkritik dibungkam, bahkan tidak jarang berakhir dengan penahanan. Menurut Towik, Indonesia kini masuk dalam kategori electoral autocracy, bukan lagi negara demokratis. Salah satu indikatornya adalah adanya 42 kasus gangguan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) pada tahun 2025, baik terhadap individu maupun komunitas.
Sukowati Utami dari GreenFaith Indonesia menyoroti ruang publik yang kini semakin dipenuhi polarisasi keagamaan, sementara krisis iklim terus mengancam dan memperlebar ketimpangan. Dalam kondisi seperti itu, media menjadi arena pertarungan narasi antara pihak pro dan kontra. Jurnalis, menurutnya, seharusnya hadir sebagai jembatan, bukan justru menjadi bahan bakar konflik. Ia menilai pemberitaan media kerap tidak seimbang: krisis lingkungan yang merusak “rumah bersama” jarang mendapat perhatian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim sangat relevan dengan isu kebebasan beragama karena dampaknya mengancam semua orang tanpa memandang agama. Semua ajaran agama, tegasnya, memuat mandat moral untuk menjaga bumi.
Salsabila Putri dari Konde menyampaikan keprihatinannya terhadap media yang kurang peka pada isu keadilan bagi perempuan serta kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Media sering kali terjebak pada perspektif maskulinitas sempit, misalnya memberikan ruang lebih besar kepada laki-laki atau menampilkan laki-laki sebagai sosok dominan. Narasi seperti ini membentuk standar maskulinitas yang tidak realistis dan dapat menormalkan dominasi. Sebaliknya, ketika media menampilkan bentuk maskulinitas yang lebih sehat, dampaknya positif karena membantu membangun identitas yang lebih seimbang.
Salsa memberi contoh betapa buruknya media memberitakan seorang penata rias atau make up artist (MUA) asal Lombok dengan nama tenar Dea Lipa atau Deni, yang belakangan viral dengan julukan “Sister Hong Lombok.” Narasi yang beredar tentang dirinya, diakuinya, sungguh tidak memiliki dasar dan fakta yang benar. Ia merasa dituduh atas hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Misalnya isu yang menuduh bahwa ia merupakan penista agama, di mana ia dituding berada di saf perempuan dan mengenakan mukena saat beribadah di masjid. Ia juga dituding sebagai kaum sodom atau “Sister Hong Lombok” yang kerap melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Bahkan yang paling sadis, ia dianggap mengidap HIV/AIDS. Akibat penyebaran fitnah yang begitu liar itu, Deni mengaku mengalami kerugian karena banyak klien yang membatalkan job. Ia juga mengaku tertekan setelah dirinya viral, bahkan sempat dua kali mencoba mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi situasi tersebut.
Salsa kemudian mempertanyakan apakah dalam pemberitaan terkait pelanggaran kebebasan beragama, khususnya yang menimpa kelompok minoritas, jurnalis harus benar-benar menggali sudut pandang perempuan. Tidak jarang media justru meminggirkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam isu-isu tersebut dianggap tabu atau aib. Dalam konteks agama dan kepercayaan, tokoh laki-laki lebih sering disorot. Menurut Salsabila, media harus berani mendobrak dominasi tersebut dan berpihak kepada kelompok minoritas, termasuk suara perempuan, misalnya dalam kasus kekerasan akibat perbedaan agama.
Sebagai pemantik terakhir, Andreas Harsono mengacu pada bukunya yang berjudul “Agama” Saya Adalah Jurnalisme. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan pandangannya tentang jurnalisme yang berkomitmen pada etika: mencari kebenaran, memantau kekuasaan, dan membela mereka yang mengalami ketidakadilan. Seorang jurnalis, tegasnya, harus independen, memeriksa fakta, memverifikasi informasi, mendengarkan semua pihak, berempati tanpa kehilangan jarak kritis, serta bertahan dari tekanan kekuasaan maupun publik.
Jurnalis boleh simpatik, tetapi tetap harus menjaga independensi. Andreas juga menyoroti bagaimana narasi nasionalisme, politik identitas, dan regulasi agama dapat menekan kebebasan berkeyakinan serta mempersempit ruang toleransi. Ideologi atau agama apa pun bisa dijadikan pembenaran untuk kekerasan, namun ketika agama digunakan untuk kekerasan, kekerasan itu tetap salah. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Platform dari verifikasi ada tiga: transparansi, sadar akan urutan peristiwa, serta berpikir terbuka. Bila disiplin pada platform verifikasi, seorang jurnalis seyogianya punya modal mengatasi bias diri.
Salah satu peserta diskusi bertanya mengapa perempuan sering dijadikan objek yang tidak pantas dan mengapa perempuan maupun kelompok minoritas kerap dijadikan alat untuk meningkatkan rating. Bagaimana dengan keadilan bagi mereka?
Menanggapi hal itu, Andreas mengajak peserta membaca buku karya Arief Budiman berjudul Pembagian Kerja Secara Seksual (1985). Buku tersebut menjelaskan bagaimana perempuan dibentuk dan diasuh untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak alamiah (nurture). Perempuan secara biologis melahirkan dan menyusui (nature), tetapi sejak kecil diarahkan untuk bermain boneka, memasak, dan aktivitas domestik lainnya. Mereka jarang didorong untuk berinteraksi dengan teknologi, militer, atau olahraga. Ketika dewasa, perempuan tidak didorong untuk masuk ke sektor publik seperti teknologi atau militer. Mereka dibina agar tetap berada di sektor domestik: mengasuh anak, memasak, dan mengurus rumah.
Sebagai jurnalis, meliput setiap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dilakukan dengan keberanian, fakta, empati, dan independensi demi keadilan bagi semua. Hanya dengan jurnalisme yang adil dan suara yang beragam, kita bisa membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan.
Editor: Andrianor










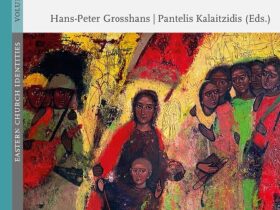

Leave a Reply