Tulisan Keenam (Catatan Akhir Tahun KBB 2025)
Oleh: Samsul Maarif
Pada 10 Desember 2025, ratusan warga Sukatani Cianjur, Jawa Barat melakukan demonstrasi di kantor Bupati Cianjur.[1] Aksi tersebut didominasi oleh perempuan yang memprotes pematokan titik proyek geotermal di Sukatani tanpa penjelasan kepada warga pada bulan sebelumnya, sekaligus menuntut Bupati Cianjur menepati janjinya untuk menolak proyek geotermal di Gunung Gede Pangrango. Demonstrasi tersebut adalah rangkaian dari gerakan komunitas menolak geotermal, membela ruang hidup. Mereka, di antaranya menarasikan bahwa gerakan penolakan tersebut merupakan perintah agama, kewajiban adat, atau ajaran leluhur.
Tulisan ini memberi perhatian khusus pada gerakan komunitas menolak geotermal seperti di Sukatani yang banyak menggunakan narasi dan praktik keagamaan, kepercayaan, dan adat. Merujuk pada gerakan komunitas tersebut, tulisan ini menunjukkan pentingnya melihat hubungan erat antara isu ke(tidak)adilan lingkungan dan isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Tulisan ini menggunakan beberapa data dari penelitian ICRS terkait polarisasi berbasis isu lingkungan 2024–2025, yang melibatkan tim Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta dan 14 peneliti komunitas yang terlibat dalam gerakan komunitas menolak geotermal: Mandailing Sumatra Utara, Padarincang Banten, Gunung Gede Pangrango Jawa Barat, Ciremai Jawa Barat, Gunung Tampomas Jawa Barat, Dieng Jawa Tengah, Songgoriti Jawa Timur, Gunung Wilis Jawa Timur, Sinjai Sulsel, Tanah Toraja Sulsel, Jailolo Maluku, Wae Sano NTT, Pocoleok NTT, dan Mataloko NTT. Informasi lebih lengkap terkait gerakan komunitas tersebut dapat dibaca di buku “Energi Hijau vs Pelestarian Ruang Hidup” (2025).[2]
Proyek Geotermal dan (potensi) pelanggaran hak warga
Tuntutan global untuk percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan semakin menguat sebagai respons terhadap krisis iklim yang makin mencekam. Dalam konteks itu, Indonesia ikut mendorong pengembangan panas bumi (geotermal) yang diklaim sebagai energi bersih dan ramah lingkungan. Geotermal telah dijadikan sebagai pilar utama transisi energi. Pengembangannya juga untuk mendorong pencapaian target emisi nol karbon 2060 dan demi terwujudnya kedaulatan energi nasional.[3]
Namun di balik narasi transisi energi tersebut, jargon energi bersih masih terus memantik kontroversi. Selain meningkatkan potensi energi untuk pembangkit listrik geotermal, pengembangannya sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, seperti gempa bumi, pencemaran air tanah melalui emisi gas, termasuk yang beracun, dan kerusakan ekosistem yang signifikan. Perencanaan dan pengelolaan transisi energi adalah proses politik yang melibatkan beragam aktor di berbagai level (nasional, daerah) yang berebut klaim ruang, peran dan kepentingan. Dalam praktik transisi energi, penyelerasan aspek teknis, keuangan, politik, dan sosial-budaya selalu memunculkan kontestasi dan bahkan polarisasi.[4]
Yang krusial dicatat adalah bahwa dalam pengembangan proyek geotermal, faktor sosial-budaya atau pelibatan warga seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian.[5] Fakta tersebut bertentangan dengan pernyataan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), “Kesuksesan pembangunan panas bumi tak hanya ditentukan oleh angka-angka, tetapi kunci utamanya adalah penerimaan sosial dari masyarakat lokal.”[6] Dominasi ahli dan tim survei dalam pengambilan kebijakan untuk penentuan WKP, pematokan hingga pengeboran yang tidak melibatkan warga secara bermakna, atau tidak serius mempertimbangkan faktor sosial-budaya telah memicu gerakan penolakan dari komunitas akar rumput, sebagaimana ramai diberitakan di berbagai media nasional dan media sosial.[7]
Berdasarkan penelitian kami, kami mencatat empat indikator pengabaian aspek sosial-budaya dalam pengembangan proyek geotermal. Pertama, komunikasi geotermal didominasi oleh elite: pengusaha, ahli dan otoritas politik, yang cenderung berjalan satu arah. Konsolidasi lintas sektor diperkuat, tetapi minim pelibatan komponen lain, terutama yang menentang seperti warga komunitas. Kedua, beberapa forum publik disediakan, termasuk yang melibatkan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal, namun umumnya dalam agenda sosialisasi. Keputusan sudah dibuat, dan forum lebih dimaksudkan untuk menyampaikan agenda proyek. Informasi geotermal yang disampaikan fokus pada potensi keuntungannya, dan potensi dampak negatifnya cenderung dihindari. Forum yang disediakan cenderung terbatas, atau tepatnya tidak mengakomodasi individu atau kelompok warga yang menentang. Ketiga, pihak pengembang geotermal memilih LSM lingkungan yang pro geotermal sebagai corong kampanye proyek geotermal. Keempat, intimidasi, represi dan bahkan kriminalisasi cukup umum dilakukan kepada individu dan kelompok warga lokal yang menentang.[8]
Dampak dari pengabaian aspek sosial-budaya di atas adalah rangkaian pelanggaran hak warga yang telah atau potensial dialami oleh warga, seperti yang terlibat dalam gerakan komunitas:
a. Perampasan atau alih kuasa lahan/wilayah. Tanah adat yang tidak/belum mendapatkan pengakuan dari Pemda atau pemerintah pusat paling rentan dirampas untuk WKP. Tanah adat bagi masyarakat adat adalah ruang hidup sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi. Keberlanjutan hidup mereka bergantung pada tanah/wilayah adatnya, dan karena itu perampasannya berarti perampasan ruang dan keberlanjutan hidupnya.
b. Hilangnya mata pencaharian. Tanah/lahan milik warga “dirampas” dengan cara dibeli atau ganti rugi, yang pembelian atau penggantinya berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian warga.
c. Kerusakan ekosistem lingkungan seperti pencemaran air dan udara, dan gangguan kesehatan. Pengalaman warga yang wilayahnya merupakan tempat operasi proyek geotermal, seperti Dieng Jawa Tengah dan Mandailing Sumatera Utara membuktikan dampak kerusakan ekosistem lingkungan tersebut. Warga yang kerentanannya berlapis-lapis bukan hanya tidak memiliki akses pada keadilan lingkungan, tetapi juga sulit mengakses penanganan kesehatan. Pengalaman warga Dieng dan Mandailing adalah kecemasan serius bagi komunitas yang wilayahnya telah ditentukan sebagai WKP. Hak hidup sehat dan aman (terancam) dilanggar.
d. Konflik sosial. Pengabaian terhadap aspek sosial-budaya dalam proyek geotermal menciptakan perpecahan antar warga. Bahkan, polarisasi warga, pro vs kontra, tampak merupakan pola umum hasil rekayasa, bagian dari operasi proyek geotermal untuk meminimalisir ongkos operasi. Yang dipersuasi untuk pro geotermal tidak perlu dalam jumlah banyak, tetapi memiliki kuasa seperti tokoh politik, tokoh masyarakat, dan diberikan insentif. Selainnya dibiarkan kontra, tetapi diintimidasi, termasuk oleh sesama warga yang pro. Konflik sosial menjangkau tingkat keluarga, antar saudara, melampaui konflik antar kelompok, atau antar kampung. Ikatan sosial yang diwarisi berdasarkan tradisi, budaya dan agama, dapat dan telah putus satu demi satu.
e. Perentanan kelompok rentan. Umum dalam industri ekstraktif, termasuk proyek geotermal bahwa mereka yang sudah rentan akan makin rentan, atau kerentanannya makin berlapis. Di situasi konflik sosial seperti poin sebelumnya, perempuan yang sudah rentan makin tertutup ruangnya, anak-anak makin terabaikan, disabilitas makin tak kelihatan. Kelompok minoritas makin terintimidasi karena salah memilih afiliasi akan berdampak pada persekusi dari berbagai arah. Masyarakat adat yang masih terus berjuang menuntut pengakuan justru ruang hidupnya dirampas. Komunitas lokal memikul hampir seluruh beban kerentanan. Mereka miskin, minim kuasa budaya dan kuasa agama, apalagi kuasa politik.
f. Pelanggaran hak budaya, agama/kepercayaan, dan adat. Keyakinan komunitas, yang merupakan basis perilaku keseharian, minim penghormatan, tanpa perlindungan, apalagi pemenuhan hak dalam bentuk fasilitasi ekspresi. Keyakinan bahwa “manusia bagian dari alam, merawat alam adalah warisan leluhur, merusak alam adalah larangan agama” tak digubris. Situs-situs suci, ragam simbol budaya dan keagamaan, dan ritual sebagai ekspresi keyakinan, instrumen pelastarian tradisi, atau syiar agama, justru cenderung ditanggapi sebagai anti-pembangunan, bahkan rentan disesatkan.
Semua bentuk pelanggaran hak warga di atas saling berkelindan. Dengan kata lain, industri ekstraktif seperti proyek geotermal telah dan selalu berpotensi melanggar berbagai dimensi hak: hak sipil dan politik (Sipol), dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).
Gerakan Komunitas: Menyikapi pelanggaran hak
Pada awal 2024, beberapa warga dari belasan komunitas lintas daerah, yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi (WKP), melaksanakan konsolidasi. Mereka berbagi pengalaman dan kepedulian, dan kemudian bersepakat menyusun agenda gerakan komunitas menolak poryek geotermal, yang menurut mereka, mengancam keberlanjutan ruang hidup mereka. Mereka selanjutnya menyusun agenda konsolidasi gerakan komunitas dengan mengutamakan konsolidasi komunitas dan pengembangan jaringan lintas komunitas.
1. Komitmen Kewargaan
Gerakan komunitas didasarkan pada kesadaran kewargaan. Berdasarkan pada apa yang mereka saksikan dan alami, proyek geotermal adalah perampasan ruang hidup. Sebagai respons, warga mengembangkan komitmen kewargaan, mengonsolidasi kesadaran kolektif terkait hak kewargaan, pro-aktif menuntut hak partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan, dan menuntut perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Warga Ciremai menegaskan bahwa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Merawat alam adalah kebenaran, mempertahankan ruang hidup adalah kebenaran, dan bersuara adalah hak warga negara.[9] Mereka menyuarakan bahwa mereka adalah pemangku kepentingan utama karena selain sebagai penghuni area WKP, mereka yang paling potensial terdampak dari kebijakan proyek geotermal. Bagi mereka, peminggiran mereka sebagai pemangku kepentingan utama telah dan akan berdampak pada kehidupan kewargaan mereka, atau pada pelanggaran hak lingkungan (ruang hidup), kesehatan, beragama, dan lainnya.
2. Pemahaman Lingkungan
Bagi gerakan komunitas, lingkungan atau alam adalah tanah dan semua yang ada di bawah dan di atasnya. Ia adalah ekosistem dan ruang hidup bagi semua yang hidup, dan manusia hanya salah satu di antaranya. Ekosistem dan ruang hidup, bagi mereka, mewadahi kehidupan masa lalu berlanjut hingga hari ini. Kehidupan hari ini adalah warisan pendahulu atau leluhur. Leluhur mewariskan ruang hidup, berikut pengetahuan dan ajarannya (kearifan lokal, agama, adat), yaitu merawat alam untuk kesejahteraan hidup (semua makhluk) dan untuk generasi berikutnya.
Warga Toraja Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa Toraja merupakan romansa alam dan manusia, yang tidak terpisahkan. Berdasarkan ajaran dan praktik kepercayaan Aluk Todolo, hutan dan tanah adat adalah kehidupan dan ruang hidup yang mencakup sumber mata pencaharian dan spiritualitas. Jika dirusak, hidup pun akan hancur. Hutan dan gunung harus dijaga, karena merekalah yang menjaga air melalui celah-celah gunung batu, mengalirkannya ke sawah hingga ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari.[10] Warga komunitas adat Pocoleok menegaskan tanah adat adalah suci dan sakral. Ia tidak terpisah atau berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu kesatuan relasi dengan komunitas dan tradisi adatnya.[11] Pemahaman serupa ditegaskan oleh warga gerakan komunitas dari Kota Batu Malang. Menurut mereka, lingkungan adalah kemanusiaan itu sendiri. Mereka menghidupkan kearifan lokal dan menjalankan agama (Islam) dengan men-sakral-kan (mata) air melalui ritual-ritual tahunan dan doa-doa.[12]
3. Ajaran agama, kepercayaan dan adat
a. Keyakinan: perintah merawat dan larangan merusak alam.
Pemahaman terkait lingkungan seperti di atas, yang menyebar di banyak komunitas lokal, khususnya yang terlibat dalam gerakan komunitas, kental dengan narasi dan praktik keagamaan, kepercayaan dan adat. Beberapa sarjana menteorikan realitas tersebut sebagai “ekoteologi”, yang seharusnya dijadikan baseline oleh Kemenag RI untuk agenda ekoteologinya saat ini, jika pro-warga.
Warga dari Gunung Gede Pangrango misalnya menjelaskan bahwa laku pertanian, wujud perawatan alam, adalah berdasarkan kearifan lokal, warisan laku leluhur. Bertani tentu tidak sekedar menanam, memanen dan memakan hasil panen, tetapi juga merawat kelestarian kesuburan tanah dan ekosistemnya. Kesuburan tanah bergantung pada air, yang karena itu mata airnya harus dirawat, bergantung pada pohon yang menyimpan air, dan karena itu pohon harus dirawat. Ia juga selalu menjelaskan bahwa Al-Qur’an, kita suci agama Islam yang diyakini dan dijalankannya, memuat peringatan tentang ancaman pengrusakan alam oleh umat manusia, perintah merawat dan larangan merusak alam. Untuk menegaskan pembelaannya terhadap hak gunung, ia secara khusus sering mengekspresikan pemahamannya tentang gunung sebagai makhluk spesial karena disebut dan dijelaskan berkali-kali dalam Al-Qur’an. Merujuk pada pemahaman dan keyakinannya, ia menegaskan bahwa proyek geotermal sebagaimana dipraktikkan bertentangan dengan kearifan lokal warisan leluhur dan tegas bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an.[13]
Kelompok Gereja di Pocoleok ikut mengampanyekan penolakan terhadap proyek geotermal khususnya kepada jamaatnya dengan menggunakan narasi dari ajaran gereja, yaitu bahwa manusia berkewajiban untuk selalu menjaga alam ciptaan Tuhan, tidak boleh merusak bumi, seperti pengeboran ke dalam perut bumi. Mereka merujuk pada ensiklik laudatosi oleh Paus Fransiskus yang isinya mengajak umat manusia untuk mencintai dan merawat alam ciptaan Tuhan seperti kita merawat diri kita sendiri.[14] Melanjutkan narasi keyakinan gereja, komunitas adat Pocoleok menunjukkan bahwa dampak buruk yang kongkrit dari proyek geotermal adalah pemaksaan pandangan tentang tanah, yang kepemilikannya berbasis individu atau milik pribadi melalui sertifikat. Tanah diperjual-belikan. Pandangan (oleh negara, ATR/BPN) tersebut bertentangan dengan konsepsi atau keyakinan komunitas adat. Tanah adat menurut keyakinan mereka, bukan milik manusia, tetapi dialah yang memiliki manusia, dan karena itu tugas manusia adalah menjaga dan merawatnya.[15]
Warga Jailolo, Maluku Utara yang beragama Islam juga menceritakan bahwa selain perintah merawat dan larangan merusak alam yang tegas dalam Al-Qur’an, mereka mendapatkan pesan dari Habib yang telah meninggal kepada anaknya melalui mimpi. Isi pesannya adalah agar generasi Desa Pabos menjaga kampung karena akan datang masalah besar, yaitu datangnya proyek geotermal.[16]
b. Ekspresi keyakinan: situs suci, ritual, dan gerakan.
Keyakinan keagamaan, kepercayaan, dan adat untuk perawatan alam diekspresikan bukan hanya oleh yang terlibat dalam gerakan komunitas, tetapi banyak komunitas lokal lainnya. Ekspresi keyakinan tersebut mencakup ragam bentuk seperti designasi situs-situs suci, ritual, hingga gerakan.
Komunitas adat Pocoleok memiliki sistem perawatan alam melalui penghormatan dan perawatan situs-situs suci seperti hutan keramat (pong) dan mata air (mata wae). Situs-situs suci tersebut, menurut ajaran adat yang banyak dinarasikan melalui mitos dan cerita rakyat, adalah ruang roh leluhur, makhluk hidup lain, termasuk binatang-binatang sakral. Situs-situs suci tersebut hidup atau dihidupkan melalui beragam ritual. Komunitas adat Pocoleok misalnya melaksanakan ritual penghormatan dan pelestarian lingkungan seperti penti, teing hang, barong wae, dan lain-lain di situs-situs sucinya.[17]
Ritual-ritual perawatan alam adalah warisan leluhur, tetapi selain itu, mereka juga mengkreasi ritual-ritual baru. Warga di kawasan Songgoriti misalnya melaksanakan “Banyu Panguripan” di Candi Songgoriti pada malam 1 Suro, ritual baru yang tujuan utamanya adalah untuk merawat dan menjaga sumber mata air dari berbagai ancaman pembangunan ekstraktif seperti proyek geotermal.[18] Warga khususnya pemuda Dieng menginisiasi Sesirat Fest untuk menghidupkan warisan tokoh komunitas (Kyai Sadin) dalam menyelamatkan kelestarian mata air (elemen utama kesejahteraan masyarakat) Sethulu, Sidandang, dan Siranti (tiga area segi tiga mata air) di Desa Bakal, Dieng. Sesirat Fest adalah acara tradisi dan ruwatan mata air tahunan yang digelar sejak 2019. Ruwatan ini diinisiasi sebagai perlawanan warga terhadap ekspansi geotermal Dieng yang diyakini akan merusak bentang air wilayah hulu mata air Sethulu dan Sidandang. Sesirat Fest adalah juga untuk menguatkan komitmen warga pada pentingnya merawat kehidupan dan mengakar-kuatkan gerakan komunitas.[19]
Komunitas adat Mataloko melakukan ritual adat “tolak bala”, khusus untuk menolak geotermal. Bagi mereka, proyek geotermal adalah bencana dan bala yang harus disingkirkan sejauh mungkin. Ritual tolak bala selalu dilaksanakan di masing-masing komunitas, khususnya sebelum aksi “jaga kampung” menghadang pengembang proyek geotermal.[20] Komunitas adat Mataloko juga melaksanakan beberapa ritual sebagai bentuk komunikasi mereka dengan leluhur yang telah mewariskan tanah kepada generasi sekarang. Ritual-ritual tersebut adalah untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa tanah adalah ruang hidup leluhur, ruang hidup mereka sekarang dan setelah mati. Jika ia dijual dan kemudian dibor (untuk proyek geotermal), ruang hidup leluhur, ruang hidup warga sekarang dan setelah mati akan hancur atau hilang.[21]
Situs-situs suci yang dihidupkan melalui ritual, dan ritual yang juga difungsikan sebagai gerakan menolak geotermal adalah rangkaian ekspresi (atau praktik) keyakinan keagamaan, kepercayaan, dan adat.
Konsep dan Agenda Advokasi KBB
Narasi dan praktik keagamaan dalam gerakan komunitas menolak proyek geotermal memaparkan ruang renungan terkait pentingnya melihat keterkaitan antara ke(tidak)adilan lingkungan dan hak KBB. Transisi energi adalah tuntutan global yang patut didorong, tetapi hak KBB dan hak kewargaan lainnya wajib dihormati dan dilindungi. Keduanya wajib dipenuhi. Untuk prinsip tersebut, advokasi KBB perlu merumuskan konsep dan agenda yang menegaskan keterkaitannya, dan pemenuhan keduanya.
1. Agama: lived religion dan religous creativity
Gerakan komunitas menolak geotermal adalah realitas “agama yang dijalani” (lived religion), yaitu realitas keagamaan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan, budaya, lingkungan hingga ekonomi dengan gerakan dan praktik keseharian. Ia mengacu pada bagaimana individu atau kelompok yang menjadikan wacana dan tradisi keagamaan, yang populer ataupun yang institusional, sebagai basis atau inspirasi untuk gerakan dan praktik kesehariannya.[22] Gerakan komunitas juga dapat dijelaskan sebagai fenomena kreativitas keagamaan (religious creativity), yaitu gagasan dan praktik “baru” hasil dari rumusan ulang atau adaptasi nilai atau ajaran keagamaan untuk mengatasi tantangan hidup, misalnya krisis atau ketidakadilan lingkungan. Kreativitas keagamaan merupakan rangkaian proses yang mencakup tiga elemen: 1) rumusan gagasan dan nilai tentang dunia yang dihadapi (kosmologi) dalam wujud simbol (seperti situs suci), ritual, pesan leluhur, dan lainnya yang digunakan dalam menyikapi dan mengatasi tantangan hidup; 2) penjelasan logis bahwa masalah hidup (misalnya ketidakadilan atau krisis lingkungan) yang sedang dihadapi bertentangan dengan atau mengancam keberlanjutan keyakinan/keagamaan; dan 3) pengembangan kapasitas, agenda dan strategi bersama yang berupa pengalaman baru dan cara baru dalam menyikapi dan menghadapi masalah hidup.[23]
Konsep lived religion dan religious creativity penting digunakan untuk menegaskan bahwa gerakan komunitas menolak geotermal adalah “realitas keagamaan”, obyek material KBB. KBB mencakup dua ranah, yaitu keyakinan (forum internum) dan ekspresi keyakinan (forum externum).[24] Lived religion dan religious creativity, selain menekankan pentingnya melihat agama atau kepercayaan sebagaimana ia dijalankan dalam keseharian, adalah kritik terhadap konsep atau teori agama/kepercayaan yang secara sempit membatasi keagamaan atau kepercayaan pada doktrin teologis berbasis teks dan kelembagaan yang meniscayakan otoritas untuk validitas kebenaran (keagamaan). Konsep agama yang terakhir perlu terus dipersoalkan karena sebagaimana digunakan oleh negara ia melegitimasi diskriminasi: yang (tidak) beragama/berkepercayaan, (tidak) mendapatkan perlindungan KBB, dan mereka yang pemahamannya bertentangan dengan pandangan elite/otoritas dipersoalkan validitas keagamaannya, atau bahkan disesatkan, dan dikriminalisasi.
2. Advokasi kelompok rentan.
Sayangnya, konsep atau teori agama yang digunakan negara cukup berpengaruh di kalangan warga. Sekalipun patuh menjalankan Islam atau Kristen, banyak warga merasa tidak otoritatif membahas Islam atau Kristen yang dijalankannya, termasuk dalam hal menggunakan narasi dalam gerakan komunitas menolak geotermal. Alasan utama mereka adalah karena mereka bukan pemimpin atau tokoh agama (ustadz, pendeta atau Romo).
Dalam kaitan itu, advokasi KBB perlu menekankan bahwa KBB sebagai norma konstitusi adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak KBB bagi setiap individu dan kelompok warga negara. Setiap individu warga dijamin oleh negara untuk meyakini dan mengekspresikan agama/kepercayaan atau keyakinannya selama tidak melanggar batasan (hak orang lain, kepentingan umum, keamanan publik, dan lain-lain) yang telah diatur oleh peraturan yang nondiskriminatif. Warga petani yang patuh menjalankan agamanya, berhak menggunakan narasi agamanya sesuai pemahamannya, dan negara wajib melindunginya, sekalipun narasinya berbeda dari atau bertentangan dengan tokoh agama.
Jika misalnya tokoh NU seperti Ulil Absar Abdallah mendukung tambang berdasarkan pemahamannya terhadap Islam, dan warga petani Muslim menolak proyek geotermal yang juga berdasarkan keyakinan Islamnya, keduanya setara dalam prinsip KBB. Perbedaannya adalah jika pandangan Ulil diekspresikan dan menyebabkan pelanggaran hak warga petani Muslim tersebut, KBB atau hak lainnya, ekspresi keyakinan Ulil (misalnya tambang atas nama agama) wajib dibatasi oleh negara, menurut norma KBB. Penolakan proyek geotermal oleh warga petani Muslim tersebut wajib dilindungi oleh negara, menurut norma KBB, karena alasan penolakannya adalah keyakinan dan praktik Islam terkait perawatan alam.
3. Interseksionalitas KBB.
Pemilahan atau pembedaan isu lingkungan, agama, ekonomi, dan seterusnya bermasalah jika dilihat tidak berkelindan. Agama dan budaya yang terlanjur dibedakan oleh proyek kolonialisme dan sekularisme dan terus direproduksi negara hingga saat ini tetap dapat dilihat berbeda, tetapi senantiasa berkelindan. Agama seperti Islam lahir dari, berkembang bersama, dan menciptakan budaya. Islam faktanya kental dengan budaya Arab, kental dengan budaya Indonesia, dan kental dengan budaya apapun dimana ia berkembang. Agama dan lingkungan juga demikian. Jika lingkungan adalah ruang (termasuk aspek materalitasnya seperti tanah), maka agama dalam ajaran dan ekspresinya selalu merupakan bagian dari isu lingkungan. Lingkungan juga adalah konsepsi terkait makna dan fungsinya, dan konsepsi tersebut oleh umat beragama senantiasa berbasis agama/kepercayaan atau keyakinan. Dengan kata lain, bagi umat beragama, setiap isu lingkungan, atau budaya, selalu berkaitan dengan isu agama, sebagaimana tampak dalam gerakan komunitas menolak proyek geotermal.
Merujuk pada konteks di atas, advokasi KBB perlu mengurai dua konsep. Pertama, interkoneksi hak KBB dengan hak lainnya. Menurut konsep ini, penghormatan satu aspek hak, seperti hak KBB, tidak boleh melanggar hak lainnya, dan pelanggaran satu aspek hak, seperti hak lingkungan, berpotensi melanggar hak-hak lainnya. Konsep advokasi KBB ini perlu digunakan untuk menginvestigasi kasus proyek geotermal. Di beberapa kasus, proyek geotermal (akan) dikembangkan di kawasan konservasi. Kawasan tersebut ada dalam penguasaan negara, atau bersih dari kepemilikan tanah oleh warga. Proyek geotermal tersebut kemudian diasumsikan tidak (akan) melanggar hak warga atas tanah. Atau, di beberapa kasus lainnya, proyek geotermal (akan) dikembangkan di lahan yang sudah dibeli dari warga. Kepemilikan tanah sepenuhnya ada di tangan perusahaan, dan karena itu dianggap tidak (akan) melanggar hak warga atas tanah.
Berdasarkan data gerakan komunitas, proyek geotermal telah memicu kerusakan ekosistem, menguras jutaan debit air, memicu gempa, dan selalu berpotensi mengeluarkan uap beracun, yang jangkauannya melampaui area eksplorasi proyek geotermal hingga pemukiman warga. Dampak buruk proyek geotermal tersebut (berpotensi) melanggar banyak hak warga, bukan hak atas tanah, tetapi hak (ruang) hidup. Dalam konteks itu, hak KBB mereka (potensial) dilanggar. Keyakinan dan ekspresi keagamaan “ekoteologi” (situs suci, ritual, gerakan) mereka (terancam) dilanggar.
Kedua, interseksionalitas KBB. Hakikat penegakan norma KBB terletak pada konteks relasi kuasa yang timpang. Dalam struktur keagamaan, selalu ada relasi kuasa yang timpang. Karena NU dan Muhammadiyah misalnya merupakan dua organisasi keagamaan yang paling besar dan dimuliakan di Indonesia, otoritas keduanya cenderung mendapatkan perlakuan istimewa dari kekuasaan atau pihak lainnya. Jika kedua otoritas lembaga tersebut misalnya mendukung dan menerima konsesi tambang, dan kelompok lain, termasuk warga NU dan warga Muhammadiyah sendiri, menolak tambang, termasuk proyek geotermal, negara tidak boleh diskriminatif dengan memuliakan otoritas NU dan Muhammadiyah di sisi lain, dan melanggar hak warga yang menolak tambang. Diskriminasi tersebut melanggar norma KBB.
Pola serupa terjadi dalam isu ke(tidak)adilan lingkungan. Untuk isu tersebut, dua pemahaman lingkungan layak jadi perhatian, yaitu pemahanan lingkungan versi orang kaya (environmentalism of the rich) vs pemahaman lingkungan versi orang miskin (environmentalism of the poor). Geotermal sebagai energi bersih adalah berdasarkan pemahaman lingkungan versi orang kaya. Narasi kebersihannya diwacanakan untuk keuntungan ekonomi (khususnya orang kaya, pemodal). Geotermal sebagai ancaman ruang hidup adalah berdasarkan pemahaman lingkungan versi orang miskin, yang menggantungkan keberlanjutan hidupnya pada ekosistem lingkungan dan ruang hidup. Relasi kuasa antara orang kaya vs orang miskin sangat timpang. Hampir semua kasus pembangunan ekstraktif, (aparat) negara mengistimewakan orang kaya atau pemodal, dan memperlakukan orang miskin sebagai tak berpengetahuan dan butuh pendidikan untuk menerima pemahaman lingkungan versi orang kaya, misalnya dalam praktik sosialisasi proyek geotermal.
Kedua kelompok elite (otoritas agama dan pemodal) yang dimuliakan saling berbagi kuasa (difasilitasi oleh kekuasaan) dalam mereproduksi kerentanan komunitas lokal, seperti mereka yang tergabung dalam gerakan komunitas, yang mencakup kelompok minoritas, petani, miskin, perempuan, anak, lansia dan seterusnya. Dengan kuasa agamanya, otoritas agama menghadiahkan narasi surgawi, misalnya alam (hutan, panas bumi, dll.) adalah SDA nikmat Tuhan untuk kesejahteraan manusia, kepada pengembang tambang termasuk geotermal yang dengan kuasa ekonominya menawarkan keuntungan ekonomi sebagai timbal balik. Struktur kuasa agama dan struktur kuasa ekonomi dibuat interseksional, dan hasilnya saling mengunci (interlocking): struktur kuasa agama menguat karena struktur ekonomi menguat, dan demikian pula sebaliknya. Penting diperhatikan bahwa interseksionalitas kedua struktur tersebut hanya bisa menguat jika sekaligus merentankan kelompok relasi di bawahnya, seperti gerakan komunitas (minoritas, petani, miskin). Kedua otoritas mereproduksi kerentanan warga yang berjuang mempertahankan ruang hidup, misalnya melalui tuduhan “wahabi lingkungan”.
Interseksional KBB menekankan bahwa (penghormatan atau pelanggaran hak) KBB adalah sistemetik, yang sistemnya adalah bagian dari sistem (penghormatan atau pelanggaran hak) lingkungan. Dalam konteks gerakan komunitas menolak geotermal, untuk melegitimasi perampasan wilayah adat (untuk proyek geotermal), adat misalnya harus dideligitimasi sebagai agama/kepercayaan. Dengan delegitimasi tanah adat sebagai keyakinan dan ekspresi agama/kepercayaan, peraturan kepemilikan tanah pribadi untuk bisa diperjualbelikan sebagai sistem agraria/lingkungan menjadi legal, atau sah melanggar hak ruang hidup warga adat.
Rekomendasi
1. Advokasi KBB perlu menghindari jebakan nomenklatur agama sebagaimana diatur oleh negara. Agama bukan hanya yang dikelola oleh kementerian agama, dan pemeluk agama yang wajib dimuliakan bukan hanya otoritas agama yang diatur oleh pemerintah.
2. Advokasi KBB dituntut untuk mempersoalkan nomenklatur agama yang dibedakan dari kepercayaan dan dipisahkan dari dimensi kehidupan warga lainnya. Ia penting mengedepankan interkoneksi dan interseksionalitas KBB. Gerakan komunitas (lintas agama, kepercayaan dan adat) menolak geotermal mengurai interkoneksi dan interseksionalitas KBB tersebut.
3. Advokasi KBB wajib menginvestigasi relasi kuasa, dan mengedepankan advokasinya pada kelompok rentan lintas identitas dan lintas isu. Untuk poin ini, di antara strategi advokasi yang perlu dikembangkan adalah konsolidasi komunitas, terutama komunitas rentan.
4. Advokasi KBB dituntut untuk dikembangkan bersama dengan advokasi lingkungan, anak, perempuan dan gender, disabilitas, dan lain-lainnya. Semua kelompok rentan berbasis identitas tersebut di hampir semua faktanya adalah hasil orkestra perentanan oleh elite lintas kepentingan melalui interseksionalitas struktur kuasa.
[1]Trend Asia. “Perempuan Sukatani Tolak Proyek Geotermal Gunung Gede Pangrango”, 13 Desember 2025. https://trendasia.org/perempuan-sukatani-tolak-proyek-geotermal-gunung-gede-pangrango/. (Diakses 30 Desember 2025).
[2]Fuad Faizi, dkk. Energi Hijau vs. Pelestarian Ruang Hidup: Cerita Warga Melawan Geotermal. Hal. 35-58. (Media Kawan Lama, ICRS, dan CRCS UGM, 2025)
[3]Dirjen EBTKE. “Dirjen EBTKE: Pengembangan Panas Bumi Harus Berkelanjutan dan Harmonis,” 14 April 2025. https://ebtke.esdm.go.id/artikel/berita/dirjen-ebtke-pengembangan-panas-bumi-harus-berkelanjutan-dan-harmonis (Diakses 23 Desember 2025).
[4]Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy transitions drive polarization: Narratives of green energy and mitigation strategies by proponents and opponents of geothermal energy developments in Indonesia”. Energy Policy 210 (2026): 115080. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2026.115080
[5]Susilowati, M. H., J. D. Smith, Maarif, S., Cahyono, E., “Geothermal Narratives and Grassroots Resistance in Indonesia: Decolonial Frameworks for Energy Transitions and Environmental Justice.” Capitalism Nature Socialism (2026): 1-17. https://doi.org/10.1080/10455752.2025.2607977
[6]Dirjen EBTKE. “Dirjen EBTKE: Pengembangan Panas Bumi Harus Berkelanjutan dan Harmonis,” 14 April 2025. https://ebtke.esdm.go.id/artikel/berita/dirjen-ebtke-pengembangan-panas-bumi-harus-berkelanjutan-dan-harmonis (Diakses 23 Desember 2025).
[7]Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy…
[8]Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy…
[9]Hendrik, “Proyek Senyap Negara, Keteguhan Perlawanan Warga”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau vs. Pelestarian Ruang Hidup: Cerita Warga Melawan Geotermal. Hal. 35-58. (Media Kawan Lama, ICRS, dan CRCS UGM, 2025)
[10]Jelsy Sanggola, “Geotermal: Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif”. Dalam Faizi, dkk., Hal. 201-208
[11]Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal Merusak di Pocoleok, masyarakat Adat Melawan”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 245-257
[12]Cici Alifiah Linggawati, “Krisis Sumber Mata Air: Penyebaran Pengetahuan untuk Menolak Rencana Pembangunan Geotermal di Kota Batu-Malang”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 151-168
[13]Cece Jaelani, “Geotermal Datang, Tawarkan Konflik, dan Petani Melawan”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 59-76
[14]Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal …
[15]Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal …
[16]Riwan Basir, “Dampak Multidimensi Tambang Geotermal di Maluku Utara”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 209-218
[17]Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal …
[18]Cici Alifiah Linggawati, “Krisis Sumber Mata …
[19]Ickra Suciana Azalia, dkk., “Bakal, “Bathin Lan Akal” (Riwayat dan Ruwat yang Terancam Energi Hisap)”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 169-200
[20]Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal …
[21]Antonius Anu, “Geotermal Mengancam Kehidupan Mataloko”. Dalam Faizi, dkk. Energi Hijau … Hal. 219-228
[22]Jonathan D. Smith, R. Adam and S. Maarif, “How social movements use religious creativity to address environmental crises in Indonesian local communities.” Global Environmental Change 84 (2024): 102772. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102772
[23]Jonathan D. Smith, R. Adam and S. Maarif, “How social …
[24]Lihat Johanna G. S. D. Poerba dan Nabila Syahrani, LeIP. https://kbb.id/2026/01/16/pembatasan-yang-tidak-sah-pembubaran-ibadah-dan-siklus-kekerasan-berbasis-agama-terhadap-anak/











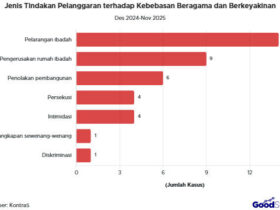
Leave a Reply