Penulis: Lailatul Fitriyah | Republikasi dari IndoProgress
“MARILAH berharap bahwa [konferensi] ini akan menghasilkan hubungan yang lebih baik di antara agama-agama yang berkonflik dalam rangkulan Kerajaan Inggris Raya; dan dengan itu, akan membawa perdamaian dan ketenangan yang permanen untuk seluruh manusia.”
Pernyataan di atas adalah bagian dari pidato Mustafa Khan, seorang tokoh muslim dari Lahore, Pakistan, dalam konferensi berjudul Agama-Agama di Kerajaan Inggris Raya: Konferensi tentang Beberapa Tradisi Agama di dalam Kerajaan Inggris Raya, yang diadakan di Institut Kerajaan di London pada 22 September sampai 3 Oktober 1924. Perhatikan bahwa dia menekankan aspek dalam rangkulan Kerajaan Inggris Raya ketika menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, seluruh umat manusia disatukan dalam rasa kemanusiaan yang sama.
Tak banyak yang berubah dalam pemahaman tentang apa itu “dialog antaragama” sejak tahun 1924, sebagaimana yang kita lihat dari banyak pernyataan para aktivisnya akhir-akhir ini—terutama dari mereka yang membenarkan kunjungan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel. Dalam artikel ini saya akan menjelaskan problematika konsepsi dialog antaragama yang umum dipraktikkan di Indonesia dan mengapa hal itu telah mengorbankan keadilan atas nama perdamaian semu. Di akhir artikel, saya menawarkan pemahaman dekolonial atas dialog antaragama dan bagaimana untuk mempraktikkan dialog antaragama yang menyatukan realisasi keadilan dengan realisasi perdamaian.
Akar Imperial dari Dialog Antaragama
Dialog antaragama seperti yang kita kenal sekarang tidak berasal dari niat baik perdamaian, melainkan ambisi kolonial Eropa di abad ke-19 dan ke-20. Di abad ke-19, ketika penjajahan negara-negara Eropa telah mencapai Afrika dan Asia Tenggara, juga Inggris telah mencaplok anak benua India, para akademisi Eropa menemukan fokus baru dalam kegiatan akademik mereka, yakni upaya untuk mendefinisikan apa itu “agama”.
Penting untuk disadari, seperti yang dijelaskan oleh Tomoko Masuzawa dan teoretikus studi agama lainnya, bahwa kategori “agama” adalah produk yang tumbuh dari konteks keagamaan Eropa, terutama dari perpisahan besar dalam tubuh tradisi Kristen yang salah satunya melahirkan etos dan logika Protestanisme.
Akademisi seperti Friedrich Max Müller, James Frazer, dan Rudolf Otto—yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Bidang Studi Perbandingan Agama-Agama—menggunakan sumber daya, koneksi, dan subjek-subjek kolonial untuk membandingkan agama-agama nonkristiani dengan tradisi Kristen di Eropa. “Agama” kemudian dipahami sebagai bentuk-bentuk keimanan yang menyerupai visi kulit putih Eropa tentang tradisi Kristen: Memiliki kitab suci, konsepsi ketuhanan (teologi), dan yang terpenting, sesuatu yang dapat dipisahkan dari etos politik.
Dalam rangka perbandingan agama-agama nonkristiani dengan tradisi Kristen Eropa inilah muncul keinginan dari kelompok-kelompok elite Eropa untuk belajar dari umat beragama lain. Di wilayah-wilayah koloni sendiri tentunya dialog antaragama dalam bentuk misi Kristen telah dijalankan oleh organisasi-organisasi misionaris dan ordo-ordo Kristen. Banyak dari para misionaris ini, seperti Henri-Alexandre Junod dan Henry Callaway, kemudian menjadi peneliti lapangan bagi para akademisi yang berbasis di Eropa. Berbeda dengan misi kristenisasi yang dibawa oleh para misionaris, studi para akademisi tersebut didasari oleh ambisi akademis (klasifikasi agama-agama nonkristiani dalam hierarki developmentalis dengan Kristen sebagai agama paling maju), ambisi teologis (mencari pembenaran atas klaim Kristen sebagai agama universal), dan ambisi kolonial (membantu administrasi penjajahan untuk memudahkan manajemen sumber daya subjek-subjek yang dijajah).
Maka, dimulai dari pertemuan Parlemen Agama-Agama Dunia pertama—sebagai bagian dari Pameran Columbian di Chicago tahun 1893—serangkaian konferensi dan pameran tentang agama-agama nonkristiani diadakan, dari mulai di Paris (1900), Basel (1904), Oxford (1908), Leiden (1912), dan London (1924) di mana Mustafa Khan berpidato sebagai salah satu perwakilan dari Islam. Dalam konferensi dan pameran ini para peserta nonkristiani diundang untuk bicara tentang agama mereka, bukan karena dianggap sebagai rekan yang setara melainkan sebagai spesimen yang harus diobservasi dari mikroskop imperialis Eropa.
Mereka didatangkan ke Eropa untuk menjadi bukti keagungan tradisi Kristen Eropa, yang melalui praktik penjajahannya telah berhasil “menyatukan” berbagai kelompok manusia yang berbeda. “Kemunduran” keagamaan mereka adalah bukti dari klaim kemajuan dan universalitas Kristen. Kedatangan mereka secara berbondong-bondong ke pusat-pusat kolonial Eropa menjadi simbol “perdamaian” imperial yang dicirikan oleh dominasi di wilayah-wilayah jajahan. Kehadiran mereka menjadi pertunjukan atas kesuksesan rezim kolonial untuk mengubah masyarakat “tak beradab” menjadi “beradab”.
Di mana posisi Yahudi—sebagai tradisi agama—dalam dinamika ini? Perspektif kolonial dalam bidang ilmu perbandingan agama-agama di abad ke-19 dan awal abad ke-20 menempatkan mereka sebagai liyan yang juga bagian dari Eropa. Didukung dengan doktrin-doktrin antisemitik gereja, Yahudi dianggap sebagai akar sejarah Kristen yang harus ditinggal di masa lalu. Terutama setelah Max Müller menulis teori perbandingan agama melalui kajian filologisnya, Yahudi dikelompokkan dalam agama Semit bersama Islam, sedangkan Kristen dalam bentuknya di Eropa dimasukkan dalam kategori Aryan (penting untuk disebutkan bahwa Müller mengonsepsikan Aryan secara khusus sebagai keluarga bahasa, bukan sebagai pembenaran rasisme). Maka, dapat disimpulkan bahwa kala itu Yahudi juga menjadi subjek pemikiran kolonial di Eropa.
Antara Perdamaian dan Keadilan
Di kelas-kelas pertama yang saya ikuti dalam studi master bidang perdamaian internasional di Amerika Serikat, ada sebuah aktivitas yang saya benci. Dosen membagi mahasiswa menjadi dua grup, yaitu grup perdamaian dan grup keadilan. Kami bebas memilih grup mana yang mau kami ikuti dan saya selalu memilih grup keadilan. Kemudian, dosen akan memberikan tugas kepada masing-masing grup untuk mencapai rekonsiliasi sebuah konflik dengan berpegang teguh kepada nilai kami masing-masing, perdamaian dan keadilan. Grup keadilan yang saya ikuti selalu gagal mencapai rekonsiliasi walaupun kami berusaha keras mewujudkannya. Sebaliknya, upaya grup perdamaian selalu mencapai kesuksesan.
Beberapa tahun setelah lulus dari program tersebut, barulah saya mengerti mengapa mencapai rekonsiliasi sangat sulit—namun sangat diperlukan—dari perspektif keadilan. Apa yang diajarkan oleh dosen saya kala itu bukanlah soal pentingnya perdamaian dan kompleksnya keadilan, melainkan konsepsi perdamaian yang tidak berdiri di atas fondasi keadilan hanya akan menghasilkan perdamaian imperial yang dicapai dengan pengorbanan mereka yang paling marjinal.
Seperti halnya perdamaian dalam rangkulan Kerajaan Inggris Raya yang didengungkan oleh Mustafa Khan, perdamaian imperial menekankan tercapainya rekonsiliasi, menjembatani perbedaan, dan pemahaman pluralitas yang dangkal. Perdamaian imperial umumnya terjadi di kalangan elite dan tidak berakar di realitas kehidupan masyarakat marjinal. Alih-alih untuk semua manusia seperti klaim Khan, perdamaian imperial mewujudkan stabilitas di kalangan elite untuk melestarikan cengkeraman kuasa masing-masing. Dialog yang memiliki misi perdamaian imperial sebenarnya bukanlah dialog antaragama, melainkan dialog antarkuasa.
Rangkaian kunjungan para agamawan Indonesia (Islam, Kristen, dan lain-lain) ke Israel yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir adalah contoh dari praktik perdamaian imperial ini. Pertama, tidak ada satu pun dari kunjungan-kunjungan tersebut yang didasari oleh pertimbangan keadilan bagi rakyat Palestina. Klaim-klaim rekonsiliasi, bicara kebenaran di depan penguasa, dan upaya agar Israel menghentikan penjajahannya—yang didengungkan oleh para delegasi Indonesia tersebut—tidak ada artinya di hadapan kelindan kuasa imperial yang mendukung penjajahan atas Palestina. Sekuat apa pun para delegasi tersebut melobi pemerintah Israel untuk menghentikan kekejamannya, upaya tersebut tidak sepadan dengan keuntungan simbolik yang didapatkan oleh Israel: Serombongan agamawan berkulit cokelat dari negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tersenyum lebar dalam foto-foto dengan pejabat Israel.
Puncak kesuksesan kampanye kolonial adalah ketika para penjajah dapat menunjukkan bahwa subjek yang terjajah setuju dengan, berpartisipasi dalam, dan terlihat bahagia dengan praktik penjajahan mereka.
Delusi para delegasi Indonesia akan kesetaraan mereka dengan para pejabat Israel adalah elemen kedua yang terlihat dari praktik perdamaian imperial tersebut. Seperti halnya Mustafa Khan dan para delegasi nonkulit putih, nonkristiani lainnya di tahun 1924, para agamawan Indonesia ini berpikir bahwa undangan dari Israel tersebut adalah pengakuan internasional terhadap reputasi mereka; pengakuan terhadap posisi mereka yang setara dalam hierarki kuasa. Seperti halnya subjek-subjek terjajah lain yang berperan sebagai informan bagi rezim kolonial (native informant, Spivak), para delegasi ini berpikir bahwa mereka sedang berdialog, padahal sejatinya menjadi tontonan dalam sirkus para penjajah.
Pada akhirnya, mereka pulang dengan kebanggaan tak terkira, berpikir telah menjadi pahlawan perdamaian, padahal sejatinya kehadiran mereka di pusat metropolis kolonial semakin meneguhkan fondasi penjajahan itu sendiri. Sebagai representasi elite dari masyarakat yang terjajah, delegasi ini sebenarnya telah terlibat bukan dalam dialog antaragama, melainkan dalam dialog antarkuasa.
Melihat Dialog Antaragama dalam Paradigma Dekolonial
Sebagai dosen pendidikan antaragama di sebuah kampus di Amerika Serikat, saya umumnya memulai kelas dengan “merukiah” para mahasiswa. Seperti para delegasi agamawan dan banyak tokoh dialog antaragama di Indonesia, para mahasiswa saya memahami bahwa dialog antaragama adalah untuk membangun hubungan (building bridges) dengan siapa saja, termasuk dengan para penindas. Asumsi ini biasanya disertai dengan argumentasi ketidakberpihakan (karena bagaimana mungkin kita berdamai dengan para penindas kalau kita berpihak dengan mereka yang marjinal?) dan argumentasi kesetaraan (bahwa setiap dialog antaragama terjadi antara dua pihak yang setara posisinya).
Kelas teori-teori dialog antaragama saya umumnya dimulai dengan bacaan-bacaan dari studi dekolonial dan poskolonia. Tujuannya tidak lain untuk membersihkan asumsi-asumsi perdamaian imperial dari benak para mahasiswa. Di akhir semester, para mahasiswa akan memahami bahwa dialog antaragama bukanlah ajang foto-foto bersama dan diskusi-diskusi simbolis di mana tuntutan keadilan tidak didengungkan. Mereka juga memahami bahwa dialog antaragama adalah konteks yang penuh dengan konflik, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara terus-menerus mendialogkan cara-cara terbaik untuk mencapai keadilan.
Ya, dalam kelas teori-teori dialog antaragama yang saya ajarkan, dialog antaragama adalah konteks yang seharusnya penuh dengan konflik, bukan menghindari konflik.
Lalu, bagaimana seharusnya dialog antaragama dilakukan dalam konteks genosida yang sedang berlangsung di Palestina dan berbagai belahan dunia saat ini? Para mahasiswa di kampus-kampus Amerika Utara yang membangun tenda perdamaian bagi Palestina dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkannya kepada kita semua. Dalam kompleks tenda perdamaian tersebut, para mahasiswa dengan berbagai latar belakang tradisi merayakan ritual keagamaan satu sama lain dengan fokus tuntutan untuk mengakhiri penjajahan terhadap Palestina. Mahasiswa Islam, Yahudi, dan Kristen berpartisipasi dalam ritual agama satu sama lain, juga saling melindungi dari kekerasan polisi dan kampus yang ingin mengakhiri pergerakan mereka.
Inilah salah satu contoh dialog antaragama sesungguhnya: ditujukan untuk mencapai keadilan bagi mereka yang marjinal, untuk mengakhiri kuasa para penindas, dan dilakukan dengan cara yang kritis dan dekolonial. Mereka tidak berdialog dengan para penindas, melainkan menyatukan perbedaan keagamaan untuk mengakhiri kekuasaan para penindas.
Dialog antaragama dalam paradigma dekolonial bukanlah dialog yang membabi buta tanpa keberpihakan, yang pada akhirnya hanya akan melestarikan kekuasaan. Pun, dialog antaragama dalam paradigma dekolonial tidak berakar dari ilusi kesetaraan kuasa yang merupakan bagian dari narasi kolonial, melainkan dari pemahaman bahwa relasi sosial, politik, dan keagamaan di dunia selalu terjadi dalam hierarki kuasa imperial yang harus didekonstruksi terlebih dahulu sebelum perdamaian dapat diwujudkan. Dialog antaragama harus meletakkan fokus keadilan sebagai fondasi utamanya, dan dengan demikian berpihak kepada mereka yang marjinal, serta tidak membangun hubungan dengan para penindas.
Kepustakaan
Chidester, David. Empire of Religion: Imperialism and Comparative Religion. Chicago: The University of Chicago Press, 2014.
Masuzawa, Tomoko. The Invention of World Religions: or, How European Universalism was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
Spivak, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.









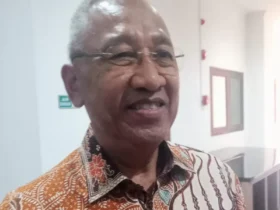
Leave a Reply