Oleh: Arina Rahmatika
Sore itu (Kamis, 2/10), Bogor membuktikan julukannya sebagai kota hujan. Langit perlahan menggelap, dan bekas hujan masih terasa di halaman Pusat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Payung, Bogor. Suasana sore itu begitu syahdu, ketika kami rombongan dari Koalisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) melangkah masuk menuju Aula JAI. Udara lembab, tapi suasana hangat. Hari itu bukan sekadar kunjungan biasa, bagi kami, ini adalah perjumpaan yang menembus sekat-sekat prasangka dan membawa kami melihat wajah lain dari keberagaman di Indonesia.
Kami disambut oleh beberapa anggota JAI yang ramah. Tak lama kemudian, hadir pula Amir JAI, pimpinan pusat organisasi ini. Dengan nada tenang, beliau membuka pembicaraan dengan sejarah singkat perjalanan JAI di Indonesia. Tahun ini, katanya, Jamaah Ahmadiyah Indonesia genap berusia seratus tahun. Satu abad, angka yang tidak main-main untuk sebuah komunitas keagamaan yang sering berada dalam posisi terpinggirkan.
“Wah, sudah 100 tahun ya. Padahal Indonesia merdeka saja baru 80 tahun,” celetuk salah satu peserta dari Nusa Tenggara Timur, seorang pemuda Kristen yang baru pertama kali bersentuhan langsung dengan komunitas Ahmadiyah. Kami semua tertawa kecil, tapi komentar itu mengandung makna mendalam, bahwa betapa panjang dan kuatnya akar keberadaan JAI di negeri ini, jauh sebelum republik ini berdiri.
Menyentuh Realitas, Bukan Sekadar Membaca Berita
Selama ini, isu Ahmadiyah sering hadir dalam diskusi kami di koalisi KBB, biasanya dalam bentuk berita pelarangan, pengusiran, atau kekerasan terhadap mereka. Tapi kali ini berbeda, kami berhadapan langsung dengan manusia di balik berita, tentu dengan wajah, cerita, dan perasaan yang nyata. Kami mendengarkan kisah perjuangan mereka bertahan di tengah tekanan sosial dan politik, mendirikan rumah ibadah yang bisa sewaktu-waktu digembok, dan menjalankan keyakinan di tengah stigma “sesat” yang menempel begitu kuat.
Salah satu isu yang sempat kami bahas dalam kegiatan advokasi KBB di Bogor adalah kasus pembubaran Jalsah Salanah tahun 2024 di Kuningan, Jawa Barat. Jalsah Salanah adalah acara tahunan JAI yang diadakan sebagai forum silaturahmi antaranggota. Namun, acara ini kembali dibubarkan dengan alasan keamanan dan desakan kelompok intoleran.
Kami menelaah kasus itu dari berbagai sisi, siapa aktor yang berperan, bagaimana kebijakan pemerintah daerah, dan kepentingan apa yang tersembunyi di balik keputusan tersebut. Dari situ terlihat jelas bahwa pelanggaran kebebasan beragama tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu terkait dengan dinamika kekuasaan, kompromi politik, dan tafsir keagamaan yang dijadikan alat pembenaran.
Padahal, jika kita kembali pada prinsip dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan, konstitusi Indonesia sudah tegas melindunginya. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Artinya, JAI berhak menjalankan ajarannya tanpa ancaman, sebagaimana umat beragama lain. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang lebar antara hukum dan praktik.
Siapa yang Berhak Menentukan Kesesatan?
Pertanyaan yang muncul di tengah perbincangan sore itu antar peserta adalah “Apakah JAI sesat?” Pertanyaan yang sederhana, tapi sekaligus rumit. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan kesesatan suatu ajaran yang diyakini banyak orang? Apakah negara, dengan perangkat hukumnya yang sering berpihak pada mayoritas? Apakah masyarakat, dengan tafsir agamanya yang dianggap paling benar? Atau apakah setiap individu berhak menempuh jalannya sendiri menuju Tuhan?
Salah satu anggota JAI yang menyambut kami sempat bergurau, “Bagi teman-teman Muslim, silakan salat di masjid kami. Silakan lihat sendiri apakah kami menghadap ke timur atau tidak.” Tawa kami pecah, tapi gurauan itu menyimpan kegetiran. Betapa banyak stigma yang menempel pada mereka tanpa dasar yang jelas. Banyak orang menuduh Ahmadiyah menyimpang tanpa pernah melihat langsung bagaimana mereka beribadah, tanpa pernah mendengar penjelasan dari mereka sendiri.
Dalam obrolan yang mengalir santai itu, saya mulai merenung. Betapa mudahnya masyarakat kita menempelkan label “sesat” kepada yang berbeda. Padahal, setiap agama besar di dunia lahir dari pergulatan tafsir dan perbedaan pandangan. Islam sendiri mengenal berbagai mazhab dan aliran, tetapi mengapa hanya beberapa di antaranya yang dianggap sah? Apakah karena jumlah penganutnya, atau karena tafsirnya lebih disukai penguasa?
Label sesat seringkali menjadi senjata yang mematikan. Ia bukan hanya melukai harga diri kelompok tertentu, tetapi juga menjadi justifikasi untuk membenarkan kekerasan. Dari pengusiran, perusakan rumah ibadah, hingga pelarangan aktivitas keagamaan, semua dilakukan atas nama “menjaga kemurnian iman”. Padahal, jika kita membaca sejarah Islam sendiri, Nabi Muhammad justru datang membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk memaksakan satu cara beriman.
Refleksi dari Sebuah Kunjungan
Bagi saya pribadi, kunjungan ke JAI Bogor menjadi pengalaman yang menumbuhkan empati dan kesadaran baru. Saya melihat wajah-wajah yang tetap tersenyum meski kerap menjadi sasaran kebencian. Saya mendengar suara yang tenang namun tegas ketika mereka berbicara tentang hak mereka sebagai warga negara. Tak ada kebencian dalam kata-kata mereka, hanya keinginan sederhana, agar mereka diakui sebagai bagian sah dari bangsa ini.
Malam itu, di tengah hujan yang sudah reda, saya memandang ke halaman depan yang mulai tergenang air. Dalam diam, saya teringat pada ironi, bangsa yang bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi masih gagap ketika harus menerima perbedaan iman di depan mata. Kita sering berbicara tentang toleransi di seminar dan media sosial, tetapi gagal menerapkannya di dunia nyata.
Toleransi sejati, saya pikir, bukan soal seberapa sering kita bicara tentangnya, tetapi seberapa berani kita membuka hati untuk mengenal yang berbeda. Tidak perlu setuju dengan semua ajaran, tapi cukup belajar menghormatinya. Karena begitu kita mulai menolak keberadaan orang lain hanya karena keyakinannya berbeda, di situlah kita sedang menghapus kemanusiaan dari diri sendiri.
Ketika Perbedaan Menjadi Ruang Belajar
Di koalisi KBB, kami sering berbicara tentang “ruang aman”, tempat di mana setiap orang bisa berbicara dan beriman tanpa takut dihakimi. Tapi kunjungan ke JAI membuat saya sadar bahwa bagi banyak kelompok minoritas, ruang aman itu belum benar-benar ada. Rumah ibadah bisa disegel, acara keagamaan bisa dibubarkan, dan identitas bisa diserang hanya karena dianggap berbeda.
Namun di balik itu semua, saya juga melihat harapan. Harapan yang lahir dari keberanian JAI bertahan seratus tahun di tanah ini. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi—dalam pendidikan, kemanusiaan, dan perdamaian. Banyak anggota JAI aktif dalam kegiatan sosial, menjadi guru, dokter, dan relawan kemanusiaan. Mereka menunjukkan bahwa beragama bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bermanfaat bagi sesama.
Seratus tahun bukan waktu yang singkat. Ia adalah bukti keteguhan iman dan kedewasaan spiritual. Di usia yang ke-100 ini, JAI tidak lagi hanya mewakili kelompok Ahmadiyah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Sebuah perjuangan untuk diakui, bukan diseragamkan, tapi untuk dihormati, bukan ditakuti.
Menatap Indonesia yang Lebih Inklusif
Perjalanan kami hari itu berakhir menjelang larut malam. Udara dingin menusuk, tapi hati terasa hangat. Di perjalanan pulang, saya teringat kalimat salahsatu teman JAI:
“Kami hanya ingin diterima sebagai sesama manusia.”
Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Ia mengandung pesan yang jauh lebih luas dari sekadar perbedaan teologis. Ia adalah seruan kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar kita hidup bersama dalam negara yang majemuk.
Mungkin benar, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk memahami Ahmadiyah, seperti halnya kita tidak bisa memaksa semua orang sepakat dalam soal iman. Tapi kita bisa belajar untuk berhenti melukai, berhenti menghakimi, dan mulai mendengar.
Karena pada akhirnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya hak kaum minoritas. Ia adalah hak kita semua, hak yang menjaga agar negara ini tidak berubah menjadi milik satu tafsir, satu golongan, atau satu suara. Ia adalah napas demokrasi dan kemanusiaan itu sendiri.
Semoga di usia yang ke-100, Jamaah Ahmadiyah Indonesia semakin kuat dalam keyakinannya dan semakin diterima dalam keberagamannya. Semoga tak ada lagi Jalsah Salanah yang dibubarkan, tak ada lagi masjid yang diserang, tak ada lagi warga yang diusir karena iman. Dan semoga kita semua, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat, maupun yang tak beragama, bisa belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, tapi ruang belajar untuk menjadi manusia yang lebih utuh.
Bogor sore itu mungkin hanya memberi kami hujan, tapi di balik hujan itu, ada pelajaran yang jauh lebih dalam bahwa kebebasan berkeyakinan bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau menghormati cara orang lain menemukan kebenaran.










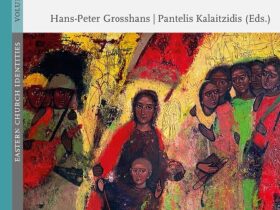

Leave a Reply