Ringkasan:
● Krisis ekologis di Sumatera memperlihatkan absennya negara dan penderitaan penyintas yang dibiarkan bertahan sendiri.
● Banjir dan longsor dipicu kerusakan hutan akibat korporasi serta buruknya tata kelola kekuasaan pusat dan daerah.
● Gerakan antar-iman menegaskan iman harus hadir membela penyintas dan memperjuangkan keadilan ekologis bersama.
Republikasi dari Institut DIAN/Interfidei
Pada Jumat, 12 Desember 2025, Jaringan Antar-Iman Indonesia menyelenggarakan talkshow bertajuk “Krisis Ekologis & Keberanian Iman” sebagai ruang refleksi dan solidaritas atas bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Kegiatan ini menghadirkan suara langsung para pejuang kemanusiaan lintas iman dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Talkshow ini diselenggarakan bukan hanya untuk mendiskusikan banjir sebagai peristiwa bencana semata, melainkan untuk mendengarkan kesaksian nyata yang kerap luput dari pemberitaan media. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa para penyintas di Sumatera tidak sendirian. Ada jejaring antar-iman di Indonesia yang hadir untuk menemani, mendukung, dan memperjuangkan keadilan bersama sebagai sesama saudara.
Sumatera Utara: Negara Absen, Rakyat Bertahan Sendiri
Ferry Wira Padang, Direktur Aliansi Sumut Bersatu, menyampaikan kesaksian mendalam tentang dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara. Wilayah seperti Tapanuli Tengah dan Sibolga menjadi daerah paling terdampak, sementara Medan dan Langkat juga mengalami banjir besar yang melumpuhkan hampir seluruh aktivitas warga. Menurut Ferry, sepanjang ia tinggal di Medan, banjir kali ini merupakan yang terparah.
Namun, yang paling menyakitkan adalah ketidakhadiran negara dalam masa tanggap darurat. Tiga hari pascabanjir, warga Medan tidak mendapatkan akses air bersih. Beban para penyintas—terutama perempuan dan anak—menjadi berlipat ganda, mulai dari kesulitan memperoleh air minum, membersihkan rumah, hingga menjaga kesehatan keluarga.
Di Sibolga dan Tapanuli Tengah, situasinya bahkan jauh lebih ekstrem. Selama tiga hari pertama, banyak warga tidak makan dan minum, terpaksa mengonsumsi air alam yang tidak layak, serta memasak beras bercampur lumpur karena kelaparan. “Mereka tidak lagi peduli nasi itu berlumpur atau tidak,” ujar Ferry, “yang penting bisa bertahan hidup.”
Ironisnya, berbagai fasilitas negara—mulai dari BASARNAS, Dinas Sosial, hingga helikopter milik TNI—tidak dimanfaatkan secara maksimal. Negara dinilai tidak siap dan tidak berempati, sehingga membiarkan masyarakat bangkit sendiri tanpa dukungan yang memadai.
Ferry juga menegaskan bahwa banjir dan longsor di Sumatera Utara tidak dapat dilepaskan dari dominasi korporasi yang merusak hutan, seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan sejumlah perusahaan lain di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Gelondongan kayu yang terbawa banjir hingga menghancurkan puluhan desa menjadi bukti nyata kerusakan ekologis yang bersifat sistemik, bahkan menyebabkan sejumlah desa hilang dari peta.
Lebih jauh, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang mewajibkan izin Kementerian Sosial bagi penggalangan donasi di atas Rp500 juta. Dalam situasi darurat kemanusiaan, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap solidaritas rakyat.
Aceh: Bencana, Kebobrokan Kekuasaan, dan Rakyat yang Ditelantarkan
Dari Aceh, Teuku Kemal Fasya, dosen Universitas Malikussaleh (Unimal), menyampaikan refleksi yang tajam. Ia menilai banjir di Aceh sebagai peristiwa yang membongkar kebobrokan tata kelola kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Wilayah seperti Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara mengalami keterputusan akses secara total. Banjir menyebabkan listrik dan internet padam, bahkan di daerah yang tidak terdampak langsung—sebuah kondisi yang, menurutnya, tidak terjadi saat tsunami Aceh. Akibatnya, terjadi diskoneksi informasi dan, dalam beberapa kasus, kerusuhan sosial.
Teuku Kemal mengungkapkan bagaimana para pejabat tampak tidak berbuat apa-apa. Beberapa kepala daerah bahkan tidak berada di lokasi saat bencana terjadi, sementara bantuan tidak kunjung datang hingga tiga hari pertama. Kondisi ini memicu penjarahan di Langsa dan Aceh Tamiang—bukan karena kriminalitas, melainkan karena warga kelaparan dan ditelantarkan.
Ia membandingkan situasi ini dengan penanganan tsunami Aceh, ketika status bencana nasional segera ditetapkan dan bantuan internasional dibuka secara luas. Dalam kasus banjir di Sumatera kali ini, status bencana nasional tidak kunjung ditetapkan, yang berdampak langsung pada lambannya mobilisasi bantuan. Akibatnya, masyarakat terpaksa menengadahkan tangan demi bertahan hidup.
Keberanian Iman dan Solidaritas Antar-Iman
Melalui talkshow ini, Jaringan Antar-Iman Indonesia menegaskan bahwa krisis ekologis merupakan krisis iman dan kemanusiaan. Ketika negara absen dan gagal melindungi rakyat, iman tidak boleh diam. Agama dan keyakinan dipanggil untuk hadir sebagai suara kenabian—membela para penyintas, mengkritik ketidakadilan, serta merawat kehidupan bersama, baik manusia maupun alam.
Talkshow ini menjadi bagian dari komitmen Gerakan Antar-Iman Indonesia untuk terus membuka ruang belajar bersama, mendengarkan suara dari akar rumput, serta menguatkan solidaritas lintas iman demi keadilan ekologis dan kemanusiaan yang bermartabat.
Editor: Andrianor

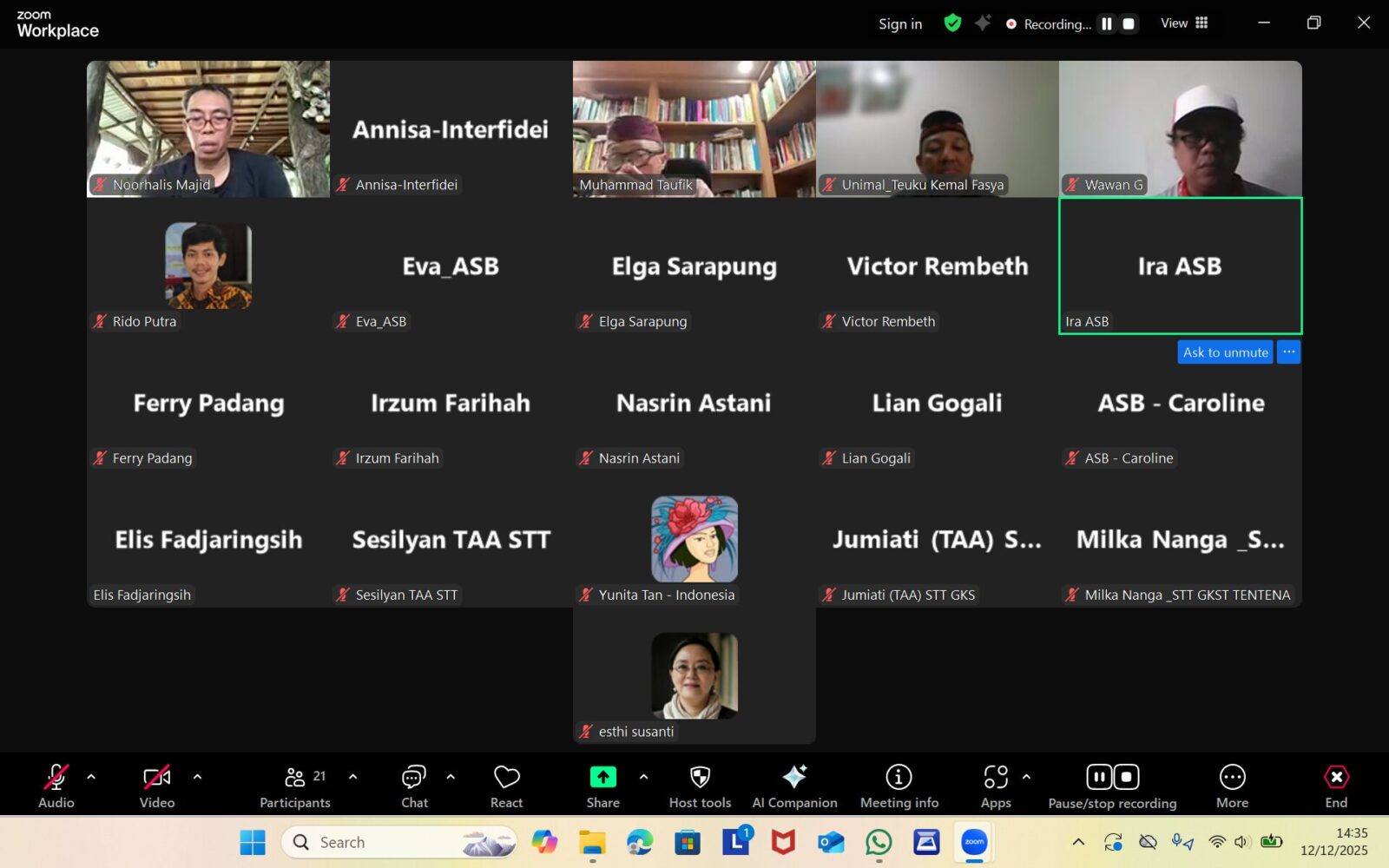










Leave a Reply