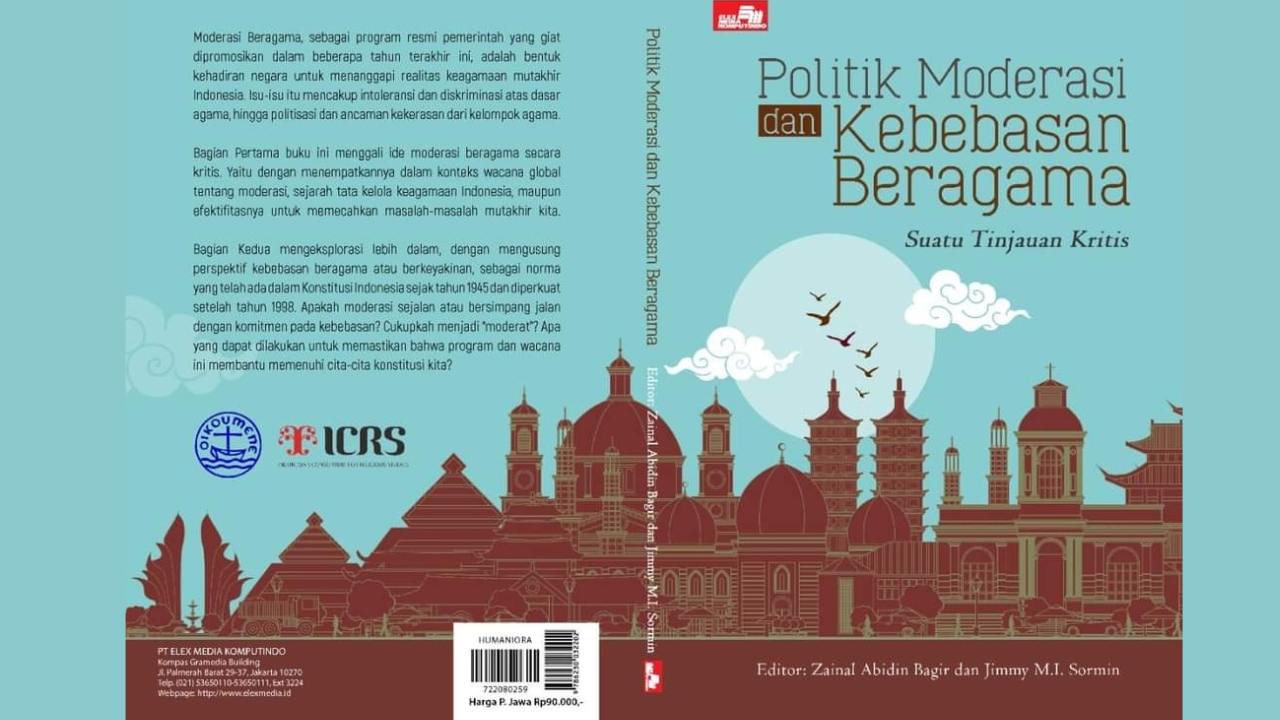Maurisa Zinira – Mahasiswa ICRS
Tantangan yang dihadapi umat beragama untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia semakin kompleks dengan melonjaknya tingkat ekstremisme agama. Ekstremisme terus mengikis nilai kebinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sektarianisme semakin kuat dan politik identitas menjadi tren dalam masyarakat majemuk Indonesia. Karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan “Moderasi Agama” untuk mengatasi krisis akibat ekstremisme agama.
Di tingkat masyarakat, program moderasi beragama yang digagas Kementerian Agama menuai berbagai tanggapan. Meski dimaksudkan untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, namun istilah dan konsep moderasi beragama tidak dapat disangkal menimbulkan polemik tentang siapa yang moderat dan siapa yang tidak. Argumen-argumen menyebar liar dan menimbulkan polarisasi di antara kelompok-kelompok agama yang terus mempersoalkan wacana moderasi. Hal ini juga meningkatkan resistensi kelompok agama anti-pemerintah.
Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) melihat efek samping yang timbul dari program pemerintah tersebut terhadap kehidupan beragama di masa depan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud melakukan delegitimasi terhadap program moderasi beragama, ICRS dan PGI menulis buku berjudul “Politik Moderasi dan Kebebasan beragama: Suatu Tinjauan Kritis”. Dalam buku ini, para penulis berupaya memberikan tinjauan kritis terhadap istilah dan konsep moderasi beragama yang dianggap rentan terhadap berbagai konflik dan kepentingan. Peluncuran buku yang digelar di Jakarta pada 12 April 2022 ini mengundang beberapa tokoh antara lain aktivis kemanusiaan seperti Alissa Wahid, akademisi, dan peneliti di Indonesia.
Moderasi Agama dan Ekstremisme
Munculnya program moderasi beragama tidak lepas dari jalannya eksklusivisme agama di Indonesia. Bisa dikatakan, program ini merupakan respons atas maraknya ekstremisme agama yang terus menghantui kehidupan beragama di Indonesia. Dalam kata pengantar buku “Moderasi Beragama” terbitan Kementerian Agama tahun 2019, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan bahwa istilah moderasi beragama mengacu pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari ekstremisme dalam agama.
Menurut Syaifuddin, menjadi moderat diperlukan untuk mencari titik temu dari dua kutub ekstrem tersebut. Di satu sisi, ada praktik keagamaan yang mengakui kebenaran absolut dari interpretasi keagamaan yang disokong oleh kaum konservatif. Dan di sisi lain, ada juga kelompok agama ekstrem liberal yang mendewakan akal dengan mengabaikan kesucian agama. Keduanya—menurut Syaifuddin—perlu dimoderasi agar tidak menumbuhkan tafsir keagamaan yang memicu konflik.
Ide moderasi beragama ditulis dalam dua buku. Buku pertama berjudul “Moderasi Beragama” dianggap sebagai buku induk. Buku kedua berjudul “Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2022-2024” merupakan turunan dari buku pertama yang memuat langkah-langkah strategis dalam sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama. Kedua buku pedoman moderasi beragama itu, menurut tim peneliti dari ICRS dan PGI, masih mengandung gagasan dan/atau konsep yang kontraproduktif dengan cita-cita pemerintah untuk merayakan keberagaman/kemajemukan.
Kajian Kritis Ide Moderasi Beragama
Buku karya ICRS dan PGI ini menyoroti program Moderasi Beragama dari perspektif politik agama. Peneliti menemukan bahwa program ini masih menggunakan pendekatan institusional yang banyak difokuskan pada pembentukan pandangan keagamaan yang sejalan dengan agenda negara. Dalam hal ini moderasi beragama lebih merupakan agenda “religion making” oleh negara untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hal ini melegitimasi Kementerian Agama (sebagai aparatur negara) untuk memegang kendali atas interpretasi dan praktik keagamaan, serta menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak terkait agama. Dengan mempertimbangkan latar belakang munculnya ekstremisme, agenda moderasi keagamaan dapat dilihat sebagai soft power pemerintah untuk memberantas ekstremisme dan menjaga ‘ketertiban’ agama.
Contoh bagaimana pemerintah mengatur keyakinan dan praktik keagamaan dapat ditemukan dalam banyak kasus. Pada tahun 1961 misalnya, Departemen Agama berusaha untuk mendefinisikan agama sebagai sesuatu yang terpisah dari kepercayaan dan BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan) diberi wewenang untuk memantau pertumbuhan iman di Indonesia. Selama bertahun-tahun setelah pembentukan badan tersebut, komunitas agama yang tidak termasuk dalam definisi tersebut telah menjadi korban hukum karena tuduhan sesat agama.
Meski mengusung semangat apresiasi terhadap pluralitas, tim peneliti ICRS-PGI memandang program moderasi beragama belum sepenuhnya lepas dari paradigma kontrol semacam ini. Hal ini setidaknya terlihat dari pernyataan Syaifuddin sendiri dalam buku tersebut. Syaifuddin mengatakan bahwa dengan program moderasi beragama menunjukkan negara hadir dalam upaya internalisasi agama menjadi landasan moral dan spiritual kehidupan di satu sisi. Serta sebagai upaya menghargai keberagaman interpretasi agama dan kebenaran di sisi lain. Kehadiran negara dalam menginternalisasi nilai-nilai “moderat” tentu mengisyaratkan kontrol negara dalam agama. Program “moderasi” pemerintah berpotensi membatasi kebebasan beragama. Sebagaimana disebutkan dalam buku kedua moderasi beragama, tiga indikator moderasi antara lain: 1) pandangan, sikap, dan praktik keagamaan tidak merugikan nilai-nilai luhur kemanusiaan, 2) pandangan, sikap, dan praktik tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila dan UUD 1945), dan 3) pandangan, sikap, dan praktik tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman masyarakat dan negara untuk mewujudkan ketertiban sosial dan kemanfaatan bersama.
Persoalannya, seperti disampaikan Zainal Abidin Bagir saat peluncuran buku, infrastruktur hukum yang ada masih memberikan ruang yang memungkinkan terjadinya intoleransi. Keberadaan UU PNPS 1965 yang masih dilestarikan oleh negara merupakan contoh bagaimana program pengelolaan agama justru digerogoti oleh kebijakan pemerintah sendiri. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah telah membatasi hak minoritas dalam beribadah. Sehingga, tanpa adanya revisi terhadap kebijakan yang bermasalah, program moderasi beragama tidak akan membawa perubahan apapun pada kebebasan beragama.
Meski mengakui kelemahan program moderasi beragama, Alissa Wahid—seorang aktivis kemanusiaan yang juga terlibat dalam perumusan program tersebut—menyatakan bahwa inisiatif pemerintah untuk terlibat dalam penanganan ekstremisme dan intoleransi tetap harus diapresiasi dan didukung. Dalam tanggapannya atas buku yang ditulis oleh peneliti ICRS-PGI tersebut, ia juga mengaku khawatir dengan istilah “moderasi” yang berpotensi menimbulkan konflik. Namun, dia percaya apa yang lebih penting untuk dilakukan saat ini adalah mengatasi krisis. Indonesia menghadapi peningkatan ekstremisme dan intoleransi yang perlu segera direspon oleh pemerintah. Oleh karenanya, moderasi beragama harus dilihat sebagai inisiatif pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut. Moderasi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih inklusif, mampu melahirkan toleransi, perdamaian, dan kerukunan.
Dia menyayangkan bahwa keadaan yang mengganggu yang disebabkan oleh intoleransi beragama tidak dijelaskan secara memadai oleh buku yang diterbitkan ICRS dan PGI. Hal ini membuat tim peneliti tidak mampu melihat signifikansi program moderasi. Baginya, penting untuk memahami konteks di balik peluncuran program untuk bisa memahami logika moderasi. Intoleransi dan ekstremisme telah mempertaruhkan kehidupan harmoni warga negara Indonesia yang beragam, yang juga perlu disikapi dengan cara yang mempertimbangkan sifat Indonesia sebagai masyarakat yang sosiosentris. Meskipun penanganan ekstremisme cukup mendesak, Pendeta Jacky Manuputty mengingatkan bahwa penggunaan cara yang lebih hati-hati sama pentingnya untuk meminimalkan risiko. Program moderasi beragama sungguh bermasalah karena dirumuskan berdasarkan paradigma ketakutan yang mencurigai adanya perbedaan pendapat yang bertentangan dengan rezim. Hal ini semakin menimbulkan polemik dan reaksi yang tidak simpatik terhadap negara. Jarak warga dan negara semakin lebar karena program moderasi seolah-olah hanya milik Kementerian Agama. Ia belum memberi kesempatan kepada masyarakat dan para tokoh agama untuk terlibat dalam program tersebut.
Meski demikian, lanjut Pdt Manuputty, upaya pemerintah untuk merespon krisis multidimensi yang disebabkan oleh lemahnya penghargaan terhadap perbedaan harus didukung dengan sikap kritis. Meskipun buku utama tentang moderasi beragama masih memuat istilah-istilah kontroversial yang memancing polemik, buku kedua tentang roadmap program tersebut cenderung menghindari perdebatan dengan mengurangi penggunaan istilah-istilah ambigu “moderat”. Melainkan lebih fokus pada rencana strategis untuk mengubah pola pikir eksklusif agama menjadi lebih inklusif melalui enam bidang kehidupan: masyarakat, negara, pendidikan, politik, agama, dan media. Roadmap tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Agama berharap dapat menggunakan program “moderasi beragama” sebagai strategi budaya untuk membawa nuansa agama yang lebih moderat. Meskipun perubahan itu penting, namun harus dilakukan dengan hati-hati melalui cara yang demokratis untuk menghindari efek samping dari program-program seperti yang disebutkan sebelumnya.
Buku yang diluncurkan oleh ICRS dan PGI ini tidak bertujuan untuk mendelegitimasi program pemerintah untuk melindungi kebinekaan. Namun dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan perbedaan yang lebih baik sekaligus mengurangi campur tangan negara ke dalam agama. Program moderasi yang mencita-citakan kesetaraan kewarganegaraan ini perlu terus didukung melalui pengembangan konsep-konsep yang menekankan penghormatan terhadap pluralitas dan kebebasan beragama. Negara harus hadir dalam kehidupan warga negara, tetapi bukan dengan menjadi polisi iman yang mengatur keimanan warga negara. Negara harus hadir dalam kapasitasnya memberikan ruang yang aman bagi warganya untuk beribadah secara bebas tanpa ada intervensi apapun dengan mengeluarkan kebijakan yang melindungi kebebasan beragama warga negara.
—–
Tulisan ini dialihbahasakan oleh Ida Fitri (Peneliti ICRS) dari artikel Maurisa Zinira berjudul The Politics of Religious Moderation: A Critical Review yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di situs web ICRS.
Klik Rekaman Diskusi