Ringkasan:
● PBM 2006 kerap menjadi alat legal untuk menghambat pendirian rumah ibadah kelompok minoritas.
● KUHP Nasional 2023 memperkuat perlindungan hukum terhadap gangguan, kebencian, dan perusakan terkait ibadah.
● Perlindungan kebebasan beragama memerlukan reformasi kebijakan perizinan dan komitmen penegakan hukum.
Oleh: Risdo Simangunsong | Republikasi dari Jakatarub
Sebagaimana terjadi di banyak wilayah lain di Jawa Barat, permasalahan pendirian rumah ibadah merupakan tantangan tersendiri di Bandung Raya. Beberapa kasus bahkan memerlukan waktu penyelesaian hingga bertahun-tahun, dan hingga saat ini belum juga ditemukan solusi yang benar-benar memenuhi hak warga untuk beribadah. Jaminan konstitusi yang mengakui hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sering kali terbentur pada kenyataan di lapangan yang justru membatasinya.
Salah satu sumber ketegangan antara jaminan normatif dan praktik nyata adalah aturan perizinan pendirian rumah ibadah, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006). Regulasi ini diterbitkan dengan harapan dapat memelihara kerukunan umat beragama, tetapi pada tingkat implementasi, aturan tersebut acap kali justru menjadi pemicu konflik.
Dua Sisi PBM 2006
Aturan mengenai pendirian rumah ibadah dalam PBM 2006 sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, regulasi ini menetapkan syarat administratif yang cukup berat: harus terdapat minimal 90 nama pengguna rumah ibadah (jemaat) dan dukungan dari setidaknya 60 warga sekitar yang masing-masing disahkan oleh pejabat setempat, ditambah rekomendasi tertulis dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan dukungan lingkungan.
Namun, dalam praktiknya, syarat ini kerap dieksploitasi untuk menghambat kelompok agama minoritas. PBM 2006 justru dipandang sebagai “akar masalah” penolakan rumah ibadah karena aturan negara tersebut memberikan celah bagi kelompok intoleran untuk memobilisasi masyarakat setempat agar enggan memberikan dukungan. Alih-alih mempermudah, aturan “90/60” tersebut sering digunakan sebagai alasan “legal” untuk menolak keberadaan rumah ibadah.
Dalam catatan LBH Bandung, sejumlah aksi penolakan gereja di Bandung Raya—seperti yang terjadi di HKI Bandung Selatan, GKP Dayeuhkolot, Gereja Katolik Arcamanik dan Rancasari, serta beberapa tempat lainnya—menunjukkan bahwa aturan perizinan ini sering kali menjadi dalih para penolak. Demikian pula bagi aparat, aturan tersebut kerap dijadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap hak warga dalam beribadah. Aksi penolakan tersebut pun sering kali dibarengi dengan ujaran kebencian, gangguan, hingga perusakan terhadap bangunan serta peralatan yang digunakan untuk beribadah.
Perlindungan dalam KUHP Nasional
KUHP Nasional 2023 memberikan perspektif baru bagi perlindungan hak beribadah dan pendirian rumah ibadah. Pasal 300, misalnya, memperbarui delik penodaan agama menjadi delik kebencian berbasis SARA. Dalam pasal tersebut, siapa pun yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, mengungkapkan kebencian, atau menghasut untuk melakukan diskriminasi terhadap golongan berdasarkan agama atau kepercayaan dapat dipidana. Kelompok atau tokoh yang mengampanyekan penutupan gereja dengan dalih kebencian (misalnya “anti-pemurtadan”) kini dapat dijerat menggunakan pasal ini.
Selanjutnya, Pasal 303 mengancamkan pidana bagi siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan maupun orang yang sedang beribadah. Pasal ini secara tepat mengkriminalisasi tindakan vigilante atau aksi main hakim sendiri. Penyerbuan massa ke acara ibadah dan pemaksaan penutupan secara jelas memenuhi unsur “mengganggu atau membubarkan orang yang sedang beribadah” dengan ancaman kekerasan.
Selain itu, Pasal 305 mengatur sanksi bagi perusakan sarana ibadah: barang siapa menodai, merusak, atau membakar bangunan tempat ibadah atau benda suci dapat dipidana hingga 5 tahun. Aksi vandalisme seperti merusak kitab suci, simbol agama, atau peralatan ibadah secara normatif dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut. Secara garis besar, KUHP 2023 mencoba menutup kekosongan hukum lama dengan memberikan payung perlindungan yang lebih jelas bagi kelompok minoritas.
Apakah Masalah Selesai?
Pertanyaannya kemudian, dapatkah pasal-pasal ini diterapkan pada kasus penolakan rumah ibadah di Bandung Raya dan Jawa Barat secara umum? Dalam perspektif rule of law, jawabannya seharusnya adalah ya. Tindakan-tindakan intoleran yang pernah terjadi di masa lalu kini secara eksplisit masuk dalam kategori pidana. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen penegak hukum.
KUHP Nasional baru akan berlaku penuh pada tahun 2026 (setelah masa transisi tiga tahun sejak 2023), sehingga penindakan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum masa tersebut masih terbentur pada asas non-retroaktif (tidak berlaku surut). Meski demikian, jika saat ini kembali terjadi upaya penghalangan ibadah, polisi dan jaksa telah memiliki landasan kuat untuk menjerat pelakunya dengan Pasal 303 atau 305.
Di sisi lain, aturan mengenai perizinan rumah ibadah masih tetap sama. Akibatnya, kesulitan yang dihadapi kelompok minoritas, khususnya kelompok Kristiani di Bandung Raya, masih terbentur pada persoalan yang serupa.
Regulasi perizinan rumah ibadah memang perlu diperbarui. Ketentuan dalam PBM 2006, terutama syarat 90 jemaat dan 60 tanda tangan warga, sebaiknya ditinjau ulang agar lebih kontekstual dan tidak memberikan “hak veto sosial” kepada masyarakat setempat. FKUB juga harus bertindak lebih transparan dan akuntabel dalam proses pemberian rekomendasi; bahkan fungsinya perlu diarahkan sebagai fasilitator dialog, bukan penentu perizinan. Aparat daerah pun harus proaktif menyosialisasikan hak kebebasan beragama dan mendukung proses perizinan secara adil.
Sinergi antara reformasi kebijakan dan rekonsiliasi sosial sangatlah penting agar negara hadir sebagai pelindung konstitusional, bukan sekadar penengah pragmatis. Semangat perlindungan kebebasan beragama dalam KUHP Nasional hanya akan menjadi kuat jika kedua upaya tersebut berjalan beriringan.
*) Disarikan dari makalah: “Analisis Konflik Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM 2006 dan KUHP 2023” oleh Fajriatun Nisa Islami (MPRK UGM). Tulisan ini diterbitkan sebagai bagian dari kampanye PROTECT-JAKATARUB terkait Dampak KUHP Nasional terhadap Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Perlindungan Kelompok Marginal.
Editor: Andrianor










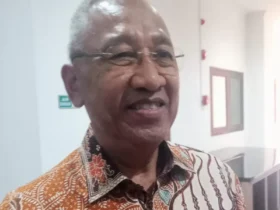

Leave a Reply